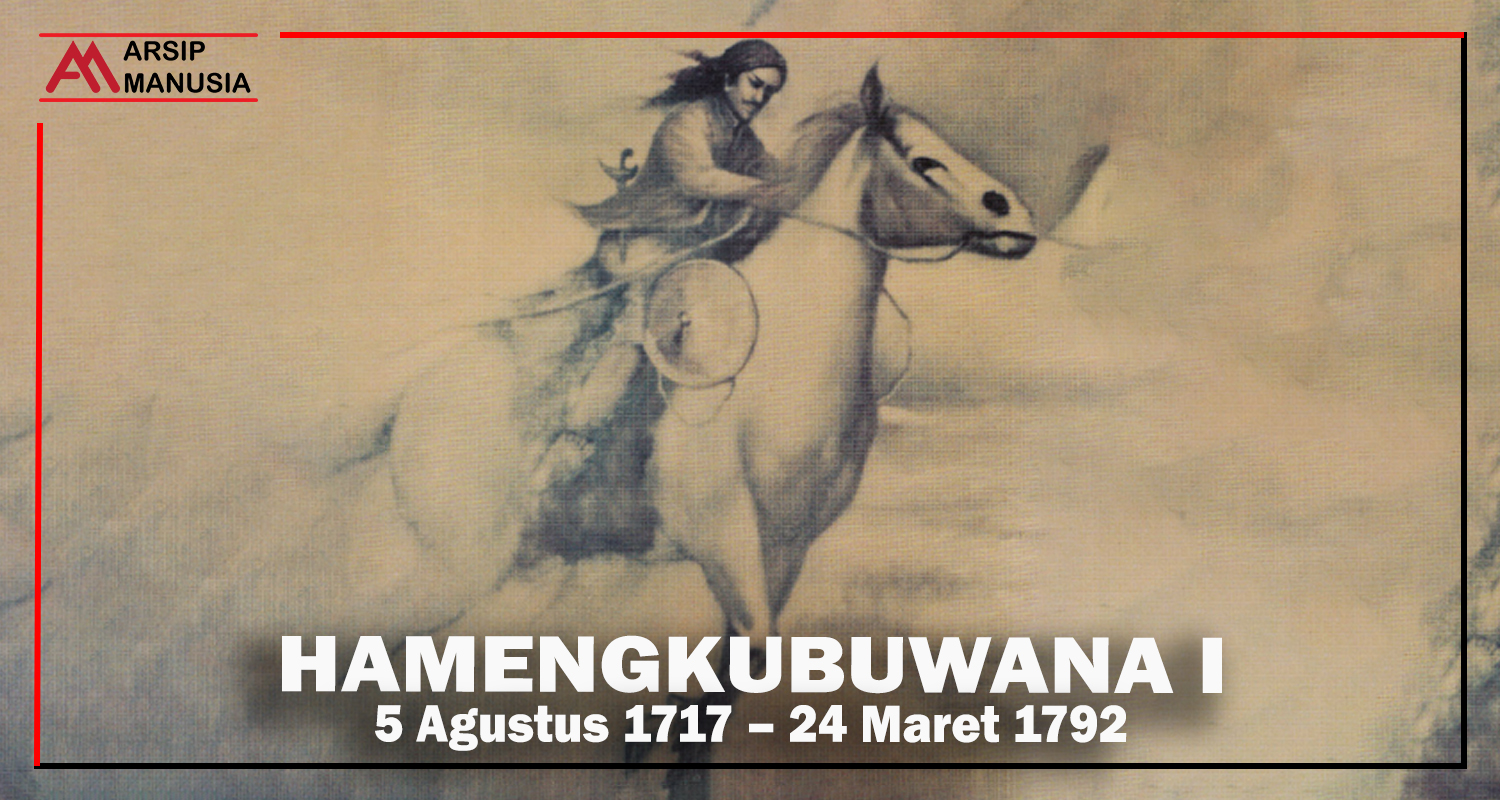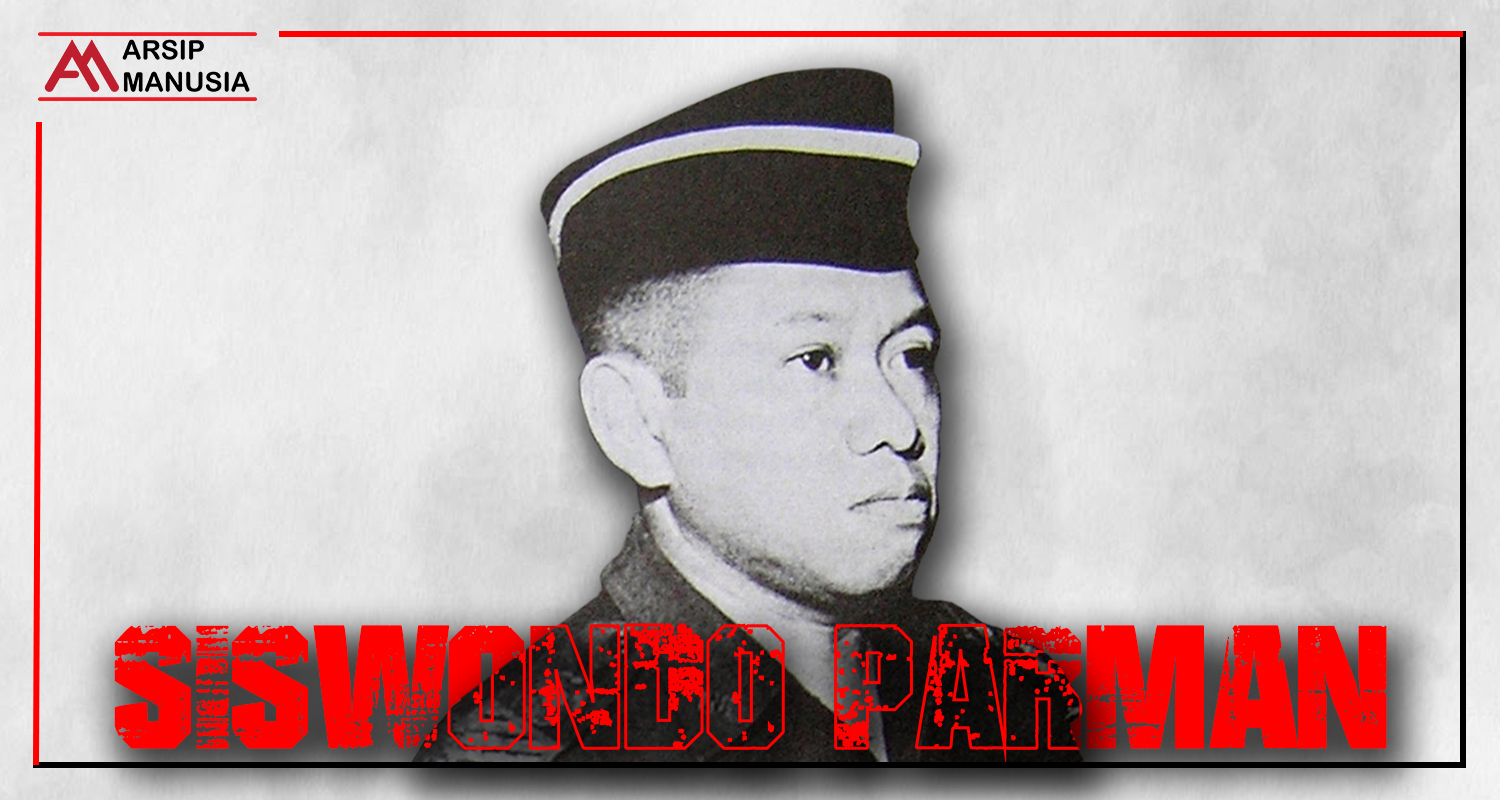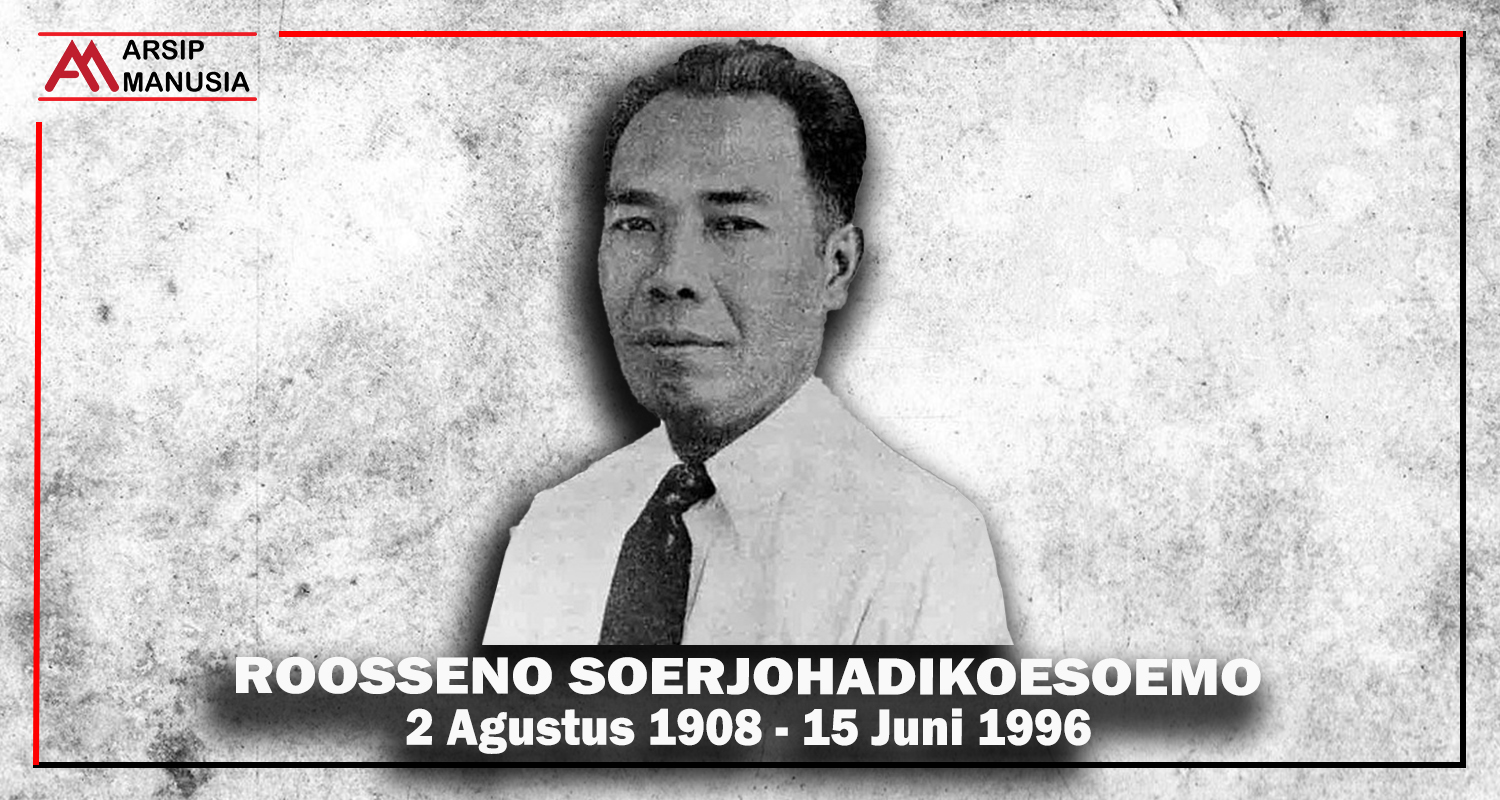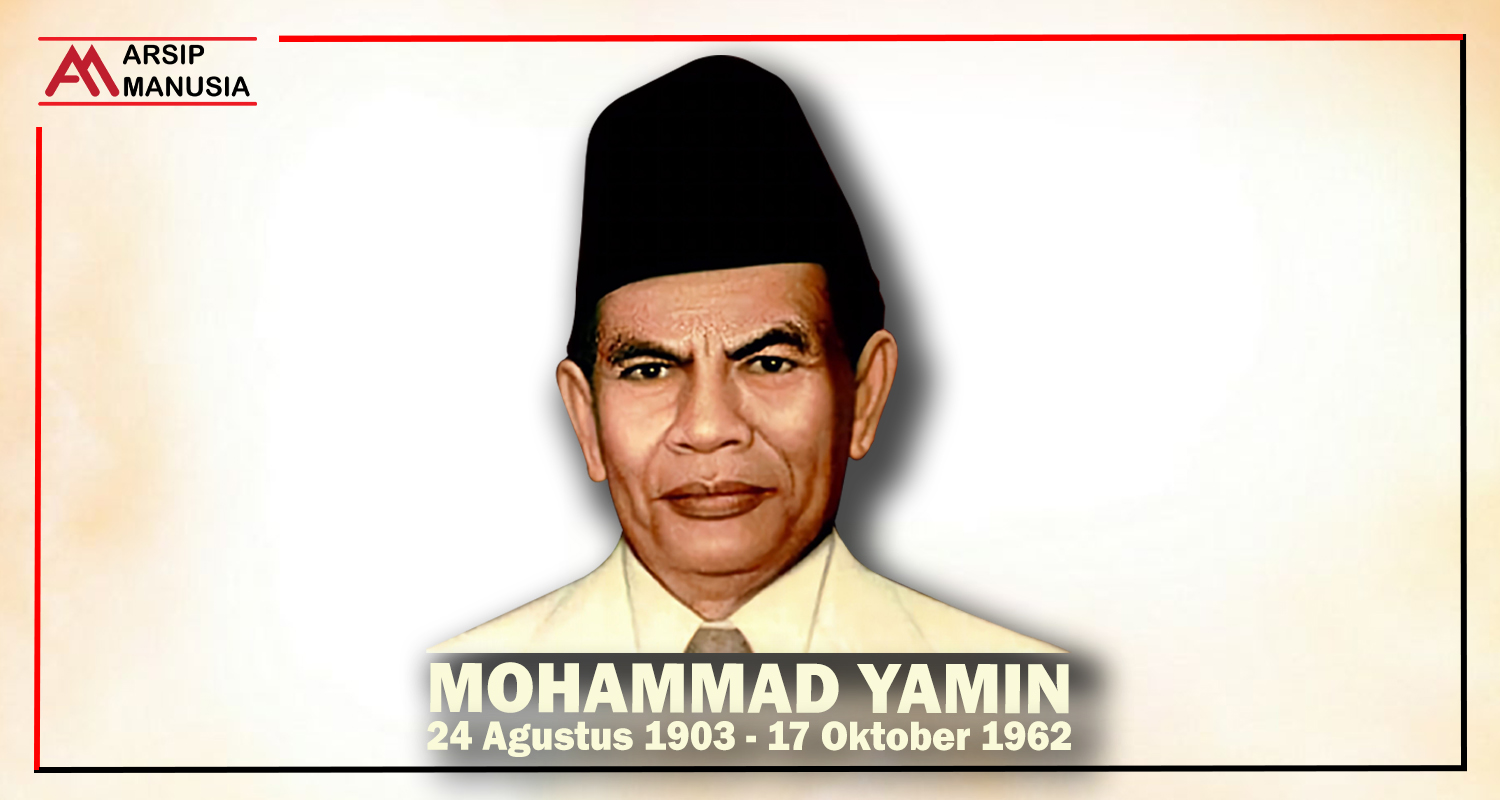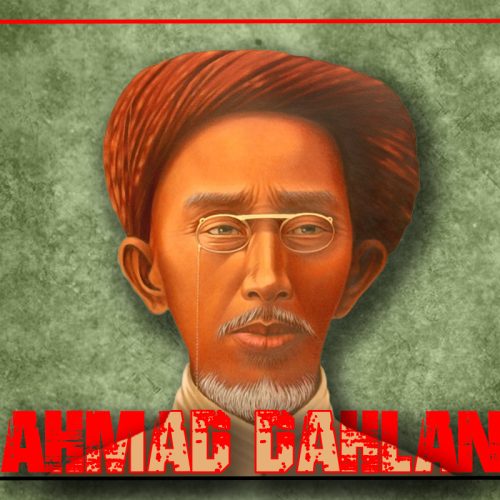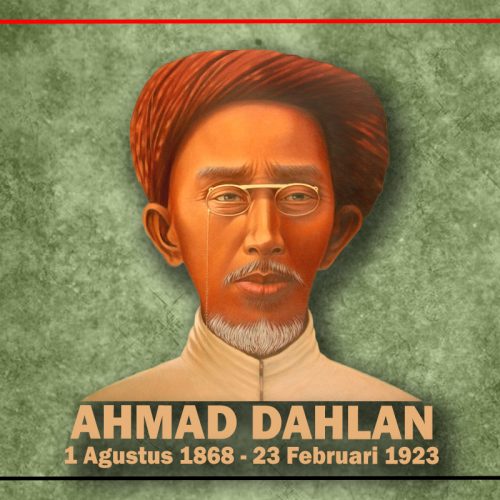Mohammad Yamin dikenal sebagai sastrawan, politikus, sejarawan, dan negarawan yang berperan besar dalam perjalanan bangsa menuju kemerdekaan. Yamin merupakan salah satu penggagas Sumpah Pemuda 1928, anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), serta tokoh yang terlibat dalam perumusan Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar 1945.
Selain kiprahnya di bidang politik, Yamin juga pernah menjabat berbagai posisi penting dalam pemerintahan, mulai dari Menteri Kehakiman, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, hingga Menteri Penerangan. Melalui karya dan gagasannya, ia turut membangun fondasi nasionalisme, bahasa persatuan, serta pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1973, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya.
Table of Contents
ToggleLatar Belakang Keluarga dan Masa Kecil
Mohammad Yamin lahir pada pukul 00.00, tanggal 23 Agustus 1903 di Sawahlunto, Sumatera Barat. Proses kelahirannya ditolong oleh seorang bidan bernama Hafsah. Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang cukup terpandang. Ayahnya, Usman bergelar Bagindo Khatib, bekerja sebagai Mantri Kopi atau Koffiepakhuismeester dengan tugas mengawasi perkebunan kopi beserta gudangnya. Ibunya bernama Siti Sa’adah, perempuan asal Padangpanjang.
Sejak kecil, Yamin tumbuh di lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan. Kakaknya, Yaman gelar Sutan Rajo Endah, berperan besar dalam membimbing Yamin dan saudara-saudaranya, termasuk tokoh pers terkenal Adinegoro. Lingkungan keluarga inilah yang kelak membentuk karakter Yamin sebagai sosok berpengetahuan luas, gigih, dan penuh semangat kebangsaan.
Pendidikan dan Pembentukan Karakter
Perjalanan pendidikan Mohammad Yamin tidak selalu berjalan mulus. Ia sering berpindah sekolah dan menyelesaikan masa belajarnya lebih lama dari anak-anak lain seusianya. Hal ini bukan karena ia tidak menyukai pelajaran, melainkan karena kondisi pendidikan di masa itu yang belum merata, ditambah sifat keras kepala Yamin yang hanya mau belajar di tempat sesuai dengan cita-citanya. Ia bahkan tidak segan meninggalkan sekolah bila merasa pelajaran atau lingkungannya tidak cocok dengan hatinya.
Pendidikan dasar pertamanya ditempuh di Sekolah Bumiputera Angka II, sebuah sekolah dengan bahasa pengantar Melayu dan lama belajar lima tahun. Pada masa itu, sekolah Angka II lebih populer dibandingkan Angka I yang kemudian berkembang menjadi Hollandsch-Inlandsche School (HIS). Yamin kemudian melanjutkan ke HIS. Karena sebelumnya ia sudah bersekolah di Angka II, Yamin tidak perlu memulai dari kelas awal. Ia akhirnya berhasil menamatkan pendidikan di HIS pada tahun 1918, dalam usia 15 tahun.
Saat menempuh sekolah dasar, Yamin tidak menetap di satu tempat. Ia sempat belajar di Talawi, Sawahlunto, Solok, hingga akhirnya menetap di Padangpanjang, di mana kakaknya turut membimbing pendidikannya. Dari sinilah minat Yamin terhadap ilmu pengetahuan, sastra, dan sejarah semakin terbentuk.
Setelah lulus HIS, Yamin sempat mencoba berbagai jalur pendidikan. Ia masuk Sekolah Dokter Hewan di Bogor, namun tidak menemukan ketertarikan. Ia lalu pindah ke Sekolah Pertanian (Landbouwschool), juga di Bogor, tetapi kembali merasa kurang cocok. Barulah ketika ia melanjutkan ke Algemene Middelbare School (AMS) Surakarta, jurusan Oostersch Letterkundige Afdeling (Kesusastraan Timur), Yamin merasa menemukan bidang yang sesuai. Di sekolah inilah ia mulai tekun belajar, hingga akhirnya berhasil menamatkan pendidikan pada tahun 1927.
Kehausannya terhadap ilmu pengetahuan mendorong Yamin melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi. Ia pindah ke Batavia (Jakarta) dan masuk ke Rechts Hogeschool (RHS) atau Sekolah Tinggi Hukum. Disiplin dan kesungguhannya membuat ia mampu menyelesaikan studi tepat waktu dan meraih gelar Meester in de Rechten (Mr.). Semasa kuliah, Yamin tinggal di Indonesisch Clubgebouw (IC) di Jalan Kramat Raya No. 106, Jakarta, bersama tokoh muda lain seperti Amir Sjarifuddin dan Sumanang.
Pendidikan yang berliku-liku ini membentuk karakter Yamin sebagai pribadi keras, gigih, dan berpikiran kritis. Ia selalu mencari jalan yang sesuai dengan cita-cita dan idealismenya, bahkan bila harus berpindah-pindah sekolah. Kelak, semangat ini pula yang ia bawa dalam perjuangan politik dan kebangsaan.
Pergerakan Pemuda dan Sumpah Pemuda
Perjalanan organisasi Mohammad Yamin dimulai sejak 1919 ketika ia bergabung dengan Jong Sumatranen Bond (JSB), sebuah organisasi pemuda asal Sumatera yang aktif dalam gerakan kebangsaan. Dari anggota biasa, Yamin berkembang menjadi pengurus, hingga akhirnya terpilih sebagai ketua JSB pada periode 1927–1928. Pengalamannya di organisasi ini menumbuhkan jiwa kepemimpinan sekaligus memperluas jejaring pergaulannya dengan tokoh-tokoh muda dari berbagai daerah.
Selain aktif di JSB, Yamin juga bergabung dengan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), sebuah organisasi yang berdiri pada 1926 setelah Kongres Pemuda I. PPPI membawa semangat persatuan nasional, sejalan dengan cita-cita Perhimpunan Indonesia di Belanda yang menginginkan kemerdekaan penuh bagi bangsa Indonesia.
Kongres Pemuda I (30 April – 2 Mei 1926, Jakarta)
Dalam forum ini, Yamin menyampaikan gagasan mengenai kemungkinan bahasa persatuan di masa depan. Menurutnya, bahasa Melayu dan bahasa Jawa memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa nasional, tentu dengan tetap menghargai bahasa daerah lain. Meskipun belum menghasilkan ikrar persatuan, Kongres Pemuda I menegaskan cita-cita menuju satu bangsa dan satu bahasa.
Kongres Pemuda II (27–28 Oktober 1928, Jakarta)
Pada peristiwa inilah lahir ikrar bersejarah yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Yamin berperan dalam penyusunan naskah ikrar tersebut, khususnya penegasan mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yang berasal dari bahasa Melayu. Ikrar ini kemudian menjadi tonggak kebangkitan nasionalisme Indonesia.
Karier Politik dan Perjuangan Kemerdekaan
Setelah aktif di berbagai organisasi kepemudaan, Mohammad Yamin semakin terlibat dalam dunia politik dan pergerakan kemerdekaan. Ia tidak hanya dikenal sebagai sastrawan dan intelektual, tetapi juga sebagai seorang politisi yang pandai berpidato, berpolemik, dan menyampaikan gagasan kebangsaan.
Pada masa pendudukan Jepang, Yamin dipercaya menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Di forum inilah, Yamin tampil sebagai salah satu tokoh penting yang mengemukakan pandangan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Pada sidang 29 Mei 1945, ia menyampaikan usulan mengenai lima asas dasar negara, yaitu:
- Peri Kebangsaan
- Peri Kemanusiaan
- Peri Ketuhanan
- Peri Kerakyatan
- Kesejahteraan Rakyat
Usulannya ini kemudian dikenal sebagai salah satu gagasan awal perumusan dasar negara, meski kemudian mengalami penyempurnaan melalui Piagam Jakarta dan akhirnya menjadi Pancasila. Yamin juga turut berperan dalam penyusunan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bersama tokoh-tokoh lain seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan Soepomo.
Setelah Indonesia merdeka, kiprah Yamin di bidang politik semakin menonjol. Ia aktif dalam organisasi, parlemen, hingga pemerintahan. Pandangan nasionalismenya membuat Yamin sering terlibat dalam perdebatan besar mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan, serta arah pembangunan bangsa.
Kecakapannya dalam bidang hukum, politik, dan sejarah menjadikan Yamin dihormati sebagai intelektual sekaligus negarawan. Ia juga dikenal gigih memperjuangkan persatuan Indonesia dengan tetap menghargai keragaman budaya, bahasa, dan agama.
Menteri dan Negarawan
Setelah proklamasi kemerdekaan, Mohammad Yamin dipercaya menduduki berbagai jabatan penting di pemerintahan Republik Indonesia. Karier politiknya berkembang pesat berkat kecakapan intelektual, kemampuan retorika, serta pemahamannya yang mendalam tentang hukum dan sejarah bangsa.
Dalam masa jabatannya sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (1953–1955), Yamin berupaya memperkuat fondasi pendidikan nasional. Ia mendorong sistem pendidikan yang berakar pada budaya bangsa, sekaligus membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Yamin juga menaruh perhatian besar pada pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi pendidikan.
Menteri Kehakiman (1958–1959), Yamin berusaha membangun sistem hukum yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ia dikenal kritis terhadap pengaruh hukum kolonial yang masih kuat, dan mendorong lahirnya sistem hukum nasional.
Sebagai Menteri Penerangan (1962–1963), Yamin memandang media massa sebagai sarana strategis untuk memperkuat persatuan nasional dan menyebarkan nilai-nilai kebangsaan. Ia juga menekankan pentingnya kebudayaan dalam membangun jati diri bangsa.
Selain menjabat di kabinet, Yamin juga aktif sebagai anggota parlemen dan berbagai forum kebangsaan. Pandangannya kerap menuai perdebatan, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ia adalah seorang pemikir yang berpengaruh dalam menentukan arah perjalanan bangsa.
Karya Sastra, Sejarah, dan Pemikiran
Selain dikenal sebagai politisi dan negarawan, Mohammad Yamin juga merupakan seorang sastrawan dan sejarawan yang produktif. Ia meninggalkan banyak karya tulis yang berpengaruh dalam perkembangan kebudayaan, sastra, dan historiografi Indonesia.
Yamin adalah salah satu pelopor sastra modern Indonesia. Ia memperkenalkan gaya penulisan baru dengan penggunaan bahasa Indonesia yang lebih terstruktur dan penuh semangat kebangsaan. Beberapa karya puisinya yang terkenal antara lain:
- Tanah Air (1922) – kumpulan puisi yang menegaskan kecintaan pada tanah kelahiran.
- Indonesia, Tumpah Darahku (1928) – karya yang sangat erat kaitannya dengan lahirnya Sumpah Pemuda.
- Bahasa, Bangsa – karya yang menekankan pentingnya bahasa sebagai identitas nasional.
Melalui karya-karyanya, Yamin berusaha membangkitkan kesadaran nasional di kalangan pemuda. Puisinya tidak hanya bernilai sastra, tetapi juga sarat dengan semangat perjuangan.
Selain menulis sastra, Yamin juga menekuni bidang sejarah. Ia menulis banyak buku dan esai mengenai asal-usul bangsa Indonesia, kerajaan-kerajaan Nusantara, serta tokoh-tokoh besar dalam sejarah. Beberapa karyanya di bidang sejarah antara lain:
- 6000 Tahun Sang Merah Putih
- Gajah Mada: Pahlawan Persatuan Nusantara
- Sedjarah dan Perdjoangan Bangsa Indonesia
Dalam karyanya, Yamin menekankan pentingnya persatuan dan kesadaran sejarah. Ia melihat bahwa bangsa Indonesia memiliki akar peradaban yang panjang dan harus dihargai sebagai modal dalam membangun masa depan.
Pemikiran Yamin berfokus pada persatuan nasional, kebudayaan, dan kemandirian bangsa. Ia meyakini bahwa bahasa, sejarah, dan kebudayaan merupakan unsur utama yang mempersatukan Indonesia. Pandangan ini sangat berpengaruh pada lahirnya Sumpah Pemuda dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
Akhir Hayat
Mohammad Yamin wafat pada 17 Oktober 1962 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Jakarta karena sakit yang dideritanya. Jenazahnya dimakamkan di tanah kelahirannya di Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat.
Untuk menghormati jasanya, Mohammad Yamin dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan Surat keputusan nomor 71/RHS/Sekj/Dpk/ 1973 dan bertanggal 3 September 1973. Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan, gedung, dan lembaga pendidikan di berbagai daerah.
Sumber:
- Kutoyo, Sutrisno “Prof. H. Muhammad Yamin S.H.” Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1982.
- Yasin, Nirwan, dan Lagut Bakaruddin. “Sumbangan Pemikiran Muhammad Yamin dalam Sejarah Indonesia.” *Al Ma’arief: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, vol. 2, no. 1, 2020, pp. 17–21. Universitas Jambi. Diakses 19 Agustus 2025.
- “Mohammad Yamin, Prof., S.H.” ikpni.or.id (diakses pada 19 Agustus 2025)
Diperbaharui pada tanggal 20 Agustus 2025