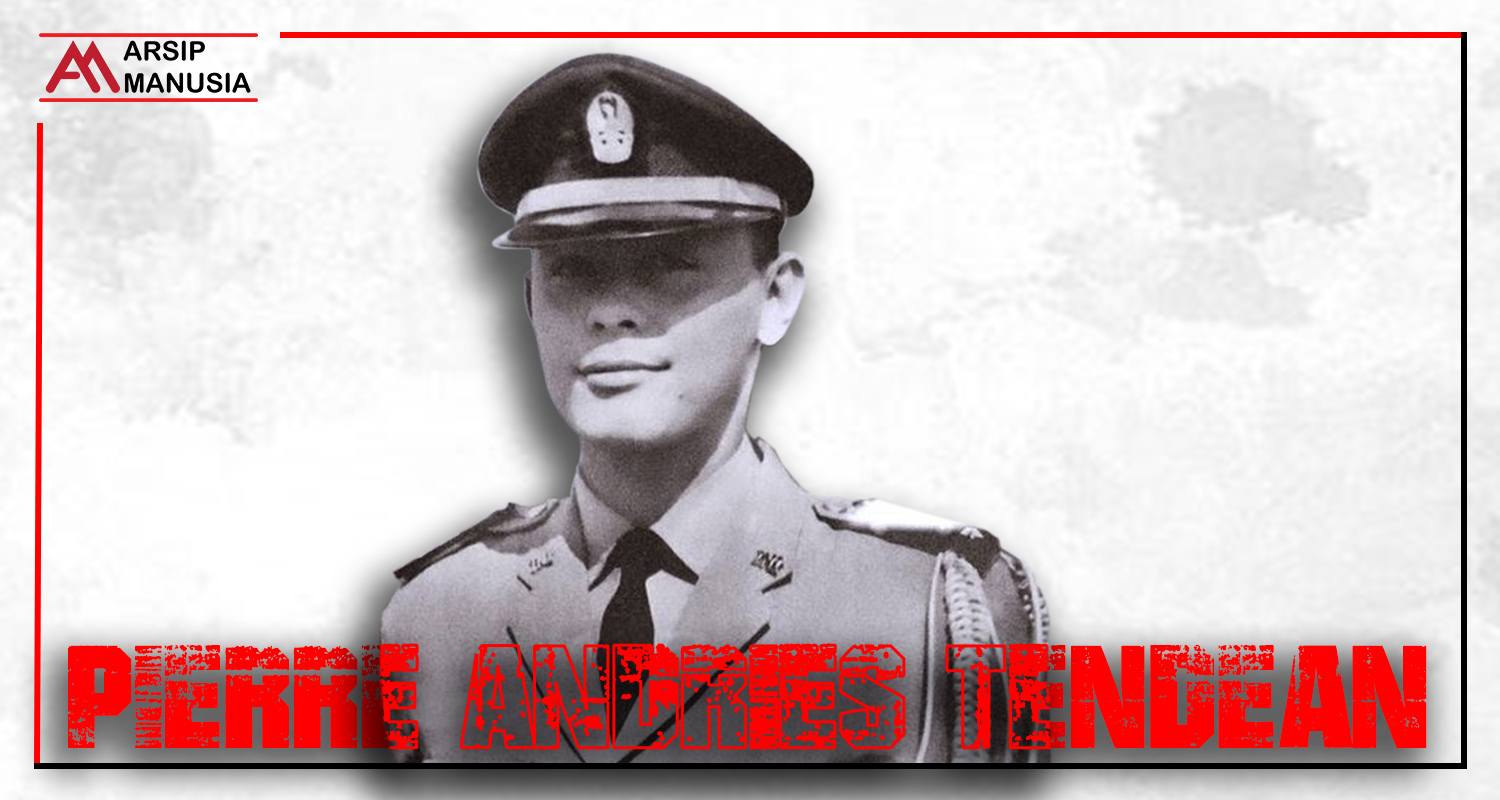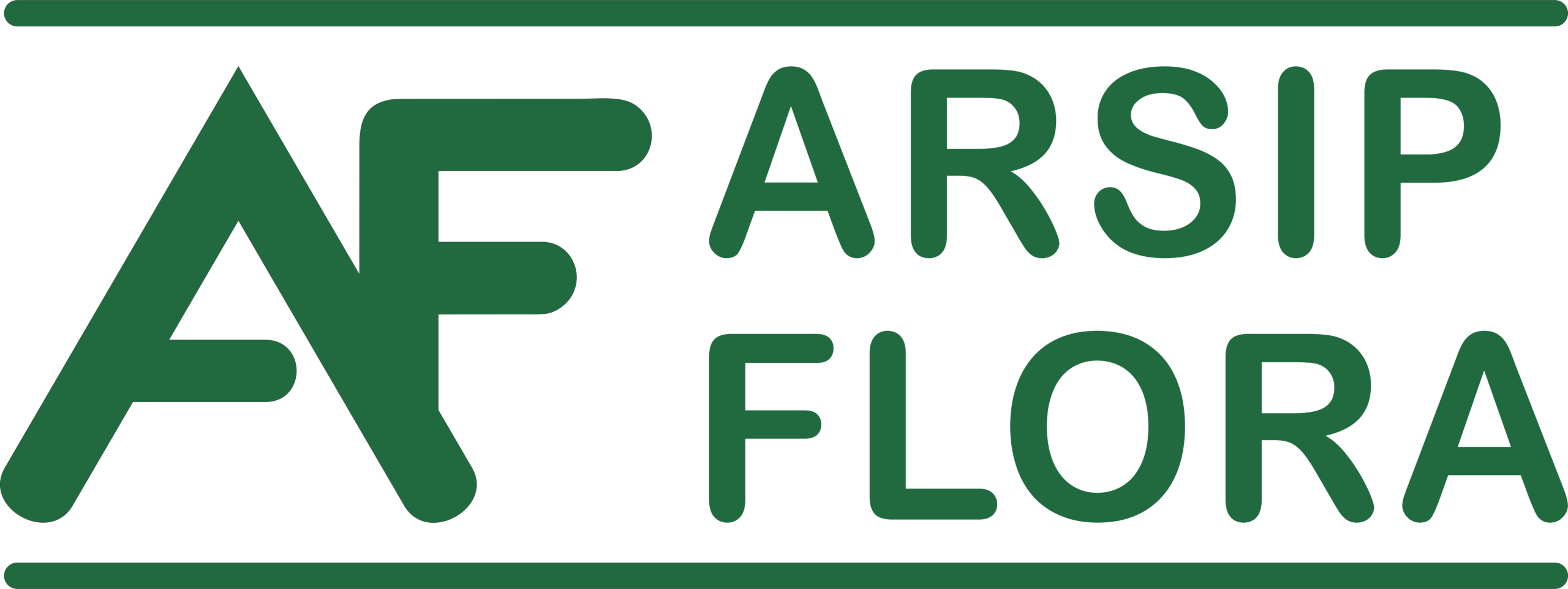Sebelum tercapainya proklamasi kemerdekaan RI, situasi tegang terjadi saat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, meninggalkan Indonesia dalam keadaan status quo. Pemberitaan ini mendorong golongan muda untuk mendesak percepatan pelaksanaan proklamasi guna memanfaatkan momentum berharga. Meski demikian, golongan tua menolak langkah tersebut, memilih agar tindakan tersebut tidak diambil dengan gegabah, yang berpotensi berakibat fatal.
Ketegangan antara kedua golongan tersebut tidak dapat dihindari dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan. Penculikan tokoh-tokoh penting, seperti Soekarno dan Moh Hatta, terjadi, menyebabkan suasana semakin memanas. Sementara golongan muda terus menekan untuk tindakan segera, golongan tua tetap kukuh menunggu kepastian.
Dalam situasi tegang itu, Achmad Soebardjo memainkan peran penengah. Ia mengusulkan agar dua tokoh penting, yaitu Soekarno dan Moh Hatta, dijemput terlebih dahulu untuk memungkinkan pelaksanaan proklamasi. Bahkan, ia bersedia menggunakan nyawanya sebagai jaminan kepada golongan yang mendesak, jika proklamasi gagal dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Table of Contents
ToggleMasa Muda dan Pendidikan Achamd Soebardjo
Achamd Soebardjo lahir di Teluk Jambe, Karawang, sebuah desa di tepi Sungai Cimanuk (Jawa Barat) pada tanggal 23 Maret 1896. Kakek buyutnya, H. Muhammad Usman, seorang pejuang perang Aceh dari Pidie, meninggalkan Aceh karena merasa tidak aman dikejar-kejar oleh aparatus pemerintah kolonial Belanda dan persaingan internal kelompok pejuang.
Pada tahun 1840, Teuku Usman dan pengikutnya tiba di perairan Indramayu, pantai utara pulau Jawa dengan perahu layer. Namun, topan menghantam perahu mereka dekat pantai Indramayu, menyebabkannya hancur. Mereka menyelamatkan diri dan terdampar di Pantai Panganjang di tepi Sungai Cimanuk.
Di situlah Teuku Usman mendirikan pesantren, menikahi seorang gadis, dan memiliki tiga anak: Teuku Saleh, Abdul Karim, dan Cut Aminah. Abdul Karim kemudian menikahi Wardinah, putri seorang pedagang kayu bernama Haji Husein, dan pindah ke kota Indramayu.
Tetapi, Abdul Karim tidak lama menetap di sana. Ia dipilih menjadi Khatib Masjid Jatibarang. Dari pernikahannya, ia memiliki lima anak: Teuku Jusuf, Ismail, Mujenal, Muchsan, dan Sidua. Setelah Abdul Karim meninggal di Jatibarang, istrinya pindah ke Indramayu lalu ke Teluk Agung, 4 KM dari kota Indramayu.
Anak-anak laki-lakinya disekolahkan di pesantren, sementara anak perempuan dan bungsu mereka tinggal bersama ibunya. Teuku Jusuf, ayah dari Achmad Soebardjo, dikenal di Indramayu sebagai Qori yang mahir membaca Al-Quran dengan suara merdu.
Kebiasaan ini sering membuatnya diundang oleh Husli Wedena (camat Teluk Agung Indramayu) yang dulunya adalah santrinya di pesantren di Surabaya, sebelum melanjutkan studinya di Belanda yang membawanya menjadi seorang kader pamong praja.
Achmad Soebardjo dilahirkan saat ayahnya sudah menjabat sebagai Mantri Polisi Pamong Praja (Sekretaris Kecamatan) Teluk Jambe. Teuku Jusuf, sebagai Pejabat Daerah, memiliki hak untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah Belanda.
Karena tidak ada sekolah Belanda di Karawang, Soebardjo dan kakak-kakaknya mondok di Batavia, bersekolah di tiga sekolah berbeda: Europeesche Lagere School-ELS di Kwitang, ELSB di Pasar Baur, dan kemudian Prince Hendrik School (Sekolah Pangeran Hendrik), serta sekolah Koning William III (KW III) di Salemba, yang merupakan sekolah tempat berkumpulnya para pemimpin Indonesia dari berbagai suku bangsa.
Selama di sekolah itu, Soebardjo gemar membaca buku. Buku yang paling berkesan baginya adalah “Max Havelaar” karya Douwes Dekker, yang menulis dengan nama samaran Multatuli. Buku ini mengungkapkan ketidakadilan penguasa Belanda dan pribumi terhadap rakyat.
Di sekolah tersebut, Soebardjo berteman dengan Max Maremis, mereka berlatih musik klasik bersama. Artikel pertama yang mempengaruhi kesadarannya terhadap politik adalah “Een Eereschuld” (Hutang Budi) karya Van Deventer, yang menyoroti peningkatan kesejahteraan pendidikan pribumi agar mereka dapat terlibat dalam berbagai bidang pekerjaan.
Kesadaran politik dan kebangsaannya semakin berkembang setelah peristiwa besar, yaitu perayaan 100 tahun kebebasan Belanda dari Perancis. Perayaan itu terganggu oleh sebuah tulisan berjudul “Als ik een Nederland was…” (Seandainya aku orang Belanda…) yang ditulis bersama tiga anggota Indische Partij, Suwardi Suryaningrat, Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, dan E.F.E. Douwes Dekker.
Soebardjo menyelesaikan pendidikannya di HBS Koning Willem III (KW III) pada tahun 1917 dan bergabung dengan Tri Koro Darmo di bawah Boedi Utomo. Selama Perang Dunia I, gerakan nasional Indonesia tumbuh pesat. Sarikat Islam, sebuah organisasi politik yang menggabungkan ideologi Islam-Nasional di bawah pimpinan Hadji Oemar Said Tjokroaminoto, menjadi dominan.
Pengaruh Tjokroaminoto dalam pidatonya tentang kebangsaan dan keagamaan sangat memukau Soebardjo. Setelah perang, Soebardjo melanjutkan studinya ke Belanda dan bertemu dengan Ibrahim Datuk Tan Malaka. Pulang ke Belanda untuk sekolah guru, Soebardjo juga bertemu dengan Sneevliet, pendiri Partai Buruh Belanda yang kemudian menjadi PKI.
Pada tahun 1908, mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan Indische Vereniging, yang menurut Soebardjo dipengaruhi oleh kemenangan Jepang atas Rusia yang dianggap sebagai manifestasi nasionalisme Asia. Organisasi ini awalnya bertujuan untuk memajukan kepentingan dan persaudaraan mahasiswa Indonesia di Belanda, kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia (P.I).
Soebardjo awalnya memimpin P.I. tetapi kemudian digantikan oleh Dr. Soetomo pada tahun 1920, lalu Mohammad Hatta menjadi ketuanya sampai tahun 1931 setelah dipilih dalam rapat bersama Soekiman.
Kongres Anti Imperialisme
Pada bulan Februari tahun 1927, diadakan Kongres Anti Imperialisme di Brussel. Tindakan pemerintah kolonial terhadap aksi aksi pembebasan dianggap telah melampaui batas kemanusiaan dan keadilan oleh komunitas Anti Imperialisme global. Fokus kongres ini adalah strategi melawan kekuatan imperialisme dan kolonialisme.
Di Brussel, utusan dari 21 negara yang mewakili beragam organisasi politik, ekonomi, dan buruh di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika telah berkumpul. Kongres tersebut berlangsung selama lima hari, dari tanggal 5 hingga 10 Februari 1927.
Perwakilan dari daerah jajahan Inggris meliputi Jawaharlal Nehru (India), Nafez Ramadan Bey (Mesir), dan Mashur Baqaf Sakri (Suriah), sedangkan dari jajahan Perancis ada Chodli Ben Mustafa. Hindia Belanda diwakili oleh Mohammad Hatta sebagai Ketua, serta Semaun (tokoh PKI), Galat Tarunamihardja, Muhammad Nazir Datuk Paniontjak, dan Achmad Soebardjo dari Perhimpunan Indonesia.
Hasil utama kongres ini adalah pembentukan League Against Imperialisme and For National Independence (Liga Anti Imperialisme untuk Kemerdekaan Nasional) dan pembentukan sekretariat permanen di Berlin. Pemerintah Belanda sangat tidak senang dengan partisipasi mahasiswa Indonesia dalam gerakan ini.
Polisi Belanda segera menangkap Mohammad Hatta, ketua P.I., bersama tiga orang lainnya: Muhammad Nazir Datuk Pamontjak, Ali Satroamidjojo, dan Abdul Madjid Djojoadiningrat untuk diadili. Achmad dan Arnold Mononutu tidak ditangkap karena mereka berada di luar negeri Belanda, tengah melakukan kunjungan ke Rusia dan Perancis.
Pergerakan di Tanah Air
Setelah tujuh tahun berdedikasi dan berjuang di organisasi P.I. di negeri Belanda, pada bulan April 1934, Soebardjo kembali ke tanah air. Setelah menyelesaikan studi hukumnya, dia menentukan arah karier. Meski banyak lowongan jabatan di pemerintahan Hindia Belanda yang terbuka lebar bagi orang berpendidikan tinggi, hati nuraninya sebagai mantan aktivis P.I. menolak bekerja pada pemerintah kolonial.
Akhirnya, ia memilih bekerja di sektor swasta di Kantor Bantuan Hukum milik Mr. Sastro Muljono, yang merupakan senior di Semarang. Banyak mantan anggota P.I. yang bekerja di pemerintahan, seperti Dr. Buntaran Martoatmodjo dan Dr. Achmad Mochtar di Semarang. Setelah itu, Soebardjo pindah ke Surabaya untuk bekerja di Kantor Bantuan Hukum milik Mr. Iskaq (Tjokro Hadisoerjo).
Di tahun-tahun itu, Soebardjo menyaksikan perlambatan perjuangan nasional. Para tokoh seperti Ir. Soekarno, Sartono, dan Mohammad Hatta memiliki perbedaan pendapat mengenai strategi perjuangan, meski memiliki dasar yang sama dalam konsep Non Kooperasi.
Partai Nasional Indonesia terpecah menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama ingin tetap berjuang secara bawah tanah, mayoritas mantan anggota Serikat Rakyat dan PRI. Kelompok kedua di bawah pimpinan Mr. Sartono memilih perjuangan melalui organisasi politik dalam bentuk partai yang lebih efektif, yang kemudian membentuk Partai Indonesia (Partindo) yang moderat. Kelompok ketiga mendirikan partai baru, Pendidikan Nasional Indonesia, yang didorong oleh Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir. Soebardjo bertemu mereka secara pribadi, mendekati Soekarno, Sartono, dan Hatta.
Namun, pergerakan nasional terhenti akibat kebijakan politik Gubernur Jenderal P.C. De Jonghe. Soebardjo memilih untuk tidak bergabung dengan kelompok manapun, meskipun pemerintah Hindia Belanda mencurigainya sebagai komunis. Ia merasa selalu diamati oleh Politicks Inlichtingen Drenst (P.I.D) atau Dinas Penyelidik Politik dari Kepolisian Hindia Belanda.
Pada tahun 1935, Soebardjo meninggalkan kantor pengacara Mr. Iskaq di Surabaya, pindah ke Malang untuk membuka kantor pengacara sendiri dan menjauhkan diri dari aktivitas politik. Namun, kantor pengacaranya tidak sukses karena kalah bersaing dengan kantor-kantor lain yang sudah ada lebih dulu. Ia jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit Soekoen.
Saat belum pulih sepenuhnya, ia mendapat surat dari Mr. Soedjono di Tokyo, yang memintanya berkunjung ke Jepang. Soebardjo yang merasa terjepit, melihat surat Soedjono sebagai berkah. Meski berencana mencari pekerjaan di Jepang, kendalanya adalah ia tidak memiliki simpanan yang cukup untuk bertahan hidup.
Akhirnya, pada bulan September 1935, ia pergi ke Jepang bersama keluarga kakaknya. Di Tokyo, ia terkesan dengan kemajuan Jepang. Dengan bantuan Soedjono, Soebardjo diperkenalkan dengan para cendekiawan Jepang dan mendapat penghasilan dari ceramah umum di beberapa organisasi.
Ia juga kagum dengan kemampuan bahasa beberapa cendekiawan Jepang yang mumpuni. Namun, hubungan ini memperlihatkan ketertarikan mereka dalam penelitian yang intensif tentang Hindia Belanda, bahkan hingga nama-nama Kepala Distrik, yang diketahuinya ketika tentara Jepang baru memasuki Indonesia.
Soebardjo kembali ke tanah air pada bulan September 1936, memilih Bandung sebagai tempat tinggalnya yang baru. Ia fokus sebagai pengacara, menjauh dari kegiatan politik, namun tetap merasa terpantau oleh P.I.D. Setelah setahun di Bandung, ia memiliki penghasilan yang stabil. Kegemarannya menulis kembali muncul saat bertemu dengan wartawan senior bernuansa sosialis, Mr. D. M. G. Koch, yang membantunya menulis sejumlah artikel.
Di samping aktivitas pengacaraannya, Soebardjo juga terlibat dalam mendirikan Asrama Indonesia Merdeka di Jalan Gunung Sahari, Gedung Dai San ka, bersama para pemuda. Asrama ini berhasil menyelenggarakan berbagai kegiatan tanpa intervensi dari pihak Jepang.
BPUPKI
Berdasarkan janji Koiso, BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada Maret 1945 untuk menyusun konstitusi negara Indonesia yang akan merdeka. Hampir semua tokoh pergerakan ditunjuk sebagai anggotanya, dengan total 61 orang yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat.
Soebardjo terpilih sebagai anggota nomor 42. Dia menekankan peran penting Soekarno dalam merumuskan pandangan hidup rakyat Indonesia yang tercermin dalam sila-sila Pancasila. Diskusi difokuskan pada teori-teori yang bisa menjadi dasar negara Indonesia: individualisme, kelas, dan negara kesatuan.
Setelah debat dan pertukaran gagasan, Soekarno membentuk panitia sembilan orang yang dikenal sebagai panitia 9. Soebardjo membawa gagasan dari Kongres Anti Imperialisme di Brussel pada 1927 yang menuntut penghapusan imperialisme dan kolonialisme.
Gagasan lain termasuk penentuan nasib sendiri yang diilhami oleh Woodrow Wilson pada 1917, yang kemudian menjadi bagian pertama dari rancangan pembukaan konstitusi. Panitia 9 mengalami kesulitan dalam menyatukan ideologi nasionalis dan konsep Islam tentang negara dan masyarakat.
Sidang kedua Panitia 9 pada Juli 1945 memutuskan:
- Menolak teori individualisme karena berpotensi menciptakan penindasan dan politik ekspansionis.
- Menolak teori Karl Marx, Engels, dan Lenin karena tidak sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia.
- Menolak bentuk negara Islam karena tidak memisahkan negara dan agama, meski Indonesia mayoritas beragama Islam; toleransi beragama berdasarkan Pancasila menjadi jalan untuk kehidupan yang damai.
Terakhir, panitia menerima teori Negara Kesatuan yang dikemukakan oleh Adam Muller dan Hegel pada abad ke-18 hingga ke-19. Teori ini menekankan bahwa negara bukan hanya menjaga kepentingan individu atau kelompok, melainkan juga masyarakat sebagai kesatuan organik yang saling terkait erat.
Soebardjo menyoroti perang yang sedang berlangsung pada pertengahan tahun 1945 yang menghalangi diskusi mendalam tentang bagian-bagian dalam rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Meskipun demikian, Badan Penyelidik berhasil menyelesaikan rancangan secara utuh pada bulan Juli 1945.
Peristiwa Rengasdengklok
Pada tanggal 15 Agustus 1945, Soebardjo bergabung dengan sejumlah tokoh dan penduduk Jakarta untuk menyambut kedatangan Dr. Radjiman, Soekarno–Hatta di Bandar Udara Kemayoran. Selain mereka, Teuku Moh. Hassan, Dr. Amir, dan Abas turut serta dalam rombongan Radjiman, mewakili Sumatera dalam PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Ketika turun dari pesawat, Soekarno memberikan pidato ringkas, “Sebelumnya, saya menyatakan bahwa Indonesia akan merdeka sebelum tanaman jagung berbuah. Sekarang saya katakan bahwa Indonesia akan merdeka sebelum tanaman tersebut berbunga.”
Pada 15 Agustus 1945, di Jakarta, beredar kabar bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Soekarno dan Hatta berupaya memeriksa kebenaran rumor itu dengan pergi ke sunseikanbu (Kantor Pemerintahan Militer). Tanpa menemui Jenderal Yamamoto Moichiro, pejabat Jepang yang dituju, mereka kemudian mendatangi kantor Soebardjo untuk mencari informasi.
Soebardjo menyarankan mereka untuk mendapatkan konfirmasi dari Laksamana Maeda. Bersama-sama, mereka bertemu Maeda, yang tidak memberikan jawaban pasti terkait desas-desus tersebut. Setelah meninggalkan kantor Maeda pada sore hari, mereka belum mendapat kepastian.
Meski Soebardjo masih ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas, mereka memiliki tugas mendesak: membahas sidang Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 16 Agustus 1945 yang akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Negara oleh BPUPKI.
Soebardjo menduga informasi yang mereka cari masih dianggap rahasia oleh Laksamana Maeda karena jabatannya dan sumpahnya. Ia mencoba menghubungi bawahannya di kantor Kaigan Bukanbu, tapi tidak mendapat jawaban. Pada sore hari, Soebardjo bertemu dengan Dr. Buntara dan Iwa Kusuma Sumantri di asrama mereka, yang juga tidak bisa memberikan informasi.
Mereka kemudian mendatangi Soekarno malam itu bersama Hatta, diterima pada pukul 11 malam. Soekarno dikelilingi oleh sejumlah pemuda termasuk Wikana, yang mendesak proklamasi kemerdekaan malam itu juga dengan nada mengancam. Soekarno menolak karena itu harus dibahas di sidang PPKI. Wikana diingatkan oleh Hatta, namun drama itu terus berlanjut hingga malam hari.
Pada tanggal 16 Agustus 1945, tepat pukul 08.00, Soebardjo mendapat laporan dari sekretarisnya, Embah Soediro, bahwa Soekarno dan Hatta telah diculik oleh sekelompok pemuda dan mereka tidak tahu di mana mereka dibawa. Pemuda-pemuda itu mengadakan rapat di kantor Soebardjo, dan Wikana juga ikut dalam pertemuan tersebut.
Soebardjo sangat terkejut dan menyadari keadaan menjadi serius karena ada rapat PPKI yang akan digelar pukul 10.00. Tanpa kehadiran Ketua dan Wakil Ketua, rapat tersebut takkan berjalan. Ia menduga Wikana mengetahui keberadaan Soekarno–Hatta dan merencanakan kontak dengan pimpinan Angkatan Laut Jepang dalam upaya pencarian mereka.
Soebardjo cemas bahwa kedua pemimpin itu bisa ditangkap oleh Angkatan Darat, dan hanya Angkatan Laut yang dapat membantu membebaskan mereka. Ia kemudian memerintahkan stafnya untuk memberi tahu Angkatan Laut melalui Nishijima.
Setelah itu, Soebardjo langsung menuju rumah Maeda untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, di mana Maeda dengan kagetnya mengungkapkan ketidaktahuannya terhadap keberadaan Soekarno–Hatta. Soebardjo bergerak cepat, kembali ke kantornya dan memulai dialog dengan Wikana, menanyakan alasan dibalik penculikan itu.
Wikana menjelaskan bahwa keputusan itu diambil untuk keselamatan mereka, membawa Soekarno dan Hatta ke luar Jakarta. Namun, Wikana menolak memberi tahu tempat mereka disembunyikan. Soebardjo juga mendapat penjelasan serupa dari Pandu Kartawiguna, yang bersikeras untuk merahasiakan lokasi keberadaan Soekarno–Hatta.
Beberapa saat kemudian, seorang anggota Tentara PETA bernama Jusuf Junto datang bersama Wikana dan Pandu, mencoba meyakinkan Soebardjo bahwa aksi penculikan itu bertujuan menyelamatkan Soekarno dan Hatta. Soebardjo menegaskan bahwa mereka tak perlu khawatir akan keselamatan Soekarno–Hatta jika kembali ke Jakarta, karena Angkatan Laut akan memberi dukungan jika mereka dalam kesulitan.
Soebardjo juga meminta informasi tentang keberadaan mereka, siap untuk mengantar kembali ke Jakarta dan memulai Proklamasi Kemerdekaan. Meski Pandu melarang Soebardjo pergi sendiri karena berbahaya, akhirnya Jusuf Kunto ditunjuk untuk mendampinginya.
Pukul 16.00, Soebardjo berangkat ke Rengasdengklok dengan mobil Skoda bersama Jusuf Kunto dan Soediro, setelah berhenti di beberapa pos PETA, mereka tiba di Rengasdengklok dan bertemu dengan Soekarni, diikuti oleh interogasi dari Komandan PETA, Cundonco Subeno.
Soebardjo menjamin niatnya bukan untuk kepentingan Jepang, dan setelah interogasi, ia dipertemukan dengan Soekarno, sementara Hatta disembunyikan di tempat lain. Mereka berdiskusi, dan setelah memastikan informasi dari Laksamana Maeda tentang penyerahan Jepang, mereka bersiap kembali ke Jakarta. Meski perjalanan kembali penuh dengan ketegangan dan ketakutan disergap tentara Jepang, mereka akhirnya tiba kembali di rumah Soekarno, rumah Hatta, dan kemudian di rumah Maeda pada pukul 21.00.
Teks Proklamasi dan Kemerdekaan Indonesia
Sebelum rombongan dari Rengasdengklok sampai di rumah Maeda, tempat itu sudah dipenuhi oleh sejumlah orang. Soekarno, Hatta, dan Maeda meninggalkan rumah dalam waktu yang tidak lama. Tak berselang lama, Dr. Buntara Martoatmodjo, Sayuti Melik, dan Iwa Kusuma Sumantri tiba.
Kemudian, Soekarno kembali ke rumah Maeda bersama kelompoknya sekitar pukul 01.00, dan ia mengajak Soebardjo dan Iwa Kusuma Sumantri untuk bertemu dengan Sjahrir di suatu rumah di Jalan Bogor Lama (Jl. Minangkabau).
Namun, Sjahrir tidak ada di sana. Soebardjo kemudian bertemu dengan sejumlah pemuda, seperti Chairul Soleh, Adam Malik, Pandu Kartawiguna, Maruto Nitimihardjo. Setelah tidak menemukan Sjahrir, mereka kembali ke rumah Maeda. Soekarno, Hatta, dan Maeda belum kembali, tetapi beberapa anggota PPKI sudah hadir.
Sekitar pukul 02.00, Soekarno–Hatta dan Maeda tiba bersama Kolonel Miyoshi, seorang Perwira Penghubung Angkatan Darat yang dahulu merupakan seorang diplomat. Sebuah pertemuan berlangsung antara Soekarno–Hatta, Miyoshi, Soebardjo, Maeda, dan Nishijima di sekitar meja bundar.
Saat itu, Hatta memberitahu Soebardjo bahwa mereka telah mengunjungi Mayor Jenderal Yamamoto Moichiro dan Mayor Jenderal Nishimura, Otoshi, Samubuco dari Gunseikon (Kepala Bagian Pemerintahan Umum) Jepang tanpa hasil. Nishimura memegang teguh prinsip status quo, menolak adanya kegiatan politik setelah 15 Agustus 1945.
Hasil pertemuan tersebut menetapkan bahwa proklamasi kemerdekaan akan tetap dilakukan tanpa persetujuan Angkatan Darat Jepang. Saat Soekarno–Hatta dan Soebardjo hendak menyusun redaksi proklamasi, Soekarno bertanya kepada Soebardjo, “Masih ingatkah Anda teks dari bab pembukaan UUD kita?” Soebardjo menjawab, “Ya, saya ingat tetapi tidak lengkap.”
Soekarno menjelaskan bahwa mereka hanya memerlukan kalimat-kalimat terkait proklamasi, bukan seluruh teksnya. Soekarno menulis, “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan.” Soekarno menambahkan, “Hal-hal mengenai pemindahan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.”
Setelah menulis, Sayuti Melik mengetik teks tersebut di sebuah mesin ketik yang ada di ruangan. Setelah pengetikan selesai, Soekarno dan Hatta membacakan Teks Proklamasi di depan sejumlah hadirin, di antaranya anggota PPKI dan beberapa pemuda.
Meski Soekarni telah membaca teks sebelumnya, ia mengkritiknya sebagai teks yang lepas dari semangat revolusioner, lemah, dan tidak percaya diri. Setelah perdebatan, para anggota PPKI menentang perubahan teks.
Anggota PPKI sepakat bahwa yang menandatangani teks tersebut adalah Soekarno dan Hatta, lalu diusulkan untuk dibacakan di rumah Soekarno, tetapi Soekarno menolaknya, maka disepakati pembacaan teks proklamasi dilakuakn di lapangan Ikada pada pukul 10.00. Setelah selesai di rumah Maeda sekitar pukul 06.00, Soebardjo meninggalkan tempat tersebut.
Pada pagi hari menjelang pukul 10.00, dua utusan dari Soekarno datang untuk menjemputnya, namun karena kelelahan, Soebardjo memutuskan untuk istirahat dan tidak hadir dalam upacara saat Soekarno dan Hatta mengucapkan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Menteri Luar Negeri
Beberapa hari setelah Proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945, anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia berkumpul di Pejambon untuk mewakili rakyat Indonesia dalam mengesahkan Undang-Undang yang telah diselesaikan oleh Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan.
Mereka juga memilih Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Keesokan harinya, PPKI mengadakan sidang lagi, di mana Presiden Soekarno menunjuk Soebardjo sebagai Ketua Panitia Kecil yang terdiri dari 2 anggota: Soebardjo Kartohadikusumo dan Alex Andries Maramis.
Tugas panitia kecil ini adalah merumuskan struktur organisasi pemerintahan pusat. Usulan tersebut kemudian dibahas dalam sidang pleno dan diterima oleh Presiden setelah disepakati. Selama sidang itu, Soebardjo mengusulkan tambahan enam Menteri Negara karena keadaan negara sedang menghadapi situasi revolusioner.
Usulan tersebut diterima oleh Presiden, meski yang diangkat hanya lima orang. Setelah sidang, Presiden membentuk kabinet yang terdiri dari 18 Menteri, dengan 13 Menteri memimpin departemen dan 5 Menteri Negara. Soebardjo sendiri ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri.
Salah satu tugas awalnya adalah membangun kementerian ini karena sebelumnya tidak ada orang Indonesia yang pernah bekerja di sana. Karena tidak ada pilihan, kantor kementerian berada rumah pribadi keluarga Soebardjo.
Selanjutnya, fokusnya adalah merumuskan dasar-dasar politik luar negeri bagi negara yang baru merdeka ini, termasuk antisipasi terhadap kemungkinan kehadiran tentara sekutu di Indonesia. Karena itu, baik Presiden, Wakil Presiden, maupun Menteri Luar Negeri terus menerus menyuarakan bahwa Republik Indonesia adalah negara demokratis yang taat pada hukum internasional.
Mereka menerjemahkan dokumen seperti Atlantic Charter dan Piagram PBB ke dalam bahasa Indonesia untuk disebarkan ke seluruh jajaran pemerintah. Tujuannya adalah agar kedaulatan Indonesia diakui oleh komunitas internasional.
Hal ini menjadi penting mengingat bahwa kedaulatan Hindia Belanda telah berakhir pada Maret 1942 dan pemerintahan militer Jepang pun berakhir pada 15 Agustus 1945. Tindakan pertama yang dapat dianggap sebagai kesuksesan kampanye Menteri Luar Negeri adalah ketika tentara sekutu akan masuk ke Indonesia sesuai protokol Dotsdam.
Mereka mengakui secara de facto Negara Republik Indonesia dan memberitahu Kementerian Luar Negeri rencana kedatangan mereka.
Testamen Politik
Pada bulan Agustus 1945, Menteri Luar Negeri Achmad Soebardjo menerima kehadiran Tan Malaka, seseorang yang sebelumnya dipercayanya telah meninggal dunia. Kedatangan Tan Malaka menarik perhatian para penggemarnya, termasuk Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, Gatot Tarunamihardja, dan Presiden Soekarno.
Dalam suatu pertemuan, Soekarno mengungkapkan kekhawatirannya akan kemungkinan ditangkap oleh tentara sekutu, dan ia meminta petunjuk taktik dan strategi perjuangan dari Tan Malaka. Tan Malaka setuju memberi arahan jika diberikan surat tugas resmi.
Beberapa hari kemudian, Soebardjo memberitahu Soekarno bahwa Tan Malaka akan datang ke rumahnya. Saat Soekarno dan Hatta tiba, Tan Malaka menanyakan tentang surat tugasnya. Soekarno menjawab bahwa mereka datang untuk menyusun surat tugas bersama-sama, dengan Tan Malaka yang menulis sendiri menggunakan kertas yang disediakan Soebardjo.
Draf surat tugas tulisan Tan Malaka diserahkan kepada Soekarno, kemudian kepada Hatta. Soekarno mengusulkan agar judul surat itu diubah menjadi Amanat Soekarno–Hatta. Salah satu pokok amanatnya adalah bahwa jika terjadi sesuatu pada Soekarno–Hatta, pimpinan perjuangan akan dilanjutkan oleh Tan Malaka, Iwa Kusuma Sumantri, Sjahrir, dan Wongsonegoro. Surat amanat tersebut kemudian dikenal sebagai Testamen Politik (Surat Wasiat Politik) yang disaksikan oleh Soebardjo.
Pada tanggal 19 September 1945, Soebardjo bertemu dengan Soekarno dan menyampaikan perlunya pernyataan tekad rakyat dalam sebuah rapat besar. Soekarno setuju untuk mengumpulkan massa di lapangan Ikada sebagai respons terhadap kedatangan pasukan AFNEI di Jakarta. Soebardjo juga meminta agar diadakan sidang kabinet untuk membahas rencana rapat tersebut.
Meskipun Presiden setuju, masih ada resiko yang harus dihadapi. Sidang kabinet diadakan di rumah Presiden dengan beberapa perdebatan yang menyebabkan penundaan hingga pukul 22.00. Presiden mencoba menghubungi pimpinan tentara Jepang namun gagal. Soebardjo kemudian mengusulkan agar semua anggota kabinet turut serta dalam rapat besar tersebut, yang disepakati.
Ribuan massa telah berkumpul di lapangan Ikada, dengan para Menteri yang memimpin, termasuk Soebardjo, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ki Hadjar Dewantara menggunakan satu mobil, sementara Soekarno dan Hatta menggunakan mobil lain.
Sebelum memasuki lapangan, mobil mereka ditahan sejenak oleh Kimpeilais. Setelah Presiden berpidato singkat meminta ketaatan kepada pemerintah dan disiplin kepada masyarakat, mereka meninggalkan lapangan Ikada dengan tertib.
Soebardjo menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam kabinet pertama selama empat bulan karena perubahan dari Kabinet Presidensial. Peristiwa rapat raksasa tanggal 19 September memiliki dampak besar, terutama di daerah yang mendengar kedatangan pasukan AFNEI bersama NICA.
September dan Oktober menjadi bulan penuh ketegangan, dengan perlawanan pemuda dan upaya Soebardjo dalam menyebarkan pesan melalui radio kepada para pemimpin Partai Buruh. Melalui pesan radio ini, ia menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi.
Pada 9 Oktober 1945, pesan lain dikirim yang menyatakan bahwa pemerintah RI tidak menentang kedatangan tentara Inggris (AFNEI) asalkan mereka melaksanakan tugas tanpa memusuhi bangsa Indonesia. Di Jakarta, insiden bersenjata semakin meluas, dan Soebardjo dipanggil oleh Panglima AFNEI Letjen Christison untuk membahas beberapa hal, termasuk memberi tentara Indonesia uniform untuk membedakan antara mereka dan kelompok liar di lapangan.
Sementara itu, Presiden mengeluarkan pernyataan penting yang menegaskan kehendak bangsa Indonesia atas kemerdekaannya dan menolak kedatangan Belanda. Insiden bersenjata juga merebak di berbagai kota seperti Surabaya, Bandung, Semarang, dan Medan.
Penangkapan dan Pemenjaraan
Pada November 1945, terjadi pergantian kabinet yang menurut Soebardjo dipicu oleh pergantian pemerintahan di Inggris dan Belanda yang memiliki orientasi sosialis. Sultan Sjahrir, seorang sosialis, diangkat sebagai Perdana Menteri, dan menurut Soebardjo, kebijakannya cenderung evolusioner dengan fokus pada “taktik diplomasi”.
Namun, rakyat sendiri bersemangat untuk melawan penjajahan Belanda. Soebardjo ditawari sebagai Wakil Menteri Luar Negeri dalam kabinet baru tersebut, namun ia menolak karena perbedaan prinsip.
Ia kemudian pindah ke Yogyakarta, dan melalui Dr. Sukirman, ia bertemu dengan Panglima Besar Jenderal Soedirman, yang sedang mencari penasehat politik. Bersama kawannya seperti Iwa Kusuma Sumantri dan Ki Hadjar Dewantoro, Soebardjo bergabung dalam Badan Penasehat Panglima Besar.
Pada akhir Juni 1946, saat anggota Badan Politik Panglima Besar kembali dari Rapat Partai Buruh di Blitar, Soebardjo mendengar kabar bahwa ia akan ditangkap oleh Pemuda Sosialis Indonesia, organisasi militer Partai Sosialis Sjahrir.
Untuk menghindari penangkapan, Soebardjo memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta dan tinggal di kompleks Tasikmadu Kartasura. Namun, keberadaannya terungkap, dan ia akhirnya ditangkap oleh polisi dan dibawa ke Tawangmangu ke sebuah kompleks tempat istirahat (bungalow), di mana ia bertemu dengan beberapa tokoh yang sejalan dengan pandangannya, termasuk pengikut Tan Malaka seperti Iwa Kusuma Sumantri, Muhammad Yamin, dan Sayuti Melik.
Kemudian, mereka dipindahkan ke penjara Wirogunan Yogyakarta. Pada 3 Juli 1946, mereka dibebaskan dari penjara oleh Jenderal Mayor Soedarsono dan dibawa ke sebuah penginapan.
Di sana, dalam percakapannya dengan Muhammad Yamin, Yamin menyampaikan bahwa ia telah menulis petisi untuk disampaikan kepada Presiden Soekarno, yang menginginkan reshuffle kabinet Sjahrir II dan menyerukan politik konfrontasi merdeka seratus persen (100%) tanpa berunding dengan Belanda.
Namun, saat mereka menghadap Soekarno, mereka ditangkap oleh pihak Istana Kepresidenan dan aparat keamanan, menjadikan Soebardjo dan rekan-rekannya tahanan pemerintah. Di antara mereka ada generasi yang lebih muda seperti Adam Malik dan Chairul Saleh.
Setelah beberapa waktu ditahan di Yogyakarta, mereka dipindahkan dengan truk ke Tretes, sebuah tempat peristirahatan di Jawa Timur. Tak lama di sana, mereka dipindahkan ke penjara Magelang karena desas-desus akan serangan Belanda. Kemudian, mereka dipindahkan ke penjara Ponorogo, lalu ke rumah penjara Mojokerto, dan akhirnya ke rumah penjara Madiun.
Pada 17 Agustus 1948, mereka memperoleh amnesti dari Presiden dan dibebaskan. Namun, saat baru menikmati kebebasan sejenak di Yogyakarta, Belanda memulai aksi militer II. Soebardjo ditangkap oleh Intelijen Militer Belanda dan dipenjara di Ambarawa, hingga akhirnya dibebaskan setelah resolusi PBB memerintahkan pembebasan semua tahanan politik.
Kembali Ke Departemen Luar Negeri
Setelah dibebaskan, Soebardjo kembali ke Departemen Luar Negeri. Pada September 1951, ia dipilih sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam konferensi perdamaian dengan Jepang di San Fransisco yang membahas beragam isu hubungan bilateral dan kompensasi perang.
Pada tahun 1953, ia menjabat sebagai Direktur Akademi Dinas Luar Negeri (ADLN). Setelah berhasil memajukan pendidikan dan melatih calon diplomat selama dua tahun, Soebardjo ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Republik Federasi Swiss.
Wafat
Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo wafat pada usia 82 tahun pada tanggal 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru. Kematian beliau disebabkan oleh flu yang berujung pada komplikasi. Almarhum dikebumikan di Cipayung, Bogor.
Pada tahun 2009, pemerintah memberikan penghormatan sebagai salah satu Pahlawan Nasional Indonesia kepada Achmad Soebardjo.
Bio Data Achmad Soebardjo
| Nama Lengkap | Mr Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo |
| Nama Kecil | Teuku Abdul Manaf / Achmad Soebardjo |
| Nama Lain | – |
| Tempat, Lahir | Karawang, Keresidenan Batavia, Hindia Belanda, 23 Maret 1896 |
| Tempat, Wafat | Jakarta, Indonesia, 15 Desember 1978 (umur 82) |
| Makam | Jl. Panatraco, Desa Cibogo, Jawa Barat |
| Agama | Islam |
| Suku | Aceh |
| Bangsa | Indonesia |
| Pekerjaan | Politisi |
| Partai | Masyumi |
| Keluarga | |
| Ayah | Teuku Muhammad Yusuf |
| Ibu | Wardinah |
| Isteri | Raden Ayu Poedji Astuti Soebardjo |
| Anak | Rohadi Soebardjo Nurwati Dewi Seribudiarti Pudjiwati Insia |
Riwayat Pendidikan Achmad Soebardjo
| Pendidikan | Tempat |
|---|---|
| Europeesche Lagere School-ELS | Europeesche Lagere School-ELS di Kwitang |
| Europeesche Lagere School B-ELSB | ELSB di Pasar Baur |
| Prince Hendrik School | |
| HBS Koning William III (KW III) (1917) | HBS Koning William III (KW III) di Salemba |
| Meester in de Rechten (saat ini setara dengan Sarjana Hukum) (1933) | Universitas Leiden |
Karir Achmad Soebardjo
| Organisasi/Lembaga | Jabatan (Tahun) |
|---|---|
| Tri Koro Darmo | Anggota (1917) |
| Perhimpunan Indonesia | Ketua |
| Kongres Anti Imperialisme | Anggota (5 – 10 Februari 1927) |
| Kantor Bantuan Hukum Mr. Sastro Muljono | Anggota |
| Kantor Bantuan Hukum Mr. Isk aq (Tjokro Hadisoerjo) | Anggota |
| Kantor Pengacara Soebardjo | Pendiri (1935) |
| BPUPKI | Anggota |
| PPKI | Anggota |
| Menteri Luar Negeri Indonesia | Menteri Luar Negeri Indonesia (2 September 1945 – 14 November 1945) |
| Badan Penasehat Panglima Besar | Anggota |
| Menteri Luar Negeri Indonesia | Menteri Luar Negeri Indonesia (4 Agustus 1951 – 20 Desember 1952) |
| Akademi Dinas Luar Negeri (ADLN) | Direktur (1953) |
| Duta Besar Indonesia untuk Swiss | Duta Besar (1957–1961) |
Penghargaan Achmad Soebardjo
| Tahun | Penghargaan |
|---|---|
| 2009 | Pahlawan Nasional Indonesia |
Penghargaan Bintang Achmad Soebardjo
| Penghargaan (tahun) | Gambar |
|---|---|
| Bintang Republik Indonesia Utama (12 Agustus 1992) | |
| Bintang Mahaputera Adipradana (19 Mei 1973) | |
| Satyalencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan, 1961 | |
| Order of Merit dari Pemerintah Mesir, 1954 |