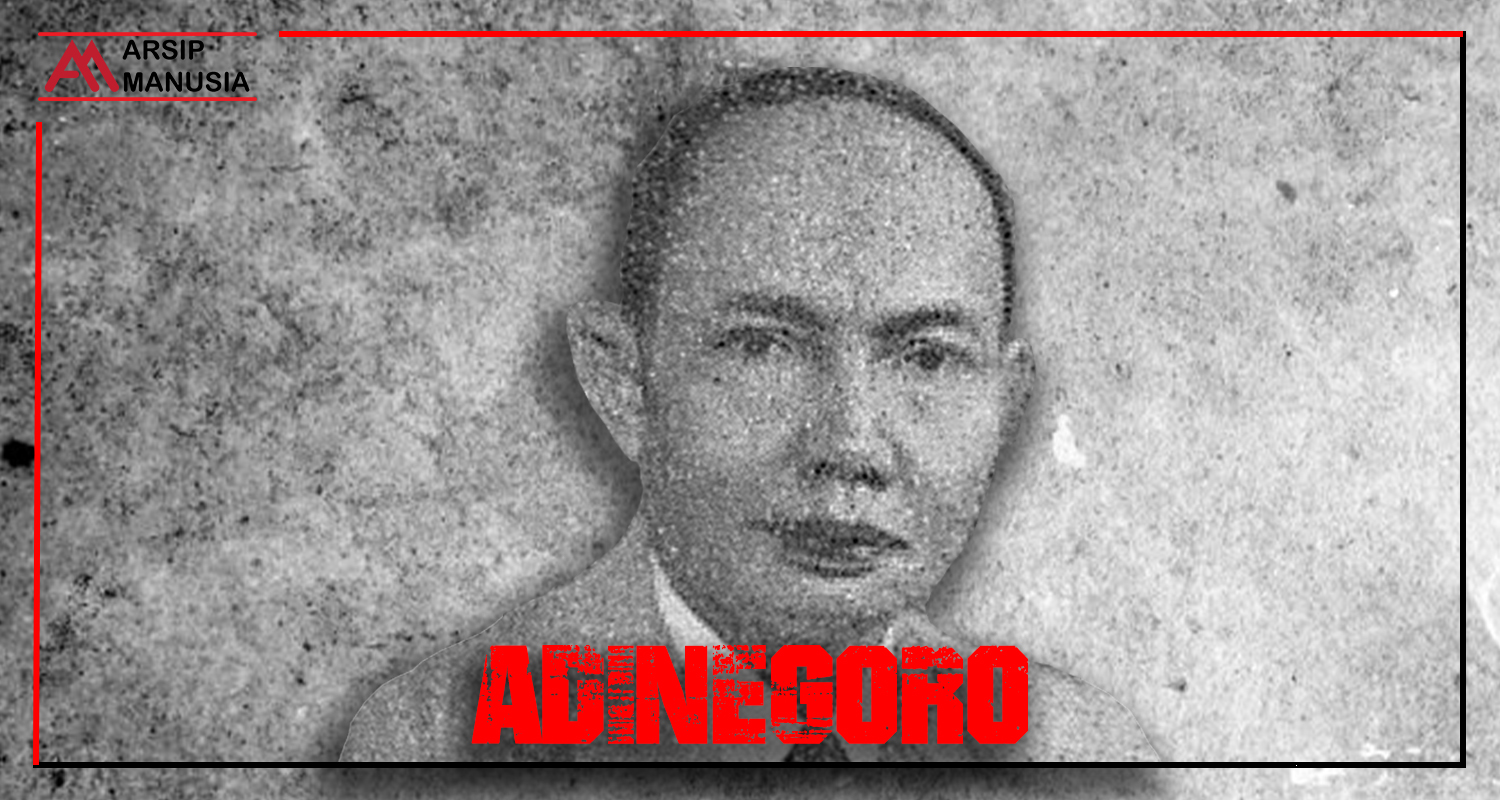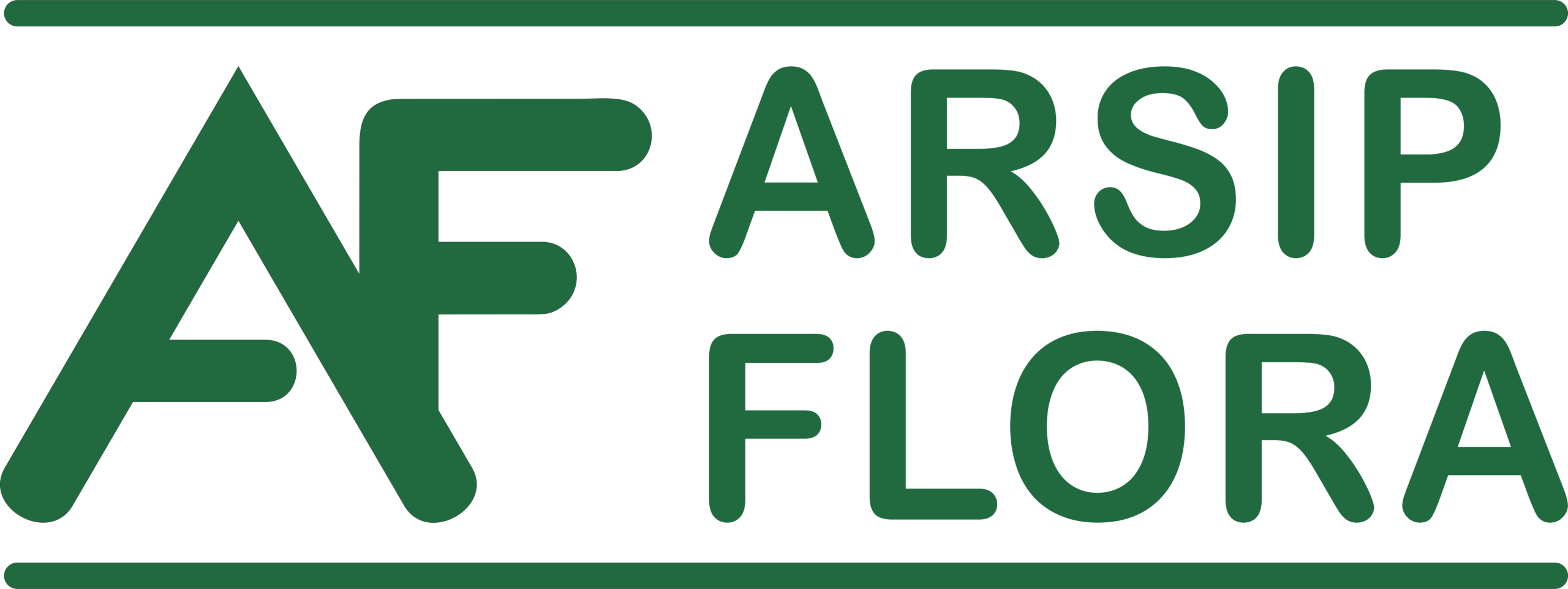Abdoel Moeis merupakan sosok penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Ia dikenal sebagai seorang sastrawan, wartawan, dan politikus yang vokal dalam memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi pada masa penjajahan Belanda. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah novel Salah Asuhan (1928), yang hingga kini dianggap sebagai karya sastra klasik Indonesia. Atas jasa-jasanya, Abdoel Moeis dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pertama oleh Presiden Soekarno pada 30 Agustus 1959.
Table of Contents
ToggleMasa Muda
Abdoel Moeis lahir di Sungai Puar, Agam, Sumatera Barat, pada 3 Juli 1886. Ayahnya, H. Abdul Gani gelar Datuk Sulaiman, adalah seorang Larak (Camat) Sungai Puar dan juga memiliki usaha pembuatan korek api. Ibunya, Siti Djariah, berasal dari Kota Gadang, Sumatera Barat, dan merupakan keturunan dari Syekh Ahmad Khatib, seorang ulama besar yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram, Makkah. Abdoel Moeis juga memiliki hubungan kekerabatan dengan tokoh nasional H. Agus Salim.
Pendidikan
Lahir di tengah keluarga terpandang membuat Abdoel Moeis memperoleh akses pendidikan yang baik. Pada usia tujuh tahun, ia mulai bersekolah di Europeesche Lagere School (ELS) di Bukittinggi dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1899.
Sejak kecil, Abdoel Moeis bercita-cita menjadi seorang dokter. Untuk mewujudkan impiannya, ia melanjutkan pendidikan ke School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) di Batavia. Awalnya, prestasinya di STOVIA sangat baik. Namun, pada tahun ketiga, ia harus mengikuti praktik bedah sebagai bagian dari kurikulum. Saat praktik berlangsung, Abdoel Moeis merasa tidak tahan melihat darah, bahkan sering merasa pusing. Setelah beberapa kali mencoba, ia akhirnya menyadari bahwa dirinya tidak cocok untuk menjadi dokter.
Ia kemudian mengutarakan kegelisahannya kepada orang tuanya, dan dengan berat hati memutuskan untuk keluar dari STOVIA pada tahun 1903, mengakhiri cita-citanya sebagai tenaga medis.
Karier Awal
Setelah keluar dari STOVIA, Abdoel Moeis bekerja sebagai juru tulis (klerk) di Departemen Onderwijs en Eredienst atas bantuan dari Mr. Abendanon, seorang pejabat Belanda yang mendukung kemajuan kaum pribumi. Ia bekerja dengan tekun dan membuktikan bahwa orang bumiputera juga mampu bekerja secara profesional. Namun, ketika Mr. Abendanon dipindahkan dan digantikan oleh Wiemans, jabatan Moeis diturunkan menjadi schrijver (penyalin naskah) dengan alasan gajinya dianggap tidak layak untuk posisi sebelumnya.
Merasa direndahkan dan tidak dihargai, Abdoel Moeis memilih keluar dari departemen tersebut.
Setelah itu, ia sempat bekerja di Bank Rakyat (Volks Credietwezen) di Bandung. Namun, ia tidak betah karena menyaksikan praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh lurah dan pamong praja setempat. Moeis pun memutuskan untuk keluar dan memilih jalur jurnalistik sebagai wadah perjuangannya.
Dunia Jurnalistik
Langkah pertama Abdoel Moeis di dunia jurnalistik dimulai ketika ia bekerja di harian Bintang Hindia sebagai penerjemah. Kemudian, pada tahun 1912, ia menjadi korektor di surat kabar Preanger Bode yang terbit di Bandung. Tugasnya adalah memeriksa dan mengoreksi naskah sebelum dicetak.
Selama bekerja di sana, ia sering membaca tulisan-tulisan orang Belanda yang merendahkan bangsa Indonesia. Hal ini membuatnya marah dan ia meminta agar tulisan-tulisan itu tidak diterbitkan. Namun, permintaan tersebut tidak dipenuhi karena surat kabar itu dikuasai oleh orang Belanda.
Tidak tinggal diam, Abdoel Moeis mulai menulis artikel tandingan yang membela kehormatan bangsa Indonesia. Ia mengirimkan tulisannya ke surat kabar De Express, yang dipimpin oleh Tiga Serangkai: Ernest Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Tak lama kemudian, ia keluar dari Preanger Bode dan bergabung dengan mereka.
Pada tahun 1913, bersama ketiga tokoh tersebut, ia ikut menerbitkan majalah mingguan Hindia Serikat dan dipercaya sebagai editor. Pada tahun yang sama, ketika pemerintah kolonial Belanda ingin merayakan 100 tahun kemerdekaannya dari Prancis, Abdoel Moeis turut aktif dalam Komite Bumiputera yang dibentuk untuk memprotes rencana itu. Komite ini dipimpin oleh Tjipto Mangunkusumo, dan Abdoel Moeis menjadi salah satu anggotanya.
Kritik paling tajam disampaikan oleh Suwardi Suryaningrat melalui tulisan berjudul Als Ik Nederlander Was (Seandainya Aku Seorang Belanda), yang akhirnya membuat pemerintah kolonial tersinggung. Akibatnya, tulisan itu disita, rumah para tokoh Komite digeledah, dan ketiganya – Douwes Dekker, Tjipto, dan Suwardi – diasingkan ke Belanda.
Bergabung dengan Sarekat Islam
Tahun 1914, Abdoel Moeis menjadi pemimpin redaksi surat kabar Kaum Muda. Di media ini, ia menyalurkan pandangan kritisnya terhadap penjajahan. Semangat perlawanan yang ia tunjukkan menarik perhatian H.O.S. Tjokroaminoto, pemimpin Sarekat Islam (SI), yang kemudian mengajak Abdoel Moeis bergabung.
Pada tahun 1915, Abdoel Moeis resmi menjadi anggota Sarekat Islam dan langsung dipercaya sebagai wakil ketua sementara untuk cabang Bandung. Karena kepiawaiannya dalam berorasi dan berdiskusi, ia kemudian diangkat menjadi anggota pengurus pusat dan tak lama setelah itu dipercaya menjabat sebagai Wakil Presiden Central Sarekat Islam periode 1915–1922.
Pengasingan dan Kehidupan di Garut
Pada tahun 1923, Abdoel Moeis mulai aktif dalam urusan perburuhan. Ia menjadi Ketua Persatuan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB) dan memimpin aksi mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap rendahnya upah pegawai. Aksi tersebut menyebabkan sekitar 3.000 pekerja diberhentikan, dan Abdoel Moeis ditahan oleh pemerintah kolonial.
Tiga tahun kemudian, pada 1926, ia dijatuhi hukuman berupa pelarangan berpolitik dan pengasingan oleh pemerintah Hindia Belanda. Menariknya, Abdoel Moeis diberikan kebebasan untuk memilih lokasi pengasingan, dan ia memilih Garut, Jawa Barat. Di sana, ia tinggal bersama istrinya, Sunarsih, yang dinikahinya pada tahun 1925.
Selama di pengasingan, Abdoel Moeis menjalani kehidupan sederhana. Ia bertani dan mengajarkan teknik pertanian modern kepada masyarakat sekitar. Meski jauh dari panggung politik, semangat nasionalismenya tidak pernah padam.
Pada tahun 1937, ia menerima tawaran untuk menjadi kontrolir—jabatan administratif yang bertugas mengawasi pemerintahan lokal. Niatnya adalah membantu masyarakat dari dalam sistem. Namun, posisinya justru membuatnya berada dalam dilema. Di satu sisi, kaum pribumi menganggapnya telah “berpihak kepada Belanda”, sementara pejabat Belanda tidak menyukainya karena ia bersikap tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa penjajah sendiri.
Pensiun dan Karya Sastra
Pada tahun 1939, pemerintah kolonial mencabut status pengasingan Abdoel Moeis. Ia pun kembali ke kehidupan bebas, meski tetap berada dalam keterbatasan akibat usia dan kondisi kesehatannya yang menurun.
Kesepian selama masa pengasingan membawanya pada kenangan masa muda—tentang kampung halamannya di Bukittinggi, masa sekolah di STOVIA, hingga kisah cintanya dengan seorang gadis Belanda yang berakhir karena perbedaan budaya dan nilai hidup. Kisah tersebut menginspirasi lahirnya novel terkenalnya, Salah Asuhan, yang diterbitkan pada tahun 1928. Novel ini menjadi salah satu karya sastra penting dalam sejarah Indonesia, karena menggambarkan konflik identitas bangsa terjajah yang terpapar modernitas Barat.
Pada masa tuanya, Abdoel Moeis sempat mencoba mencari nafkah di Jakarta. Namun karena faktor usia dan kondisi fisik yang lemah, ia menolak tawaran bekerja di pemerintahan. Sebagai gantinya, ia tetap aktif menulis dan menerjemahkan karya-karya sastra asing untuk menyambung hidup.
Wafat dan Pengakuan sebagai Pahlawan
Abdoel Moeis meninggal dunia pada 17 Juni 1959, dalam usia 76 tahun, akibat penyakit tekanan darah tinggi yang dideritanya. Dua bulan setelah wafatnya, tepat pada 30 Agustus 1959, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia pertama kepada Abdoel Moeis melalui Surat Keputusan Presiden No. 218 Tahun 1959.
Penghargaan terhadap Abdoel Moeis tidak berhenti di situ. Pada tahun 1968, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mansyur S.H. memberikan penghargaan seni kepadanya sebagai salah satu Sastrawan Indonesia Utama, berkat kontribusinya yang besar terhadap perkembangan kesusastraan nasional melalui novel Salah Asuhan.
Abdoel Moeis adalah contoh nyata seorang intelektual yang memadukan pena dan perjuangan. Ia tidak hanya menulis untuk menyuarakan perlawanan terhadap kolonialisme, tetapi juga turun langsung dalam dunia politik, pendidikan, dan pergerakan buruh. Sosoknya menggambarkan perjalanan seorang pejuang bangsa yang kompleks—kadang dipuja, kadang dikucilkan—namun tetap konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan dan harga diri bangsanya.
Sebagai wartawan, ia bersuara; sebagai politikus, ia berjuang; dan sebagai sastrawan, ia meninggalkan warisan abadi yang terus dikenang hingga kini.
Sumber:
- “Abdoel Moeis” esi.kemdikbud.go.id (diakses 16 Februari 2025)
- Sa’roni, Moh. (1995), “Abdul Muis: Studi Tentang Peranan dalam Perkembangan Sarikat Islam Tahun 1912-1922”, Skripsi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- “Abdoel Moeis (1886 – 1959)” ensiklopedia.kemdikbud.go.id (diakses pada 16 Februari 2025)
- “Abdoel Moeis” merdeka.com (diakses 16 Februari 2025)
- “Biografi Abdoel Moeis” hobbymiliter.com (diakses 16 Februari 2025)