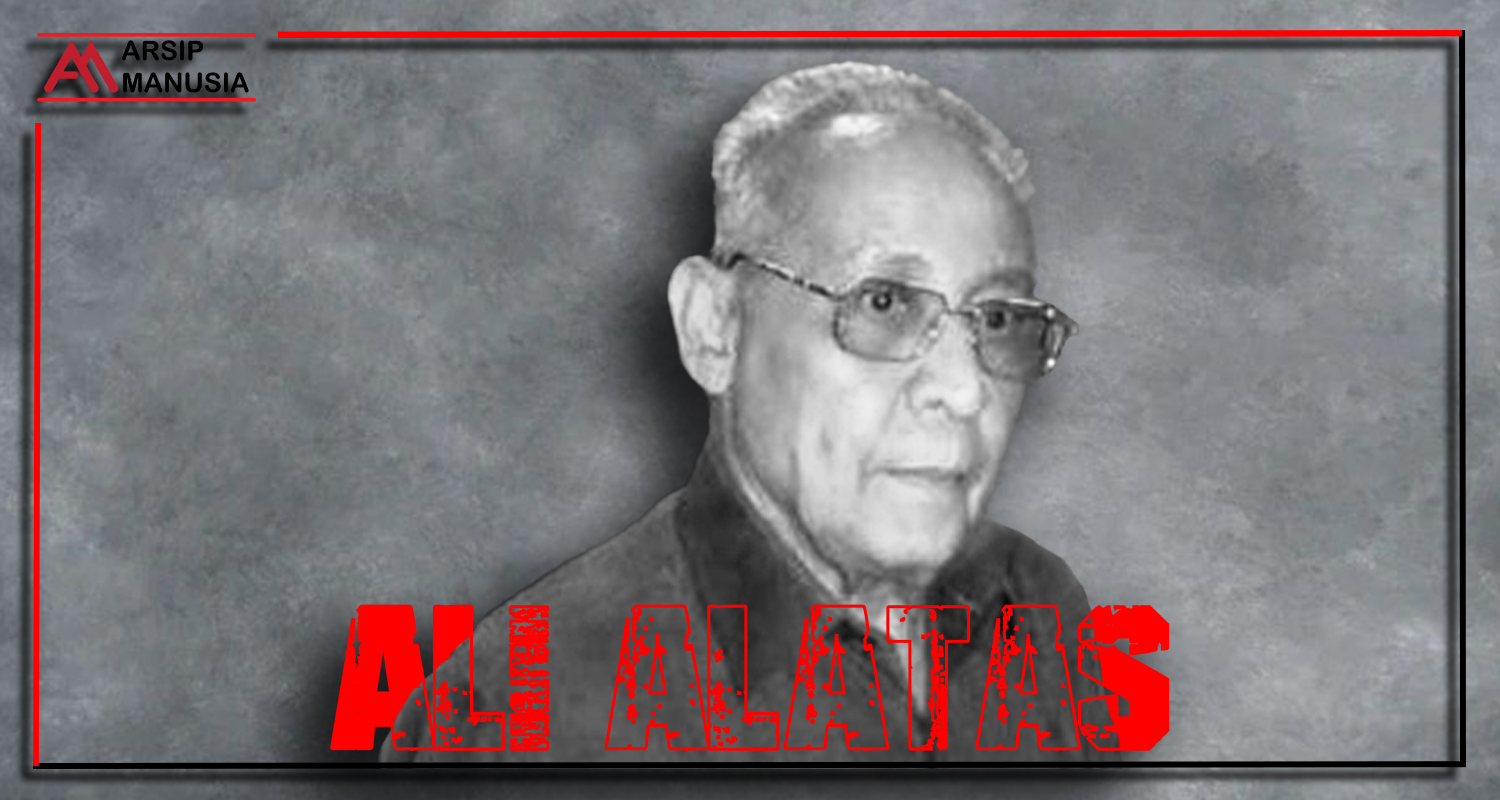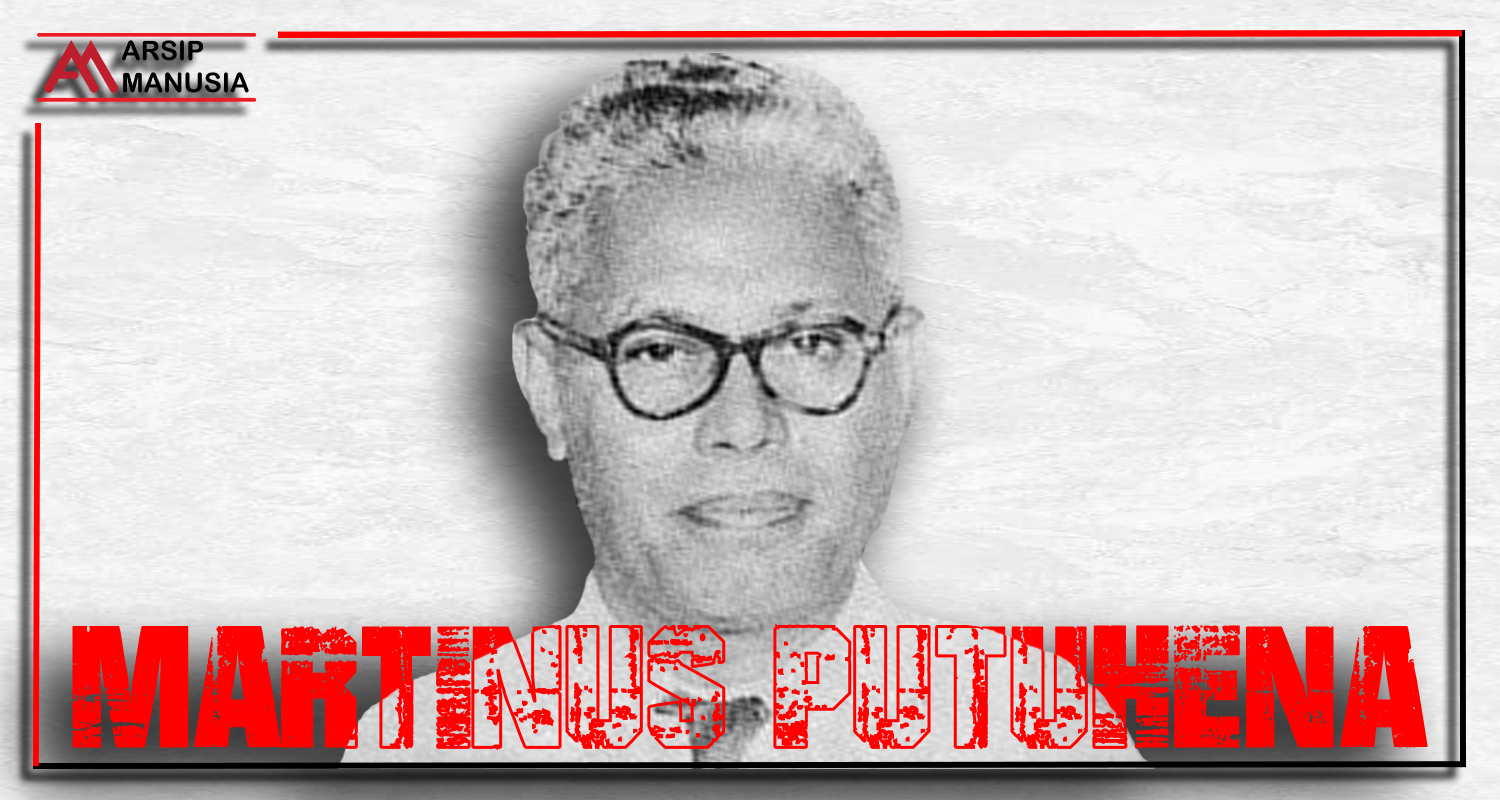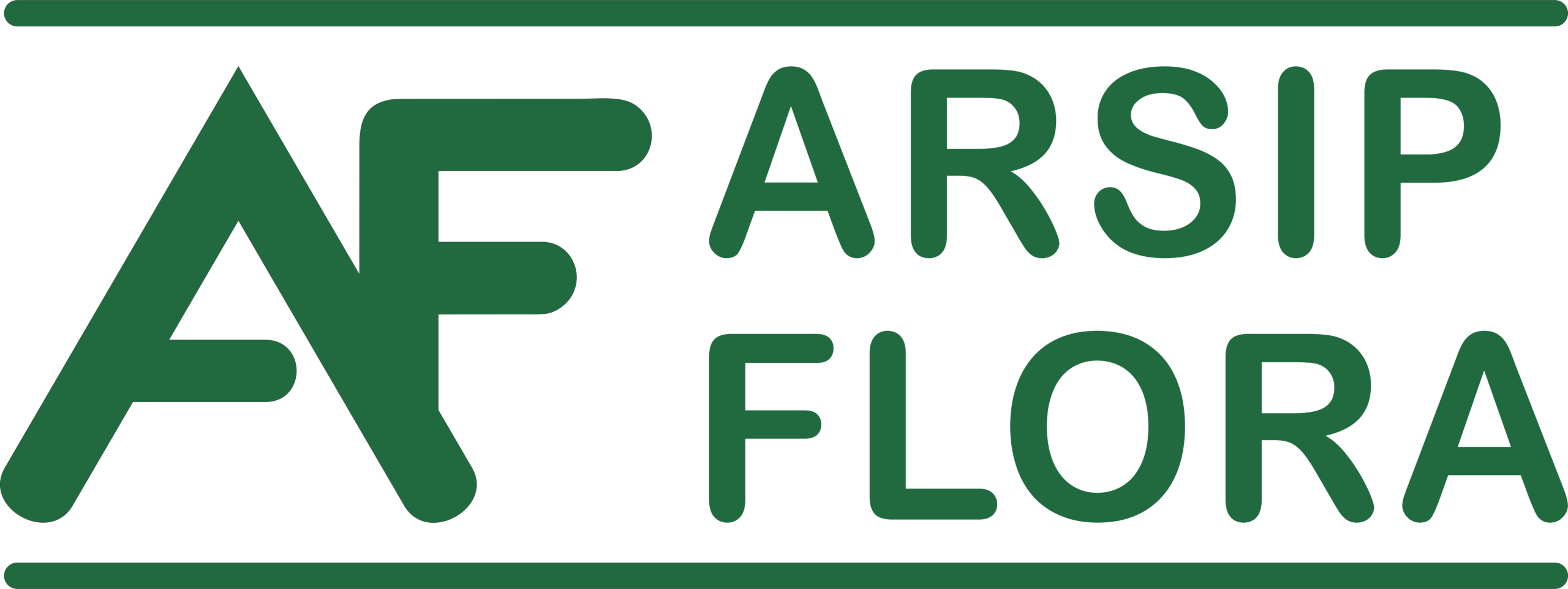Daoed Joesoef merupakan salah satu tokoh di dunia pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Daoed dikenal sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada era Presiden Soeharto serta sebagai seorang intelektual muslim yang teguh memperjuangkan nilai-nilai keilmuan dan kejujuran akademik.
Gagasan-gagasannya mengenai pendidikan, modernisasi, dan identitas bangsa Indonesia tidak hanya memengaruhi kebijakan nasional, tetapi juga meninggalkan jejak kuat dalam perkembangan pemikiran generasi intelektual Indonesia.
Table of Contents
ToggleMasa Kecil dan Latar Belakang Keluarga
Daoed Joesoef dilahirkan di kota Medan, Sumatra Utara, pada tanggal 8 Agustus 1926. Ia merupakan anak keempat dari lima bersaudara dalam keluarga yang taat beragama dan cukup terpandang. Ayahnya, yang dikenal sebagai seorang pegawai Jawatan Pos, mengajarkan pentingnya disiplin dan tanggung jawab sejak dini, sementara ibunya banyak membentuk karakter Daoed dengan kasih sayang dan nilai-nilai ke-Islaman yang kuat.
Lingkungan keluarga yang sederhana namun kaya akan nilai-nilai moral ini menjadi dasar dalam membentuk kepribadian Daoed kecil. Sejak usia muda, Daoed telah menunjukkan ketertarikan yang besar pada dunia membaca dan belajar.
Kehidupan masa kecilnya juga diwarnai oleh pengalaman hidup dalam masyarakat yang majemuk. Hal ini secara tidak langsung membentuk pandangan Daoed tentang pentingnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa.
Pendidikan dan Masa Studi di Luar Negeri
Daoed Joesoef menapaki jenjang pendidikan formalnya dari Sekolah Dasar Melayu, sebelum kemudian melanjutkan ke Hollandsch-Inlandsche School (HIS) sebuah sekolah berbahasa Belanda yang kala itu diperuntukkan bagi pribumi. Di sana, sebagian besar teman-teman sekelasnya berasal dari kalangan Melayu, mencerminkan sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif namun tetap Daoed manfaatkan sebaik mungkin.
Pada tahun 1940, ia melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). Setelah lulus, Daoed memilih untuk melanjutkan pendidikan SMA di Yogyakarta. Di kota pelajar ini pula ia ikut bergabung dengan Tentara Pelajar dalam Brigade 17 Batalyon 300.
Namun situasi di Yogyakarta tidaklah kondusif. Agresi militer Belanda membuat kondisi keamanan tak menentu, mendorong Daoed untuk pindah ke Jakarta demi melanjutkan pendidikan. Di ibu kota, ia mengikuti ujian extrane—ujian kelulusan bagi siswa nonformal—dan berhasil lulus meski hasilnya tak terlalu memuaskan. Ia lalu mendaftar di Akademi Nasional Swasta dengan memilih jurusan sosial-ekonomi, dan tak lama kemudian pindah ke Universitas Indonesia setelah kampus tersebut dinasionalisasi dari Universiteit van Indonesië.
Menjalani kuliah di tengah kerasnya kehidupan Jakarta, Daoed Joesoef tak menyerah. Ia bekerja sebagai guru SMA untuk membiayai kebutuhan hidup dan kuliahnya. Kerja keras itu membuahkan hasil—setelah lulus, ia menjadi dosen di almamaternya, Universitas Indonesia.
Karier akademis Daoed kemudian menembus dunia internasional. Pada tahun 1967, ia meraih gelar Docteur de l’Université dalam bidang hukum dari Université de Paris. Tak berhenti di situ, enam tahun kemudian ia meraih gelar Docteur d’État di bidang ekonomi dari Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, salah satu kampus paling prestisius di Prancis. Gelar ini ia raih dengan predikat cum laude sebuah pencapaian yang membanggakan, baik secara pribadi maupun untuk Indonesia.
Selama masa studinya di Sorbonne, Daoed aktif berdiskusi bersama mahasiswa dari berbagai negara. Ia tak hanya menyerap ilmu, tapi juga memperluas wawasan lewat dialog lintas budaya dan pemikiran. Di sinilah terlihat jelas, semangat belajar dan berdialektika yang menjadi ciri khas Daoed Joesoef sepanjang hidupnya.
Karir
Saat masih menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Daoed Joesoef dikenal begitu menguasai bidang Ekonomi Moneter, hingga pada tahun 1953 sempat ditawari menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk menggantikan Sjarifuddin Prawiranegara. Sebuah tawaran luar biasa bagi seorang mahasiswa. Namun dengan penuh pertimbangan, Daoed menolak tawaran tersebut karena ingin menuntaskan studinya terlebih dahulu.
Tiga tahun berselang, tepatnya pada 1956, Daoed mulai meniti karier akademik dengan ditunjuk sebagai asisten dosen di Fakultas Ekonomi UI. Tak butuh waktu lama, setahun sebelum ia menyelesaikan skripsinya—yakni pada 1958—Daoed resmi diangkat menjadi dosen tetap.
Daoed tak hanya mengajar di Universitas Indonesia, tetapi juga aktif mengajar di beberapa universitas ternama lainnya. Berkat prestasi akademik yang terus bersinar, Daoed kemudian mendapat kesempatan melanjutkan studi ke Université de Paris (Sorbonne), Prancis. Awalnya, ia berniat memperdalam ilmu keuangan. Namun, di sana ia mengambil program master dan kemudian doktoral, hingga meraih gelar di bidang Ilmu Keuangan Internasional dan Hubungan Internasional.
Dalam waktu tiga tahun, dari 1962 hingga 1965, Daoed memegang sejumlah jabatan penting di Fakultas Ekonomi UI. Ia tercatat sebagai: Kepala Departemen Ekonomi (1962–1965), Kepala Jurusan Umum dan Ekonomi Pemerintahan (1962–1965), Kepala Departemen Administrasi Umum (1964–1965).
Daoed juga aktif di Centre for Strategic and International Studies (CSIS)—sebuah lembaga pemikir (think tank) ternama di Indonesia. Di sinilah namanya semakin dikenal luas, terutama ketika ia menjabat sebagai Direktur CSIS pada 1970–1973. Dalam periode itu, Daoed juga menjadi anggota tim riset CSIS yang bekerja sama dengan Georgetown University di Washington DC, Amerika Serikat.
Sebelum dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1978, Daoed sempat menjabat sebagai asisten ahli menteri di departemen yang sama pada periode 1976–1978. Setelah masa jabatannya sebagai menteri berakhir, ia kembali ke dunia pemikiran strategis dengan menjabat sebagai Ketua Dewan Direktur CSIS dari tahun 1984 hingga 1999. Setelahnya, Daoed tetap aktif sebagai pembina di yayasan tersebut, menunjukkan komitmennya yang konsisten dalam bidang pendidikan, riset, dan kebijakan publik hingga akhir hayatnya.
Kebijakan Kontroversi
Menghapus Libur Penuh Ramadhan
Pada tahun 1978, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef mengeluarkan kebijakan yang menuai banyak perdebatan, terutama dari kalangan umat Islam. Dalam Surat Keputusan No. 0211/U/1978 pasal 6, Daoed menetapkan bahwa bulan Ramadhan tidak lagi menjadi libur penuh bagi siswa dan siswi di seluruh Indonesia. Sebaliknya, bulan tersebut ditetapkan sebagai waktu belajar seperti biasa, meski dengan penyesuaian tertentu.
Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan penting. Pertama, Daoed melihat bahwa bulan Ramadhan yang maju sekitar 11 hari setiap tahunnya akan berdampak pada ketidakkonsistenan kalender akademik jika terus dijadikan masa libur penuh. Hal ini dikhawatirkan mengganggu efektivitas proses belajar-mengajar yang sebenarnya sangat penting bagi kemajuan pendidikan nasional. Ia juga mencontohkan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Tunisia, Irak, Mesir, dan Aljazair, yang tidak meliburkan sekolah selama Ramadhan. Dari sinilah Daoed ingin mendorong perubahan paradigma: bahwa puasa dan pendidikan dapat berjalan berdampingan.
Kedua, Daoed menilai tradisi libur penuh di bulan Ramadhan merupakan warisan kolonial Belanda yang sengaja dirancang sebagai bentuk pembodohan sistemik. Libur selama sebulan dianggap telah menjauhkan generasi muda dari penguasaan ilmu pengetahuan, membuat mereka semakin tertinggal dan mudah dikuasai.
Ketiga yang tak kalah penting bersifat spiritual. Daoed merujuk pada momentum Nuzulul Qur’an, yaitu turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan umat manusia untuk membaca. Dari peristiwa ini, Daoed menarik kesimpulan bahwa justru di bulan Ramadhan, semangat menuntut ilmu seharusnya semakin diperkuat, bukan malah dihentikan.
Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, waktu libur selama Ramadhan kemudian dipangkas menjadi 10 hari kerja: tiga hari di awal bulan puasa dan tujuh hari menjelang Idulfitri. Selain itu, pemerintah menetapkan penyesuaian aktivitas di sekolah, seperti menutup kantin selama jam belajar dan mengurangi durasi pelajaran agar siswa tetap dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik. Kegiatan fisik yang terlalu berat juga ditiadakan agar kondisi fisik siswa tetap terjaga.
Namun, keputusan ini tidak diterima dengan mudah. Tokoh-tokoh Islam seperti K.H. Saifuddin Zuhri dari Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa meskipun kebijakan tersebut tidak bertentangan langsung dengan ajaran Islam, libur Ramadhan sesungguhnya memberi dampak positif bagi guru dan murid, terutama dalam mendalami nilai-nilai keagamaan. Senada dengan itu, Buya Hamka dari Majelis Ulama Indonesia bahkan menyebut kebijakan ini sebagai “cobaan serius” bagi umat Muslim.
Beberapa ulama dari kalangan pesanteren menilai Daoed terlalu terpengaruh oleh nilai-nilai Barat yang lebih mengedepankan ilmu duniawi ketimbang nilai-nilai keislaman. Mereka beranggapan bahwa selama masa kolonial pun, Belanda menunjukkan penghormatan terhadap umat Islam dengan meliburkan sekolah selama Ramadhan—sebuah hal yang justru tidak diteruskan oleh pemerintah Indonesia sendiri di masa Orde Baru.
Hubungan antara rezim Orde Baru dan kelompok Islam mulai menunjukkan ketegangan. Sikap saling tidak percaya ini tercermin dari beragam kritik yang dilontarkan tokoh-tokoh Islam terhadap kebijakan pemerintah, termasuk terhadap Daoed Joesoef sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Larangan Hijab
Kebijakan paling kontroversial pada masa Dooed menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah larangan penggunaan jilbab di lingkungan sekolah. Larangan ini tertuang dalam Surat Keputusan Mendikbud No. 052/C/Kep/D.82, yang menetapkan pedoman seragam nasional untuk seluruh pelajar dari tingkat TK hingga SMA. Tujuannya, menurut pemerintah, adalah membangun rasa persatuan, mengurangi perbedaan sosial berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, serta menghindari sikap eksklusivitas di kalangan siswa.
Siswi Muslimah yang memilih mengenakan jilbab dianggap melanggar aturan karena tidak menggunakan seragam sesuai ketentuan. Banyak sekolah menolak memberikan toleransi, bahkan menjatuhkan sanksi. Tak sedikit siswi berjilbab yang dipanggil ke kantor guru, dipulangkan saat jam pelajaran, hingga mendapatkan nilai buruk karena dianggap membangkang. Beberapa di antaranya bahkan dikeluarkan dari sekolah secara diam-diam, tanpa sepengetahuan orang tua, demi menghindari konflik.
Kondisi ini membuat sisiwi Muslimah dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mereka ingin menaati ajaran agama untuk menutup aurat. Di sisi lain, mereka terancam dikeluarkan dari sistem pendidikan formal. Diskriminasi yang dialami memunculkan rasa keterasingan, bahkan membentuk kelompok sosial eksklusif di antara sesama siswi berjilbab. Situasi ini makin memanas ketika media mulai memberitakan kasus-kasus penolakan jilbab secara luas.
Pemerintah Orde Baru sempat menanggapi pemakaian jilbab sebagai bagian dari gerakan dakwah yang dipandang dekat dengan politik identitas Islam. Sikap ini tak lepas dari pandangan rezim saat itu yang menganggap ekspresi keislaman yang kuat sebagai potensi ancaman ideologis. Maka, kebijakan seragam sekolah pun dijadikan alat untuk membatasi ruang gerak dakwah Islam di sekolah-sekolah negeri.
Namun, seiring meningkatnya tekanan publik dan kesadaran masyarakat, pemerintah akhirnya melunak. Pada 26 Februari 1991, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan No. 100/C/Kep/D/1991 yang menjadi titik balik polemik jilbab di sekolah. Meski tidak menyebut langsung kata “jilbab”, SK ini menggunakan istilah “seragam khas” yang memberi ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan pakaian siswi berdasarkan pertimbangan agama dan adat istiadat setempat. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 5 Ayat 4, dan secara tersirat mengizinkan pemakaian jilbab di sekolah negeri.
Setelah kebijakan ini diberlakukan, penggunaan jilbab mulai diterima secara luas di lingkungan pendidikan. Siswi-siswi yang sebelumnya mengalami tekanan akhirnya dapat mengenakan jilbab tanpa rasa takut. Dalam waktu singkat, jilbab berubah dari simbol perlawanan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas siswi Muslimah di Indonesia. Kini, mengenakan jilbab di sekolah bukan hanya dibolehkan, tetapi sudah menjadi tren positif yang mencerminkan semangat keagamaan dan kebebasan berekspresi.
NKK/BKK
Daoed mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan nama Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Kebijakan ini menjadi salah satu keputusan paling kontroversial dalam sejarah perguruan tinggi di Indonesia.
Tujuan utama dari NKK/BKK adalah untuk membersihkan kampus dari aktivitas politik praktis. Daoed memandang bahwa dunia kampus seharusnya menjadi ruang akademik yang steril dari kepentingan politik, dan bahwa mahasiswa sebaiknya fokus pada peran utamanya yaitu belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Pandangan ini ia pertegas melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0156/U/1978, yang menandai diberlakukannya program normalisasi kehidupan kampus secara resmi.
Dampak dari kebijakan ini sangat besar. Kampus-kampus negeri yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas kritis mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah mendadak menjadi “zona sunyi politik”. Mahasiswa dilarang keras menggelar kegiatan yang bernuansa politik, dan sanksi berat, termasuk pemecatan, siap dijatuhkan kepada mereka yang melanggar. Tidak hanya itu, Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa (Dema)—dua organ penting dalam kehidupan demokrasi kampus—dibubarkan melalui SK Mendikbud No. 037/U/1979. Sebagai gantinya, pemerintah membentuk Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) yang berada di bawah pengawasan ketat birokrasi kampus dan pemerintah.
Sejak saat itu, kegiatan politik mahasiswa nyaris lumpuh. Ruang untuk menyuarakan aspirasi atau mengkritik kebijakan negara menyempit drastis, bahkan nyaris hilang. Banyak kalangan menganggap bahwa kebijakan NKK/BKK merupakan alat kontrol pemerintah Orde Baru untuk mengekang daya kritis generasi muda, terutama setelah maraknya demonstrasi mahasiswa pada awal 1970-an yang dianggap mengancam stabilitas politik nasional.
Meskipun Daoed Joesoef menyatakan bahwa kebijakan ini murni demi kepentingan akademik dan ketertiban kampus, tak sedikit yang melihatnya sebagai bagian dari strategi pengendalian politik oleh rezim Soeharto. Mahasiswa kehilangan ruang demokratis, sementara kampus menjadi semakin birokratis dan jauh dari semangat kebebasan berpikir.
Wafat
Daoed Joesoef, tutup usia pada Selasa malam, 23 Januari 2018 pukul 23.55 WIB di Rumah Sakit Medistra, Jakarta. Ia wafat dalam usia 91 tahun akibat komplikasi penyakit jantung yang telah lama dideritanya. Sebuah ring telah terpasang di jantungnya sejak usia 73 tahun, dan selama bertahun-tahun, Daoed dikenal sangat menjaga kesehatannya. Bahkan di usia 90, fisiknya masih tampak bugar dan penuh semangat.
Namun, menurut sang menantu, Bambang Pharmasetiawan, kondisi Daoed mulai menurun setelah menyelesaikan bukunya pada November 2017. “Sejak saat itu, Beliau susah sekali dinasihati soal kesehatan,” ujar Bambang di rumah duka, Jalan Bangka VII, Jakarta Selatan, pada Rabu, 24 Januari 2018. Kondisi Daoed memburuk mulai 1 Januari 2018, tetapi ia bersikeras untuk tidak dirawat di rumah sakit. Ia lebih memilih dirawat di rumah, dikelilingi keluarganya.
Keinginan Daoed untuk tetap di rumah didasari oleh cinta dan perhatian terhadap keluarga. Ia ingin merayakan ulang tahun ke-1 cicitnya, Natasha, yang jatuh pada 20 Januari 2018. Baru setelah perayaan sederhana itu selesai, Daoed bersedia dibawa ke rumah sakit. “Beliau sangat sayang kepada cicitnya. Berkali-kali Beliau bilang, tidak pernah menyangka bisa melihat cicit di usia setua itu,” kenang Bambang.
Selama menjalani perawatan, Daoed bahkan meminta agar foto keluarga empat generasi dipajang di sisi tempat tidurnya. Bagi Daoed, momen bisa melihat anak, cucu, hingga cicit adalah kebahagiaan tersendiri yang tak bisa ditukar dengan apapun. Ia wafat dalam ketenangan, dikelilingi keluarga yang mencintainya.
Jenazah Daoed Joesoef dimakamkan di Pemakaman Giri Tama, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu siang setelah salat Zuhur. Ia meninggalkan seorang istri, Sri Sulastri, seorang anak perempuan, Sri Sulaksmi Damayanti, menantu, dua cucu, serta seorang cicit yang sangat ia sayangi. Kepergian Daoed Joesoef bukan hanya duka bagi keluarga, tetapi juga bagi dunia pendidikan Indonesia. Ia adalah simbol intelektual yang teguh, penuh dedikasi, dan telah memberi warna penting dalam perjalanan bangsa.
Sumber:
- Solihat, Amalia, Abdul Syukur, dan Kurniawati. “Kebijakan Kontroversial Menteri Daoed Joesoef 1978–1983: Perubahan Tahun Ajaran dan Libur Bulan Ramadhan.” Jurnal Pendidikan Sejarah, vol. 9, no. 1, Jan. 2020, pp. 55–70. DOI: 10.21009/JPS.091.04. Diakses 16 Juli 2025.
- Riwanto, Abiyyu, dan Iin Nur Zulaili. “Kebijakan Pendidikan Sekuler Era Menteri Pendidikan Daoed Joesoef 1978–1983.” Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization, vol. 6, no. 2, Sept. 2022, pp. 67–81. Diakses 16 Juli 2025.
- “Daoed Joesoef Tak Mau Dibawa ke Rumah Sakit Sebelum Rayakan Ulang Tahun Cicitnya” nasional.kompas.com (diakses pada 3 Agustus 2025)
- “Cerita Daoed Joesoef: Dari Tolak Bank Indonesia Hingga ‘Matikan’ Politik Kampus” asumsi.co (diakses pada 3 Agustus 2025)
- “Sejarah Hidup Daoed Joesoef, Mendikbud yang Pernah Melarang Jilbab” tirto.id (diakses pada 3 Agustus 2025)