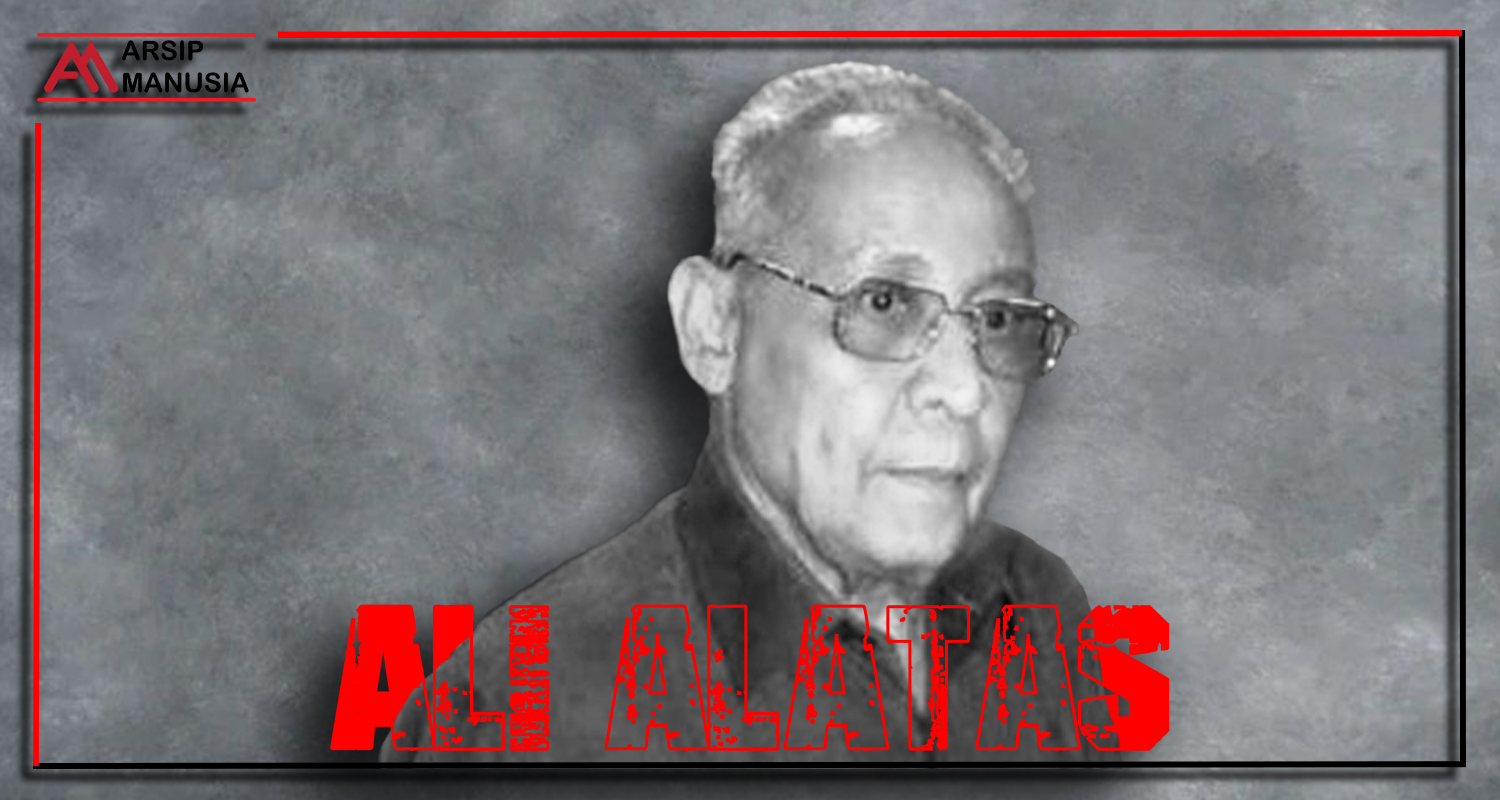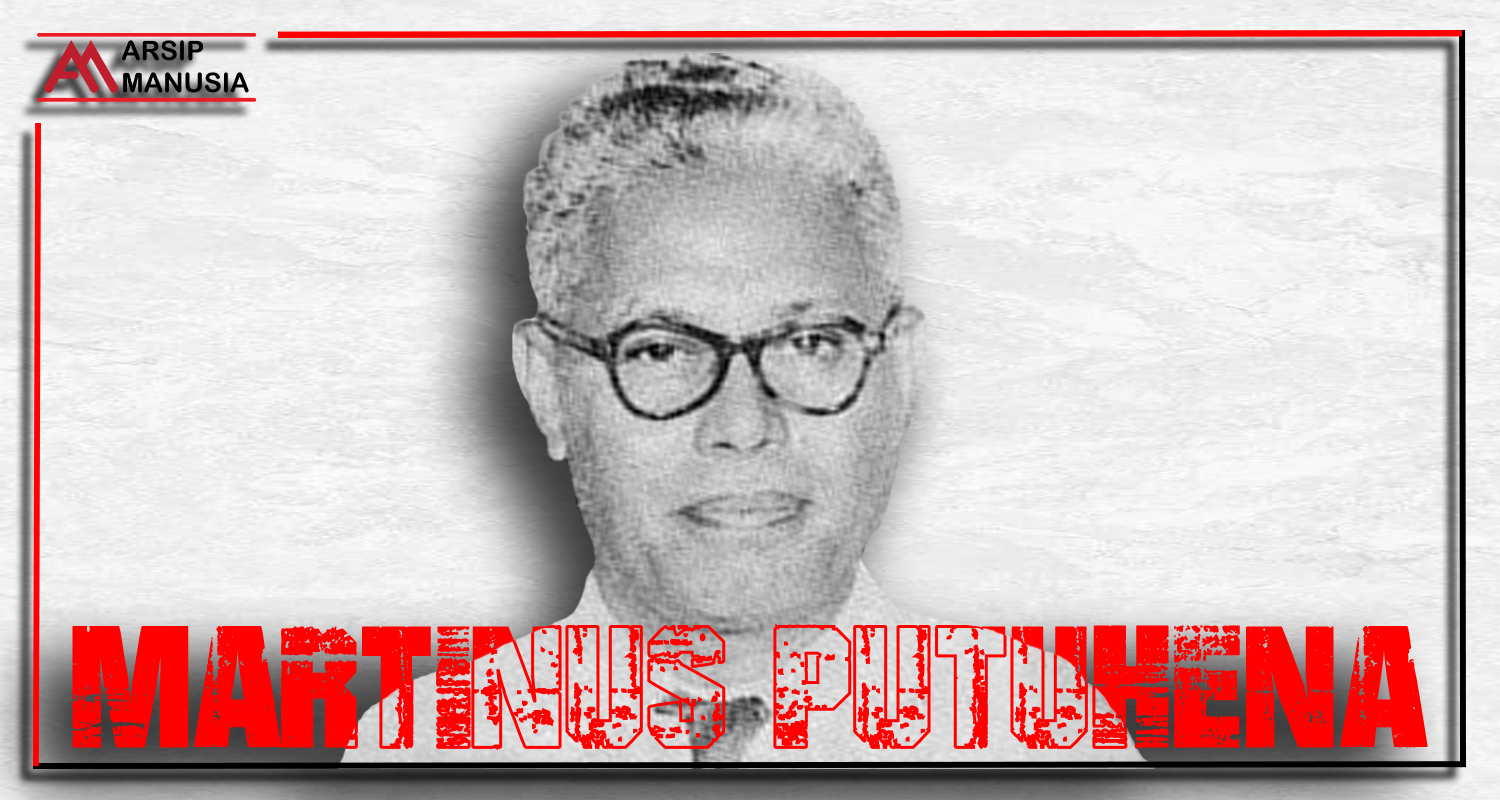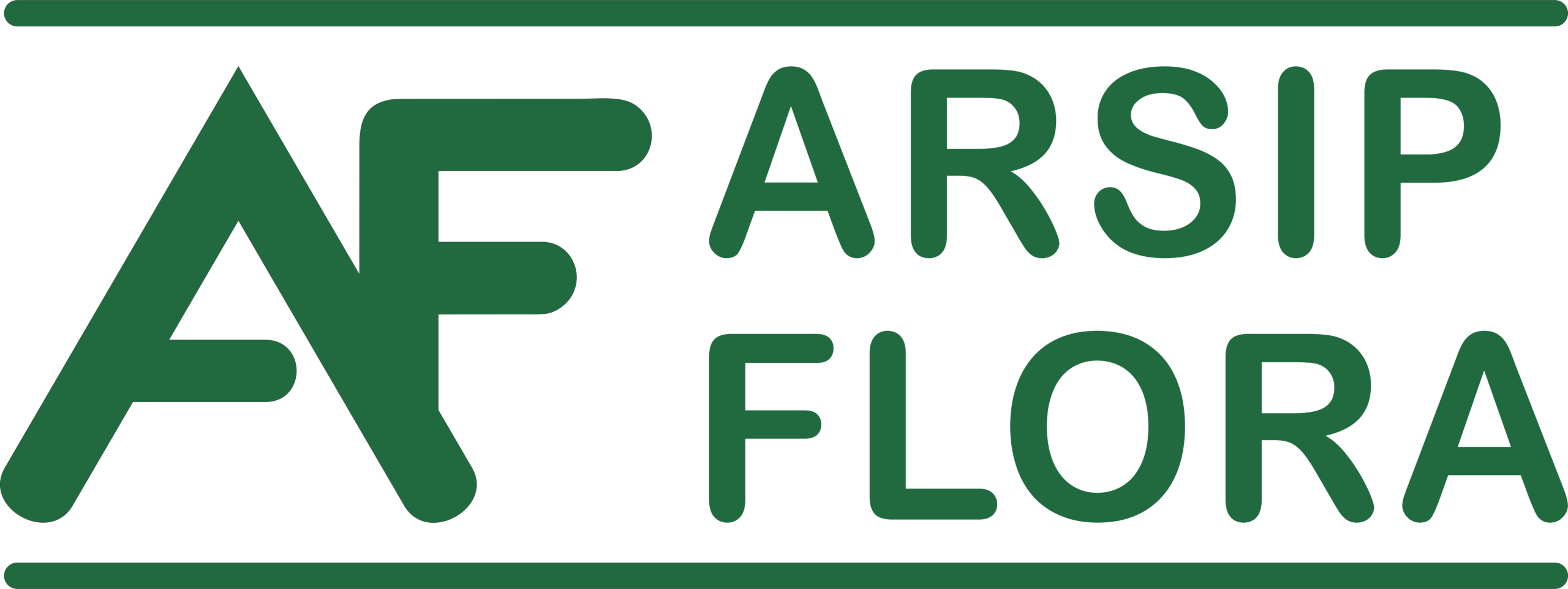KH. Hasan Basri dikenal sebagai ulama yang berpengaruh, pendidik, dan pemimpin organisasi keagamaan, serta pernah menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kiprahnya tidak hanya terbatas pada bidang dakwah, tetapi juga merambah ke dunia politik, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.
Table of Contents
ToggleLatar Belakang Keluarga
KH. Hasan Basri lahir di Moeara Teweh pada 10 Agustus 1920. Ibunya, Siti Fatimah, dikenal sebagai sosok yang dihormati di Kalimantan Tengah dan Selatan. Ia bukan hanya seorang ahli pengobatan tradisional berbahan dasar akar kayu hutan Kalimantan, tetapi juga seorang dukun beranak yang bijaksana dalam memberi nasihat. Siti Fatimah wafat pada tahun 1979 di Jakarta dalam usia 90 tahun. Ia gemar membaca karya-karya Syekh Abdul Qadir Munsyi yang ditulis dalam aksara Jawi (huruf Arab Melayu), mencerminkan kecintaan terhadap ilmu sejak usia dini.
Ayah Hasan Basri wafat ketika ia baru berusia tiga tahun, menjadikannya anak yatim sejak kecil. Ia kemudian diasuh oleh kakeknya, Haji Abdullah, seorang pegawai pengadilan negeri (Landraad) di Banjarmasin yang pensiun pada tahun 1940. Setelah pensiun, sang kakek beralih menjadi petani lalu pedagang. Dalam asuhan kakeknya, Hasan kecil tumbuh dengan disiplin, cinta ilmu, dan semangat untuk menjadi berguna bagi masyarakat. Ia juga memiliki dua saudara kandung, yaitu Haji Thamrin dan Husni Rasyid.
Masa Kecil Hasan Basri
Sejak usia lima tahun, Hasan Basri sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam berbicara. Setiap sore menjelang waktu magrib, ia berdiri di atas meja kecil dan menyampaikan pidato tentang aktivitas hariannya. Seluruh anggota keluarga menjadi pendengar setianya. Kebiasaan ini terus berlangsung hingga usianya 12 tahun, membentuk dasar keterampilan berbicara di depan umum yang kelak menjadi salah satu kekuatannya sebagai ulama dan pemimpin.
“Pendidikan di rumah itu yang menyebabkan saya tidak pernah merasa demam panggung saat berpidato di depan umum,” kenang Hasan Basri.
Selain berbakat bicara, Hasan Basri juga menonjol dalam hal disiplin belajar. Pada tahun 1928, saat usianya delapan tahun, ia mulai bersekolah di Volksschool (Sekolah Rakyat) di Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Jarak sekolah yang jauh dari rumah membuatnya harus berjalan kaki setiap hari, sebab kendaraan seperti sepeda pun masih langka saat itu. Namun, ia menjalani rutinitas tersebut tanpa mengeluh.
Setelah pulang dari Sekolah Rakyat pada siang hari, Hasan Basri masih meluangkan waktu untuk belajar agama di Sekolah Diniyah Awaliyah Islamiyah setiap sore. Ia sangat menyukai pelajaran sejarah, terutama sejak duduk di kelas tiga, ketika ia diizinkan membaca buku sejarah tentang para panglima perang. Hal ini merupakan hal yang istimewa di masa penjajahan Belanda, karena bacaan sejarah bagi anak pribumi sangat dibatasi.
Di luar pendidikan formal, Hasan Basri banyak mendapatkan pelajaran berharga secara nonformal dari kakeknya. Usai salat magrib, bila sang kakek ada di rumah, Hasan diminta naik ke atas meja dan menyampaikan pidato di hadapan keluarga. Ia diminta menyampaikan secara runut dan sistematis apa yang telah dipelajarinya hari itu. Kakeknya pun selalu memberikan evaluasi atas setiap pidato, membenahi kata-kata yang keliru, dan memberi nasihat untuk menjaga pergaulan.
Latihan rutin ini bukan hanya melatih kepercayaan diri dan kemampuan berbicara, tetapi juga daya ingat dan kemampuan menyampaikan pesan secara ringkas dan bermakna. Sejak kecil, Hasan dibiasakan menggunakan bahasa Indonesia, meskipun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitarnya lebih umum menggunakan bahasa Banjar atau bahasa Bakumpai.
Pendidikan di Banjarmasin dan Yogyakarta
Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Rakyat dan melanjutkan pelajaran agama di Diniyah Awaliyah Islamiyah, pada tahun 1935 Hasan Basri melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Atas dukungan kakeknya, ia dipindahkan ke Tsanawiyah Muhammadiyah di Banjarmasin. Saat itu, belum ada asrama yang memadai, sehingga ia tinggal di rumah keluarga.
Kehidupan di Banjarmasin menjadi pengalaman baru bagi Hasan. Ia menghadapi lingkungan yang lebih kompleks dan beragam, baik dari segi sosial, budaya, maupun pola pikir. Kota itu dihuni oleh berbagai suku, yang memperluas wawasannya dan menambah dinamika dalam kehidupan sehari-hari.
Sekolah Tsanawiyah Muhammadiyah di Banjarmasin telah menggunakan pendekatan pendidikan yang lebih modern. Sistem hafalan (tradisional) mulai ditinggalkan, digantikan dengan metode klasikal dan penggunaan buku-buku pelajaran baru. Di sekolah ini, Hasan mulai mengenal karya-karya pemikir besar Islam seperti Imam Al-Ghazali, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Imam Syafi’i. Buku-buku seperti Tarikh al-Tasyri’ al-Islami dan Fiqh menjadi bagian dari materi ajar yang ia pelajari dengan penuh semangat.
Selain belajar di kelas, Hasan juga mendapatkan pelatihan berpidato melalui pelajaran muhadharah, yakni latihan berbicara di depan umum yang menjadi ciri khas sekolah Muhammadiyah. Di sinilah kemampuannya yang telah diasah sejak kecil semakin terasah dalam suasana yang lebih terstruktur.
Pada masa inilah ia pertama kali bertemu dengan Buya Hamka, yang kala itu berkunjung ke Banjarmasin sebagai utusan Muhammadiyah Pusat. Pertemuan itu sangat membekas dan menjadi inspirasi bagi Hasan Basri untuk mengikuti jejak Buya Hamka sebagai dai dan pemikir Islam. Ia mulai membayangkan dirinya suatu hari nanti mampu berpidato dan menyampaikan dakwah di hadapan banyak orang seperti panutannya itu.
Setelah menamatkan pendidikan di Tsanawiyah Muhammadiyah pada tahun 1938, Hasan Basri memperoleh restu dari ibunda dan kakeknya untuk melanjutkan studi ke Pulau Jawa. Sebuah langkah besar, mengingat pada masa itu merantau ke luar pulau merupakan hal yang jarang dilakukan, terutama bagi anak muda dari pedalaman Kalimantan.
Ia pun berangkat ke Yogyakarta dan mendaftarkan diri di Sekolah Zu’ama Muhammadiyah, sebuah lembaga pendidikan yang dirancang untuk mencetak kader ulama dan pemimpin umat. Sekolah ini memiliki orientasi yang lebih maju dan sistematis, bertujuan melahirkan tokoh-tokoh yang mampu memimpin umat dengan pendekatan manajerial dan pemahaman keislaman yang mendalam.
Para pengajar di Sekolah Zu’ama saat itu adalah tokoh-tokoh ternama seperti KH. Mas Mansur, KH. Farid Ma’ruf, Prof. Kahar Muzakir, KH. Baidhowi, dan Buya AR Sutan Mansur. Di bawah bimbingan mereka, Hasan Basri mendapatkan pembekalan ilmu agama, retorika, serta wawasan keorganisasian.
Di luar kegiatan sekolah, ia juga aktif mengikuti kegiatan Partai Islam Indonesia (PII) dan menghadiri rapat-rapat politik. Pemimpin-pemimpin seperti Dr. Sukiman, Wiwoho Purbohadidjoyo, dan KH. Taufiqurrahman menjadi sosok-sosok yang ia perhatikan dan pelajari sepak terjangnya. Dari sini, Hasan Basri tidak hanya berkembang sebagai santri dan calon ulama, tetapi juga mulai memahami dinamika politik dan pentingnya keterlibatan umat Islam dalam kehidupan berbangsa.
Ia menempuh pendidikan di Sekolah Zu’ama selama tiga tahun, sejak tahun 1938 hingga 1941. Masa ini menjadi fondasi intelektual dan spiritualnya yang sangat kuat. Di akhir masa studinya, Hasan Basri sudah dikenal sebagai pemuda yang cerdas, tenang, berwibawa, dan mampu berbicara dengan lugas serta meyakinkan di depan umum.
Setelah lulus, di usia 21 tahun, ia menikah dengan Nurhani, seorang gadis kelahiran 19 Januari 1924. Nurhani juga merupakan lulusan dari bagian puteri Sekolah Zu’ama Muhammadiyah. Bersama sang istri, Hasan Basri kemudian kembali ke kampung halaman di Kalimantan Selatan untuk mulai mengabdikan diri dalam dunia pendidikan dan dakwah.
Awal Perjuangan dan Aktivisme Politik
Kiprah KH. Hasan Basri dalam perjuangan dan dunia pergerakan Islam dimulai sejak masa penjajahan Jepang. Saat itu, ia aktif dalam organisasi Barisan Ulama di Kalimantan Selatan, yang menjadi wadah bagi para tokoh agama untuk menyuarakan semangat kemerdekaan melalui jalur dakwah dan sosial keagamaan. Peran aktifnya dalam organisasi ini menunjukkan bahwa meski masih berusia muda, ia telah memiliki keberanian dan visi kebangsaan yang kuat.
Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, perjuangan belum selesai. Indonesia masih harus menghadapi berbagai ancaman, termasuk upaya Belanda untuk kembali menjajah melalui agresi militer. Dalam situasi genting tersebut, KH. Hasan Basri mengambil bagian dalam perlawanan melalui Laskar Mujahidin Kalimantan Selatan, sebuah pasukan perjuangan bersenjata berbasis keagamaan yang beroperasi di daerah Martapura. Ia tidak hanya berperan sebagai pemuka agama, tetapi juga sebagai pejuang yang turun langsung ke medan konflik demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Pada masa-masa itulah, ketokohan KH. Hasan Basri mulai dikenal luas, terutama karena kemampuannya menjembatani antara peran ulama dengan semangat nasionalisme. Ia aktif menyampaikan khutbah-khutbah yang membangkitkan semangat umat Islam untuk berjuang demi kemerdekaan dan keadilan sosial. Ia juga terlibat dalam menyusun strategi pergerakan bersama tokoh-tokoh lain, baik dari kalangan pesantren maupun pejuang lokal.
Pengalaman berjuang di medan tempur dan di tengah masyarakat yang sedang bangkit dari penjajahan membentuk karakter Hasan Basri sebagai ulama yang tidak hanya paham teks keislaman, tetapi juga mampu merespons tantangan zaman. Pandangannya mengenai hubungan antara agama dan negara pun mulai terbentuk, yang kelak akan menjadi fondasi pemikirannya dalam ranah dakwah dan kebijakan keislaman nasional.
Dakwah dan Organisasi Keislaman
Setelah perjuangan fisik di masa revolusi kemerdekaan mereda, KH. Hasan Basri tidak menghentikan langkahnya. Ia justru mengalihkan fokus pada perjuangan intelektual dan spiritual melalui jalur dakwah serta organisasi keislaman. Bagi Hasan Basri, membangun bangsa tidak hanya melalui senjata, tetapi juga lewat pendidikan moral, penguatan akidah, dan pengorganisasian umat.
Pada era 1950-an, ia mulai dikenal luas sebagai seorang mubalig yang berpengaruh, tidak hanya di Kalimantan Selatan tetapi juga di berbagai wilayah Indonesia. Ceramah-ceramahnya menyentuh berbagai aspek kehidupan umat, mulai dari akhlak, pentingnya persatuan umat Islam, hingga sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Pendekatannya yang lugas namun santun membuat dakwahnya mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.
Puncak kiprahnya dalam organisasi keislaman terjadi ketika ia dipercaya menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada periode 1984–1990. Dalam posisi tersebut, KH. Hasan Basri memainkan peran strategis dalam menjembatani hubungan antara umat Islam dengan pemerintah. Ia berupaya memastikan bahwa aspirasi umat tetap diperhatikan, sekaligus menjaga agar MUI menjadi institusi independen yang memiliki kredibilitas moral dan intelektual.
Salah satu langkah penting yang ia tempuh adalah mendorong penguatan peran MUI sebagai lembaga fatwa dan pembinaan umat, bukan sekadar menjadi alat legitimasi kekuasaan. Di bawah kepemimpinannya, MUI semakin aktif dalam menyikapi isu-isu strategis nasional, termasuk soal ekonomi umat, pendidikan Islam, dan pergaulan global.
Tak hanya di MUI, KH. Hasan Basri juga aktif dalam organisasi-organisasi Islam internasional, yang memperluas pengaruh dan pemikiran Islam Indonesia ke panggung dunia. Ia dikenal sebagai sosok ulama yang mampu berdialog lintas budaya dan agama tanpa kehilangan identitas keislamannya. Hal ini memperkuat posisinya sebagai jembatan antara tradisi keulamaan klasik dengan tantangan zaman modern.
Isu Sosial dan Kebangsaan
KH. Hasan Basri tidak hanya dikenal sebagai tokoh agama, tetapi juga sebagai intelektual muslim yang peduli terhadap kondisi sosial dan kebangsaan. Dalam berbagai kesempatan, ia kerap menyuarakan keprihatinan terhadap problematika sosial yang dihadapi masyarakat, mulai dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, hingga isu-isu keadilan dan hak asasi manusia.
Sikapnya terhadap persoalan kebangsaan selalu berangkat dari nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Ia percaya bahwa agama tidak boleh dipisahkan dari realitas sosial. Karena itu, Hasan Basri tidak ragu bersuara ketika melihat adanya penyimpangan kekuasaan atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai keadilan. Salah satu ciri khas dari perjuangannya adalah keberanian menyampaikan kritik secara santun namun tegas, baik melalui forum keagamaan maupun dalam pernyataan publik.
Sebagai Ketua Umum MUI, ia kerap menjadi juru bicara umat dalam menyikapi berbagai kebijakan negara. Misalnya, ia pernah mengkritik keras praktik-praktik ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat kecil, serta menyoroti lemahnya peran negara dalam menangani kemerosotan moral generasi muda. Dalam isu-isu kebangsaan seperti Pancasila dan UUD 1945, KH. Hasan Basri mengambil posisi yang moderat dan bijak, menekankan bahwa nilai-nilai Islam dan dasar negara tidak harus dipertentangkan, tetapi dapat saling memperkuat.
Peran penting lainnya terlihat ketika ia turut merespons berbagai dinamika politik nasional, terutama dalam masa transisi menjelang Reformasi. Meski telah berusia lanjut, suaranya masih diperhitungkan sebagai moral force. Ia mendorong agar proses demokratisasi dijalankan secara damai dan bermartabat, serta mengingatkan agar reformasi tidak kehilangan arah dan tetap menjunjung etika sosial serta nilai-nilai keagamaan.
KH. Hasan Basri juga aktif membela kelompok-kelompok marginal dan minoritas, menunjukkan bahwa pandangan keislamannya inklusif dan membumi. Ia percaya bahwa Islam hadir untuk membawa keadilan bagi seluruh umat manusia, tanpa memandang suku, ras, maupun agama.
Wafat
KH. Hasan Basri wafat pada tanggal 8 November 1998 di Jakarta, dalam usia 78 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi umat Islam Indonesia dan seluruh bangsa yang telah ia layani dengan penuh dedikasi.
Hasan Basri meninggalkan empat orang anak dan sepuluh cucu, yang masing-masing tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berhasil di bidangnya. Nilai-nilai perjuangan, integritas, dan pengabdian yang diwariskannya terus hidup dan menjadi inspirasi, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat luas.
Sumber:
- “K.H. Hasan Basri: Politikus, Ketua MUI, & Penggagas Bank Muamalat” tirto.id (Diakses pada 5 Agustus 2025)
- “Hasan Basri (Alm), Pelopor Pendirian Bank Tanpa Bunga” kebudayaan.kemdikbud.go.id (Diakses pada 5 Agustus 2025)
- “Ulama Banjar (70): KH. Hasan Basri” alif.id (Diakses pada 5 Agustus 2025)
- “Kehidupan dan Perjuangan KH. Hasan Basri: Seorang Ulama dan Pemimpin” solutif.id (Diakses pada 5 Agustus 2025)