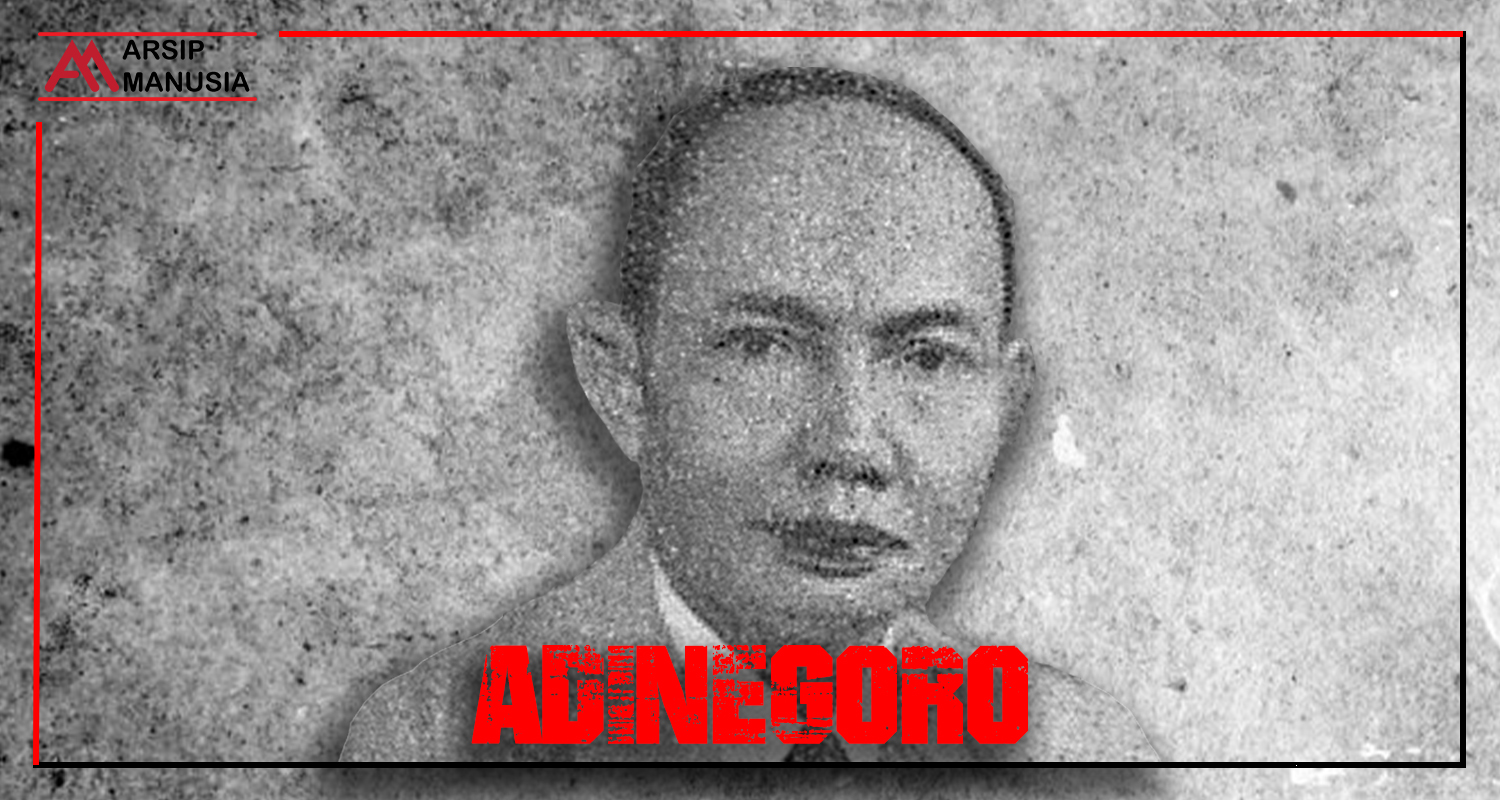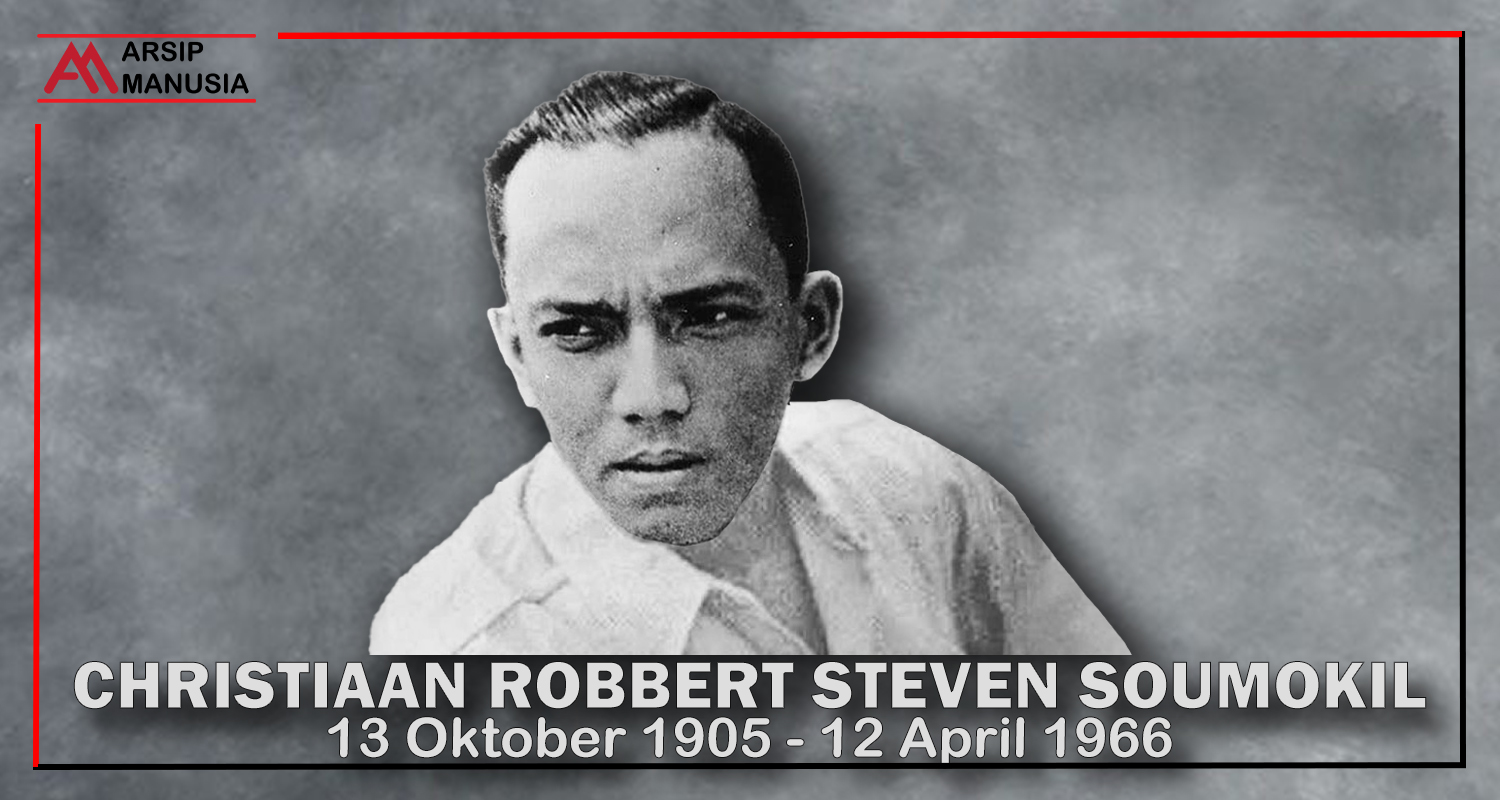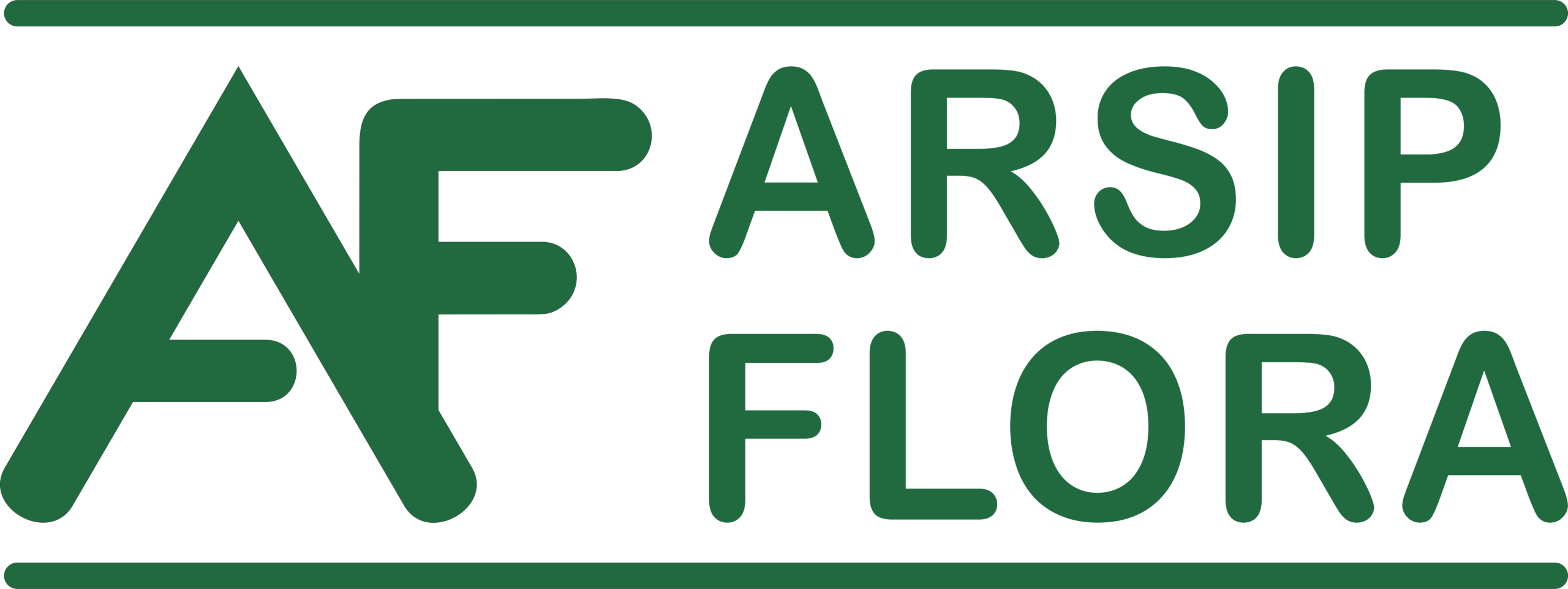Chris Soumokil tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai sosok kontroversial, seorang intelektual hukum yang pada akhirnya berakhir tragis di hadapan regu tembak. Lahir di Ambon, Maluku, Soumokil dikenal bukan hanya karena kecerdasannya sebagai lulusan hukum yang pernah menjabat di pemerintahan Republik Indonesia, tetapi juga karena jabatannya sebagai Presiden Republik Maluku Selatan (RMS), sebuah gerakan separatis yang memproklamasikan kemerdekaan dari Indonesia pada tahun 1950.
Kisah hidupnya tentang pergulatan ideologi, identitas daerah, dan nasib seorang tokoh yang memilih jalan berseberangan dengan arus sejarah bangsa. Dari seorang pejabat negara yang terhormat, Chris Soumokil berubah menjadi pemimpin pemberontakan yang diburu oleh pemerintah pusat. Keputusan-keputusannya membawa dampak besar bagi sejarah Maluku dan perjalanan integrasi Indonesia sebagai negara kesatuan.
Table of Contents
ToggleLatar Belakang Keluarga dan Kehidupan Awal
Christiaan Robbert Steven Soumokil, yang lebih dikenal dengan nama Chris Soumokil, lahir di Surabaya pada 13 Oktober 1905. Ia berasal dari keluarga Maluku yang berpindah ke Jawa karena pekerjaan ayahnya. Ayahnya bekerja sebagai pejabat rendahan di Kantor Pos Semarang, sebuah posisi yang tergolong status sosial kelas menengah pribumi terdidik pada masa Hindia Belanda.
Masa kecil Soumokil diwarnai oleh lingkungan yang disiplin dan religius. Keluarganya memeluk agama Kristen Protestan dan aktif dalam Gereja Reformis, yang pada masa itu memberikan pendidikan dan pembentukan karakter masyarakat Maluku di perantauan.
Tumbuh di tengah kota pelabuhan yang kosmopolit seperti Surabaya dan kemudian Semarang, Soumokil kecil terbiasa dengan keberagaman budaya dan etnis. Pengalaman ini membentuk pandangan terbuka sekaligus kesadaran sosialnya terhadap perbedaan.
Pendidikan
Chris Soumokil menempuh pendidikan dasarnya di sekolah Kristen dan kemudian melanjutkan ke Hogere Burger School (HBS), lembaga pendidikan menengah bergengsi yang kala itu hanya terbuka bagi kalangan terpilih. Lingkungan HBS yang bercorak Kristen dan Belanda menanamkan padanya kedisiplinan, rasionalitas, dan nilai-nilai intelektual Barat yang kuat.
Setelah menyelesaikan pendidikannya di tanah air, Soumokil melanjutkan studi ke Belanda, mengikuti jejak banyak anak pribumi terpelajar pada masa itu. Awalnya ia berniat menempuh pendidikan kedokteran, namun kemudian mengubah pilihannya menjadi studi hukum di Universitas Leiden, salah satu universitas tertua dan paling bergengsi di Eropa.
Di Leiden, Soumokil menonjol sebagai mahasiswa cerdas dan tekun. Ia lulus pada tahun 1934 dan memperoleh gelar Meester in de Rechten (ahli yurisprudensi), yang menjadi landasan karier hukumnya di kemudian hari. Pada masa studinya, ia bergaul dengan para mahasiswa dari berbagai latar belakang, termasuk sejumlah intelektual Indonesia, seperti Kusumaatmadja dan Soepomo.
Selain menimba ilmu, Soumokil juga sempat menjalani wajib militer di Belanda, yang semakin memperkuat kedekatannya dengan kebudayaan dan sistem sosial Negeri Belanda. Pengalaman tersebut, disertai statusnya sebagai warga negara Belanda, turut membentuk cara pandangnya terhadap hukum, politik, dan tata pemerintahan. Dari sinilah mulai tumbuh sikap pro-Belanda dalam dirinya.
Negara Indonesia Timur (NIT)
Setelah menyelesaikan pendidikannya di Belanda, Chris Soumokil kembali ke Hindia Belanda dan memulai kariernya di bidang hukum. Berbekal latar belakang akademik yang kuat serta pengalamannya di Eropa, ia dengan cepat menempati posisi strategis dalam sistem peradilan kolonial sebagai jaksa. Reputasinya sebagai pejabat hukum yang cermat dan tegas membuatnya dikenal di kalangan birokrat dan pemerintahan Hindia Belanda.
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, wilayah timur Nusantara mengalami dinamika politik yang berbeda dari Jawa. Dalam konteks pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) di bawah pengaruh Belanda, Soumokil tampil sebagai salah satu tokoh utama. Ia dipercaya menjabat sebagai Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman NIT, serta sempat menduduki posisi Wakil Perdana Menteri. Jabatan-jabatan tersebut menempatkannya di lingkaran elite pemerintahan federal bentukan Belanda yang berusaha menyaingi kekuasaan Republik Indonesia.
Dalam menjalankan tugasnya, Soumokil dikenal dengan prinsip hukum formal dan loyalitas terhadap sistem yang menjamin stabilitas, sesuatu yang menurutnya diwujudkan oleh Belanda. Sikapnya ini membuat ia sering bersinggungan dengan perwira-perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang datang dari Jawa untuk mengintegrasikan wilayah-wilayah bagian ke dalam Republik Indonesia.
Salah satu keputusan kontroversi yang ia buat adalah memutuskan hukuman mati untuk Wolter Monginsidi, pejuang muda asal Sulawesi Selatan yang dianggap melawan pemerintahan NIT. Tindakan ini mempertegas posisi politik Soumokil yang cenderung federalis dan pro-Belanda, bertolak belakang dengan semangat unitaris Republik Indonesia yang ingin mempersatukan seluruh wilayah bekas Hindia Belanda.
Situasi politik pasca-kemerdekaan ketika itu memang penuh ketegangan. Terjadi dualisme kekuasaan antara kubu Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta dan negara-negara bagian bentukan Belanda seperti NIT. Dalam konflik politik tersebut, Soumokil berdiri di pihak federalis.
Republik Maluku Selatan (RMS)
Lahirnya Republik Maluku Selatan (RMS) pada tahun 1950 tidak dapat dilepaskan dari situasi politik yang tegang pasca pembubaran Negara Indonesia Timur (NIT) dan upaya pemerintah pusat untuk mengintegrasikan seluruh negara bagian ke dalam Republik Indonesia Serikat (RIS).
Bagi sebagian kalangan di Maluku, terutama mereka yang pernah menjadi bagian dari tentara Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) dan pejabat NIT, integrasi ini dianggap sebagai ancaman terhadap posisi sosial dan keamanan mereka.
Dalam konteks ketegangan tersebut, muncul gerakan separatis di Ambon yang menolak integrasi ke Republik Indonesia. Chris Soumokil, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri NIT, menjadi salah satu tokoh pembentukan gerakan ini.
Pada 25 April 1950, RMS secara resmi dideklarasikan di Ambon, dengan Soumokil sebagai penyusunan deklarasi dan pembentukan struktur pemerintahan awal.
Tak lama setelah deklarasi, pada 3 Mei 1950, Soumokil diangkat menjadi Presiden Republik Maluku Selatan, menggantikan Johannes Manuhutu yang sebelumnya menjabat sebagai kepala negara sementara. Di bawah kepemimpinan Soumokil, RMS berusaha memperoleh pengakuan internasional dan mempertahankan keberadaannya melalui dukungan sebagian mantan anggota KNIL yang masih bersenjata.
Pemerintah pusat Republik Indonesia menanggapi deklarasi RMS dengan tegas namun berhati-hati. Awalnya, Presiden Soekarno menugaskan Dr. J. Leimena, seorang tokoh Maluku yang dekat dengan pemerintah, untuk melakukan pendekatan damai dan membuka ruang dialog agar konflik tidak meluas. Namun, upaya diplomatik tersebut gagal, karena pihak RMS tetap bersikeras mempertahankan proklamasinya dan menolak integrasi dengan Indonesia.
Akhirnya, pemerintah pusat memutuskan untuk mengambil tindakan militer. Sebuah operasi militer dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang dari TNI dikirim ke Ambon untuk menumpas pemberontakan. Operasi tersebut menjadi awal dari pertempuran sengit di Maluku yang menandai babak baru dalam sejarah konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan Republik Maluku Selatan.
Perlawanan dan Gerilya di Maluku
Setelah operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang berhasil menaklukkan Ambon pada akhir tahun 1950, kekuatan utama Republik Maluku Selatan (RMS) runtuh. Pemerintahan RMS kehilangan kendali atas wilayah, dan banyak tokohnya melarikan diri atau menyerah.
Namun, Chris Soumokil menolak untuk menyerah. Ia bersama sisa pasukannya melarikan diri ke Pulau Seram, wilayah yang dikenal dengan medan hutan lebat dan pegunungan terjal, sulit dijangkau oleh pasukan pemerintah.
Di Pulau Seram inilah Soumokil memimpin perlawanan gerilya yang berlangsung selama lebih dari dua belas tahun. Meski kekuatannya semakin kecil, semangat perlawanan RMS tetap hidup di kalangan pengikutnya yang sebagian besar berasal dari bekas prajurit KNIL dan masyarakat lokal yang setia. Mereka berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain, membentuk basis kecil, dan terus berupaya mempertahankan simbol perlawanan terhadap pemerintahan pusat.
Kondisi medan di Pulau Seram yang berat memberikan keuntungan bagi pasukan RMS dalam bertahan hidup. Mereka memanfaatkan hutan rimba, sungai, dan perbukitan sebagai tempat persembunyian alami. Namun, kehidupan di pedalaman yang serba terbatas membuat gerilya ini juga diwarnai penderitaan dan keterbatasan logistik.
Bagi pemerintah Indonesia, menghadapi gerilya RMS di Seram bukanlah perkara mudah. Operasi militer yang dilancarkan berulang kali menghadapi kesulitan dalam menjangkau markas tersembunyi Soumokil dan para pengikutnya. Selama bertahun-tahun, Soumokil berhasil menghindari penangkapan, menjadikannya simbol perlawanan yang masih membayangi stabilitas keamanan di Maluku bagian tengah.
Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, kekuatan RMS semakin melemah. Minimnya dukungan dari luar negeri serta berkurangnya pasokan dan personel membuat perlawanan itu perlahan kehilangan daya.
Operasi Penangkapan Chris Soumokil
Setelah bertahun-tahun melakukan perlawanan di Pulau Seram, keberadaan Chris Soumokil akhirnya menjadi prioritas utama bagi pemerintah Republik Indonesia. Pada 10 Mei 1963, Markas Besar TNI di Jakarta mengeluarkan perintah untuk menangkap pemimpin Republik Maluku Selatan (RMS) itu secepat mungkin. Perintah tersebut dilaksanakan oleh Brigade Infanteri 15 Tirtayasa dari Kodam Siliwangi, di bawah komando Letnan Kolonel Musa Natakusumah. Brigade ini terdiri atas tiga batalyon utama: Batalyon 310, Batalyon 315, dan Batalyon 320 Badak Putih.
Operasi militer di Pulau Seram berlangsung lama. Hingga memasuki bulan keenam, pasukan belum juga berhasil menemukan tempat persembunyian Soumokil. Medan hutan yang lebat, kondisi geografis yang berat, dan taktik berpindah-pindah membuat pencarian semakin sulit. Dalam situasi inilah, Letkol Musa menugaskan satu satuan khusus dari Peleton Cadangan Batalyon 320 Badak Putih, di bawah pimpinan Pembantu Letnan Dua (Pelda) Rukhiyat S., untuk menjadi tim pemburu utama.
Tim kecil ini bergerak pada 29 November 1963 menuju kawasan Kompleks H. Asinepe yang dicurigai menjadi basis persembunyian Soumokil. Setelah sehari penuh melakukan penyisiran, mereka melihat asap mengepul di kejauhan, tanda adanya aktivitas manusia. Namun, ketika lokasi itu didekati, tak ditemukan tanda-tanda kehidupan. Malam harinya, sekitar pukul 21.00, terdengar suara orang menebang pohon sagu, pertanda adanya aktivitas di dekat posisi pasukan.
Menyadari pentingnya kesempatan itu, Pelda Rukhiyat segera memerintahkan satu regu pengintai yang dipimpin Sersan Dua M. Suratman untuk menyelidiki sumber suara. Dengan penuh kehati-hatian, regu itu bergerak senyap di tengah kegelapan malam dan baru mencapai jarak sekitar 50 meter dari sasaran menjelang pukul 01.00 dini hari. Pasukan TNI memutuskan menunggu hingga para gerilyawan tertidur sebelum melakukan penyergapan.
Sekitar pukul 05.00 pagi, 2 Desember 1963, ketika sebagian penghuni gubuk mulai terbangun, pasukan Rukhiyat bergerak cepat mengepung lokasi. Penyergapan berlangsung tanpa satu pun peluru ditembakkan. Para pengikut Soumokil menyerah tanpa perlawanan, dan di antara mereka ditemukan senjata api jenis Lee Enfield dan Owen Gun.
Dalam buku Bintang Sakti Maha Wira Ibu Pertiwi tercatat bahwa Pelda Rukhiyat sendiri yang memasuki gubuk tempat Soumokil tidur. Ia menunggu hingga sang pemimpin RMS itu terbangun, kemudian menangkapnya tanpa perlawanan. Penangkapan itu menjadi akhir dari perjalanan panjang gerilya selama lebih dari dua belas tahun.
Sore harinya, Soumokil dan para pengikutnya digelandang ke Pantai Sawai, sebelum diserahkan kepada Komandan Kompi dan selanjutnya kepada Komandan Batalyon 320, Mayor Enjo Martadisastra. Dari sana, mereka dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Operasi ini kemudian dikenal sebagai bagian dari “Operasi Djala”, yang menjadi catatan penting dalam sejarah militer Indonesia. Keberhasilan pasukan di bawah komando Pelda Rukhiyat ini menandai berakhirnya perjuangan bersenjata RMS di tanah Maluku yang telah berlarut-larut sejak 1950.
Persidangan dan Eksekusi
Setelah tertangkap pada awal Desember 1963, Chris Soumokil segera dibawa ke Jakarta untuk menjalani proses hukum. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengadilinya di hadapan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub), lembaga yang kala itu digunakan untuk mengadili kasus-kasus pemberontakan dan kejahatan terhadap negara.
Persidangan dimulai pada April 1964, dengan perhatian publik yang cukup besar. Soumokil didakwa sebagai dalang dan pemimpin pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), yang selama bertahun-tahun menentang kedaulatan Republik Indonesia. Dalam sidang tersebut, ia didampingi oleh Mr. Pierre-William Blogg, seorang pengacara Belanda sekaligus teman lamanya semasa kuliah di Universitas Leiden.
Sepanjang proses persidangan, Soumokil menunjukkan sikap yang keras dan tak menyesal atas tindakannya. Ia bersikeras berbicara dalam bahasa Belanda, meskipun hakim dan jaksa memintanya menggunakan bahasa Indonesia. Tindakan ini dipandang banyak pihak sebagai simbol ketidakmauannya mengakui otoritas Republik Indonesia.
Dengan latar belakang hukum yang kuat, Soumokil kerap menjawab pertanyaan pengadilan secara logis dan tenang, tetapi tetap menunjukkan keyakinannya bahwa perjuangan RMS adalah sah.
Setelah melalui serangkaian sidang dan pemeriksaan saksi, Mahkamah Militer Luar Biasa menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Chris Soumokil. Putusan ini dianggap sebagai bentuk keadilan negara terhadap tindakan pemberontakan bersenjata yang telah memakan banyak korban.
Eksekusi terhadap Soumokil dilaksanakan pada 12 April 1966 oleh regu tembak Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, terdapat perbedaan sumber mengenai lokasi pelaksanaan eksekusi. Soumokil di eksekusi di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu.
Kabar eksekusi tersebut membawa duka mendalam bagi keluarganya. Istri Soumokil dikisahkan tidak pernah memaafkan pemerintah Indonesia atas hukuman mati yang dijatuhkan kepada suaminya.
Bagi keluarga dan sebagian simpatisan RMS di pengasingan, Soumokil dipandang sebagai martir perjuangan. Namun bagi pemerintah Indonesia, eksekusi itu menandai berakhirnya satu bab kelam dalam sejarah pemberontakan di wilayah Maluku.
Sumber:
- “Christian Soumokil dan RMS: Sejarah Pelik Separatisme Maluku” tirto.id (Diakses pada 13 Oktober 2025)
- “Mengenal Dr. Chris Soumokil, Keluarga Terdidik Dari Negeri Booi” titastory.id (Diakses pada 13 Oktober 2025)
- “Chris Soumokil, Proklamator Republik Maluku Selatan” www.tempo.co (Diakses pada 13 Oktober 2025)
- “Siapa Pemimpin Pemberontakan RMS? Ini Sosoknya” kumparan.com (Diakses pada 13 Oktober 2025)
- “Menjaring Soumokil” historia.id (Diakses pada 13 Oktober 2025)
- “Christiaan Robbert Steven Soumokil Memproklamasikan Republik Maluku Selatan (RMS)” djawanews.com (Diakses pada 13 Oktober 2025)
- “Christiaan Robbert Steven Soumokil” cekricek.id (Diakses pada 13 Oktober 2025)
- “Pasukan Siliwangi Tangkap Presiden RMS, Buronan Paling Dicari Selama 13 Tahun” www.merdeka.com (Diakses pada 13 Oktober 2025)
- “Kekeceweaan Pada Negara Federal yang Memicu Gerakan Republik Maluku Selatan” intisari.grid.id (Diakses pada 13 Oktober 2025)
- “Christian Robert Steven Soumokil” tirto.id (Diakses pada 13 Oktober 2025)
- “Christiaan Robbert Steven Soumokil, Pemimpin Pemberontakan RMS” www.kompas.com (Diakses pada 13 Oktober 2025)