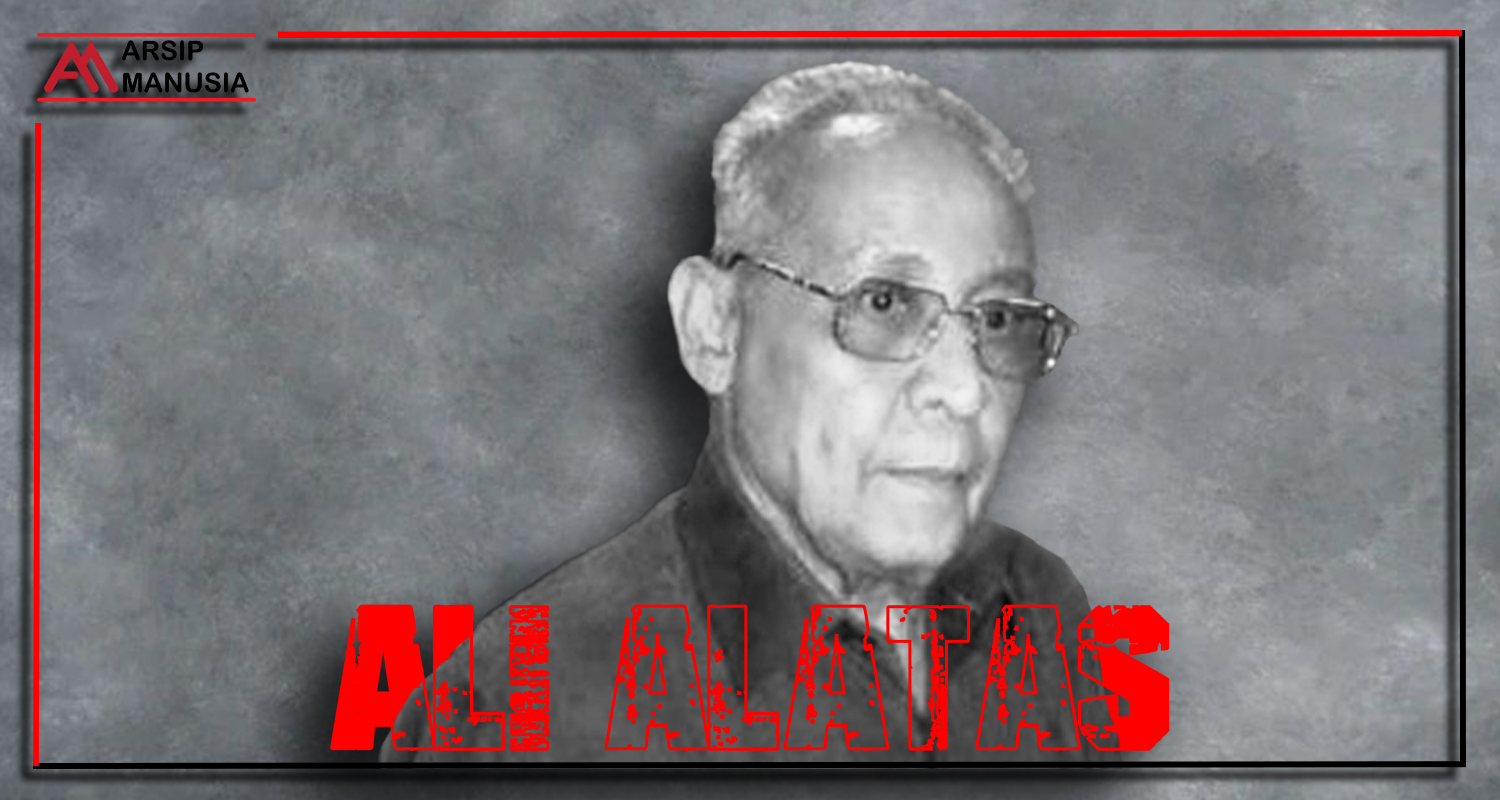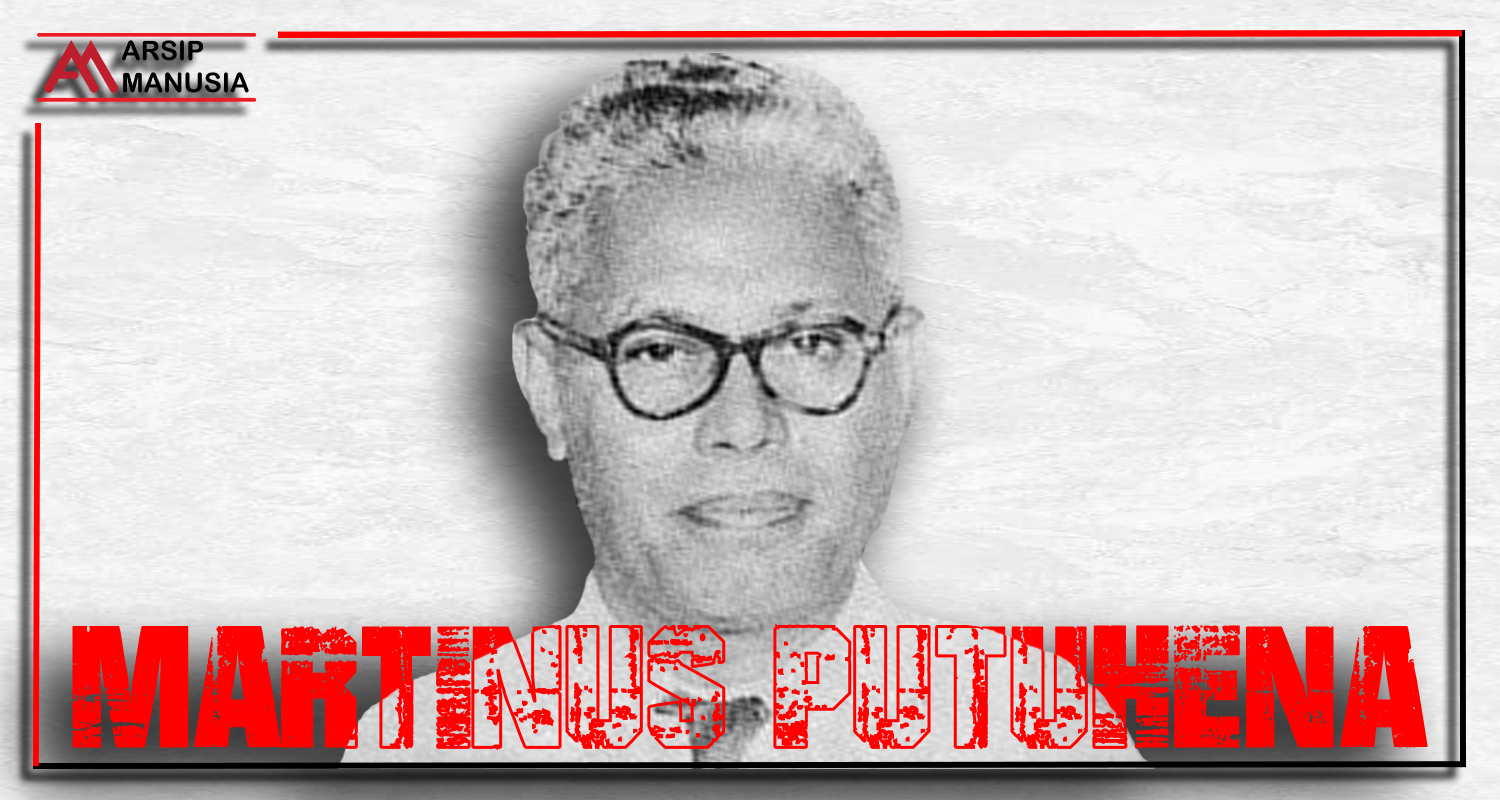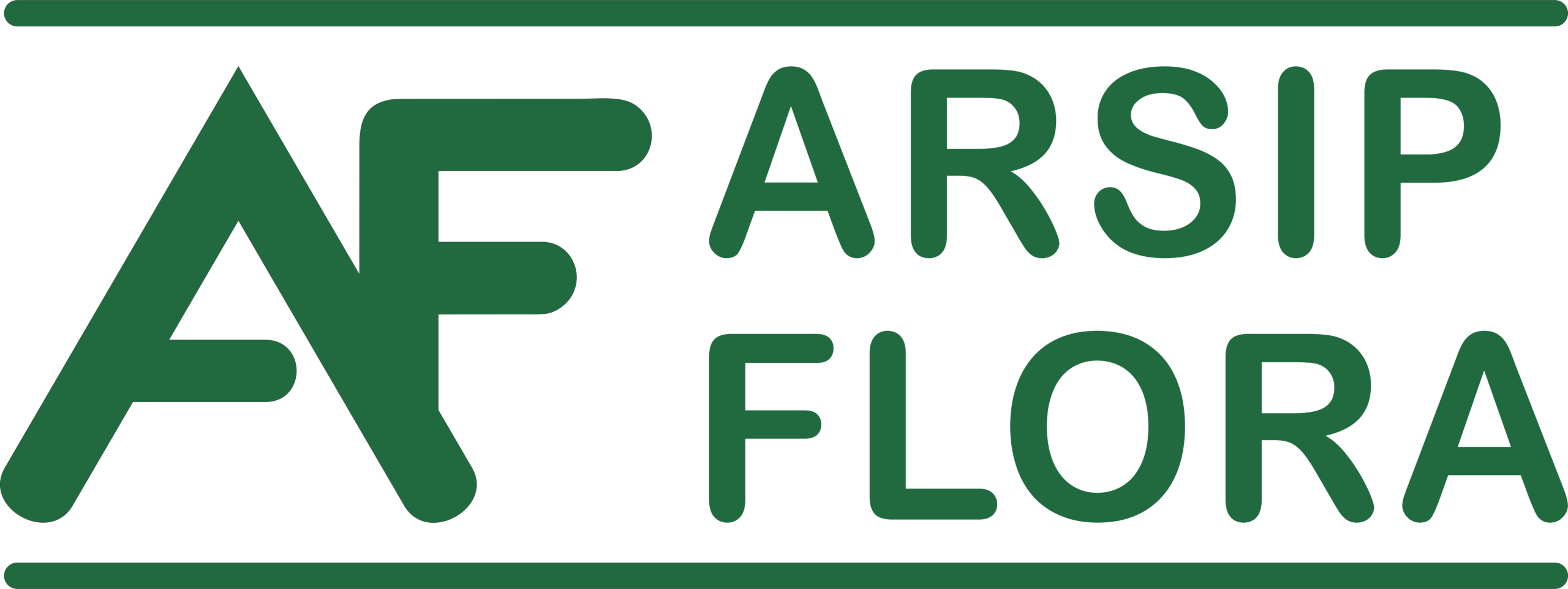Djuanda Kartawidjaja, pahlawan nasional yang dikenal melalui Deklarasi Djuanda, lahir pada 14 Januari 1911 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Beliau menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-10 dan terakhir dari 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959, setelah itu memegang jabatan Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja I.
Selama masa kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri, Ir. H. R. Djuanda Kartawidjaja menyusun Deklarasi Djuanda tahun 1957. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa laut yang mengelilingi, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia merupakan bagian integral dari wilayah NKRI.
Hal ini dikenal sebagai negara kepulauan dalam kerangka Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on Law of the Sea/UNCLOS).
Table of Contents
ToggleAwal Kehidupan
Ir. H. Djuanda Kartawidjaya, yang dihormati sebagai pahlawan, lahir pada 14 Januari 1911 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Meskipun terdapat dua versi mengenai tanggal kelahirannya, dengan dokumentasi di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang mencatat 10 Juli, penyesuaian tanggal lahir mungkin terjadi pada masa itu untuk memenuhi syarat masuk sekolah karena faktor usia yang belum memadai.
Anak dari Raden Kartawidjaya dan Nyi Momot, Djuanda berasal dari keluarga dengan latar belakang ayahnya yang seorang guru di Leles, sebuah kecamatan di Garut, dan ibunya Nyi Momot yang berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Djuanda memiliki dua saudari perempuan, Djuandi dan Koswara, serta satu saudara laki-laki, Dadang.
Ayahnya awalnya seorang guru dan kemudian diangkat sebagai mantri guru di Hollands Inlandse School (HIS), dengan tingkat jabatan mantri guru yang lebih tinggi dari guru.
Pada masa tersebut, guru memiliki status sosial yang dihormati, dan masyarakat sangat menghargai peran seorang guru, terutama jabatan mantri guru, karena dianggap sebagai jasa dalam memajukan dan mendidik anak bangsa.
Riwayat Pendidikan
Djuanda memulai pendidikannya di Hollandse Inlandse School (HIS), tempat ayahnya mengajar. Setelah melewati sejumlah perubahan di sistem pendidikan, termasuk pindah dari HIS ke Eouropese Lagere School (ELS), Djuanda menunjukkan prestasi gemilang dan lulus lebih awal pada tahun 1924.
Selanjutnya, Djuanda melanjutkan pendidikan di Hogere Burgerlijke School (HBS) dan kemudian Technische Hoge School Bandung (THS), yang sekarang dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung (ITB).
Djuanda berhasil mendapatkan beasiswa pemerintah untuk membiayai studinya di THS. Dia menunjukkan ketekunan dalam belajar, menguasai empat bahasa asing, dan aktif dalam kegiatan perkuliahan serta organisasi mahasiswa.
Pada saat itu, suasana politik di Indonesia semakin memanas, terutama dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan pidato pembelaan Ir. Soekarno pada tahun 1930. Djuanda mulai terlibat dalam kegiatan nasionalis, menjadi ketua Indonensische Studenten Vereniging (ISV), sebuah perkumpulan pelajar Indonesia di THS.
Meskipun ada ketegangan politik, pengaruhnya terhadap mahasiswa di THS tidak begitu besar dibandingkan dengan institusi pendidikan lainnya.
Dengan tekadnya, Djuanda berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya pada tahun 1933 dan meraih gelar Civil Ingenieur (Insinyur Sipil). Kelulusannya menjadi suatu kebanggaan bagi keluarga dan komunitasnya.
Organisasi Muhammadiyah
Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta dengan tujuan memberantas penjajahan dan menanamkan sifat cinta terhadap tanah air. Organisasi ini menggabungkan sistem sekolah dan pesantren, memadukan ajaran Islam dengan pengetahuan umum.
Muhammadiyah banyak membangun fasilitas umum, termasuk pendidikan. Djuanda, setelah lulus dari THS, mencari pekerjaan di Jakarta pada masa krisis ekonomi Hindia Belanda tahun 1930an. Ia menikahi Julia dan memiliki empat anak.
Djuanda bekerja di sebuah sekolah Muhammadiyah dan menunjukkan perkembangan karier yang pesat. Belanda kemudian memberlakukan kebijakan pengawasan ketat terhadap sekolah, menyebabkan pertentangan dengan pergerakan nasionalis. Djuanda menjabat sebagai direktur sekolah selama lima tahun dan berhenti pada tahun 1939 setelah perekonomian membaik.
Djuanda, sebagai anggota Muhammadiyah, mendirikan sekolah tinggi sosial ekonomi Muhammadiyah dan memberikan bantuan dana. Pada tahun 1936, ia mendukung pendirian madrasah dan tetap diakui sebagai anggota Muhammadiyah.
Djuanda pernah mengikuti muktamar Muhammadiyah dan dalam wawancara, ia menyatakan bahwa ia hanya menjadi anggota Muhammadiyah dan tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Djuanda meninggal pada tahun 1963 setahun setelah menghadiri muktamar Muhammadiyah terakhirnya.
Paguyuban Pasundan
Paragraf tersebut menggambarkan perjalanan Djuanda dalam kehidupan politiknya. Awalnya, minatnya terhadap kemasyarakatan tumbuh saat ia membaca surat kabar harian Sipatahoenan yang diterbitkan oleh Pagoeyoeban Pasoendan (PP) ketika ia masih di HBS.
PP, organisasi Sunda yang masih aktif hingga saat ini, bergerak dalam berbagai bidang seperti pendidikan, sosial ekonomi, budaya, dan kepemudaan.
Meskipun Djuanda baru bergabung dengan PP pada tahun 1934 setelah lulus dari THS, kecintaannya terhadap tanah kelahirannya, Sunda, dan latar belakang keagamaannya membuatnya merasa cocok bergabung dengan organisasi tersebut. PP, pada saat itu, memiliki 52 cabang dan lebih dari tiga ribu anggota.
Djuanda memandang PP sebagai tempat untuk memperdalam ilmu, terutama dalam bidang politik, dan dia diperkenalkan dengan beberapa tokoh, seperti Otto Iskandar Dinata, yang memberikan dukungan dan merekomendasikannya untuk masuk sekolah Muhammadiyah.
Dalam PP, Djuanda mengalami kenaikan pangkat dari sekretaris II menjadi sekretaris I dengan cepat. Artikel yang ditulisnya, berjudul “Suatu Tindakan yang Bijaksana Bahwa Pemerintah Memberikan Jabatan Kepemimpinan Pada Para Akademisi Indonesia,” mencerminkan keprihatinan Djuanda terhadap krisis ekonomi, politik, dan sosial yang dialami masyarakat.
Djuanda menyampaikan pandangannya bahwa pemerintah seharusnya memberikan jabatan kepemimpinan kepada para akademisi Indonesia.
Pengalaman Djuanda di PP membentuknya sebagai seorang yang cerdas dan tanggap dalam bidang politik. Ia juga terlibat dalam mengkritik kebijakan pemerintah terkait krisis ekonomi dan masalah sosial. Aktivitasnya dalam organisasi ini memberikan landasan bagi kemajuan karirnya serta membentuk pemikiran nasionalis dan progresif untuk Indonesia ke depannya.
Djawatan Kereta Api dan Menteri Muda Perhubungan
Ir. Djuanda berhasil merebut kantor kereta api dari tangan Jepang pada bulan September 1945. Pada saat Ir. Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Ir. Djuanda memimpin gerakan untuk merebut kantor kereta api tersebut. Semangat perjuangan Ir. Djuanda bersama pemuda Bandung pada saat itu berhasil menguasai dan merebut kantor kereta api dari kekuasaan Jepang.
Usaha perlawanan Ir. Djuanda mendapatkan apresiasi dari pemerintah Indonesia karena posisi Ketua Djawatan Kereta Api kosong sejak tahun 1945. Oleh karena itu, pemerintah menunjuk Ir. Djuanda sebagai Ketua Djawatan Kereta Api pada 31 Januari 1946 melalui Maklumat Kementrian Perhubungan No./KA tanggal 23 Januari 1946.
Pelantikan Ir. Djuanda dilakukan secara tidak resmi, hanya melalui Maklumat Kementrian Perhubungan No./KA tanggal 23 Januari 1946 yang ditandatangani oleh Presiden Ir. Soekarno. Sejak saat itu, Ir. Djuanda langsung bergabung dengan staf DKA lainnya di Bandung.
Namun, kejadian tragis Bandung Lautan Api pada 23 Maret 1946 menyebabkan evakuasi massal dan pengosongan kantor dinas di Bandung. Akibat peristiwa tersebut, kantor DKA yang baru beroperasi dipindahkan ke Cisurupan, Jawa Barat.
Ir. Djuanda dihadapkan pada tugas berat untuk melakukan revolusi di bidang kereta api, mulai dari memperbaiki fasilitas, stasiun, hingga perumahan karyawan DKA, serta melakukan perbaikan pada gerbong kereta api yang sudah tidak layak pakai.
Program revolusi pengadaan lokomotif kereta api yang diinisiasi oleh Djawatan Kereta Api melibatkan perbaikan jalur kereta api yang sebelumnya dibongkar oleh Jepang, seperti Pengandaran-Cijulang sepanjang 22 km, Purwosari-Kartosuro 12 km, Purwodadi-Ngemplak 10 km, Kutoarjo-Purworejo 12 km, Kudus-Bangkalan 24 km, Plumpang-Tuban 22 km, dan Ponorogo-Slahung 26 km.
Ir. Djuanda, yang bertanggung jawab dengan baik selama menjabat sebagai Ketua Djawatan Kereta Api, mendapatkan kepercayaan dari Perdana Menteri Sjahrir untuk bergabung dalam kabinet.
Beliau diangkat menjadi Menteri Muda Perhubungan, menjadikan jabatan rangkap antara Ketua Djawatan Kereta Api dan Menteri Muda Perhubungan yang dimiliki oleh Ir. Djuanda. Dengan jabatan ganda tersebut, menunjukkan pengakuan akan kemampuan Ir. Djuanda dalam membangun pemerintahan di Indonesia.
Sebagai Ketua Djawatan Kereta Api, Ir. Djuanda berhasil mengadakan pertemuan antar staf DKA di seluruh Jawa, yang diselenggarakan di Solo.
Pada masa tersebut, sistem kereta api di pulau Jawa terbagi menjadi tiga daerah, yakni DKA bekas SS (Staatsspoor-DKA Hindia Belanda) di Jawa Barat, bekas perusahaan kereta api swasta di Jawa Tengah, dan bekas SS (Staatsspoor-DKA Hindia Belanda) di Jawa Timur.
Ketiga daerah ini menghadapi masalah masing-masing dan bekerja secara terpisah tanpa adanya kerjasama antara satu DKA daerah dengan DKA daerah lain, khususnya dalam hal bahan bakar kereta api.
Salah satu permasalahan yang dibahas adalah mengenai bahan bakar kereta api, dan setelah rapat selesai, diambil keputusan untuk saling membantu dalam pembangunan kereta api di Indonesia, terutama di pulau Jawa.
Menteri Perhubungan
Kabinet Sjahrir III terbentuk setelah PM Sjahrir kembali dari penculikan oleh kelompok oposisi, yang kemudian diberi mandat oleh Ir. Soekarno untuk membentuk kabinet baru dengan nama Kabinet Sjahrir III. Ir. Djuanda, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perhubungan di Kabinet Sjahrir II, kembali mendapat tugas yang sama dalam kabinet ini.
Sebagai Menteri Perhubungan, Ir. Djuanda terus fokus pada pembangunan dalam berbagai sektor transportasi. Setelah memperbaiki infrastruktur transportasi darat, khususnya kereta api, Ir. Djuanda melanjutkan dengan pembangunan transportasi laut, yang dianggap sebagai moda transportasi penting selain kereta api.
Meskipun telah dibentuk Djawatan Oeroesan Laoet Seloeroeh Indonesia (DJOLSI) untuk mengatasi masalah di bidang pelayaran, transportasi laut tidak berkembang sesuai harapan.
Tidak adanya kemajuan dalam transportasi laut membuat Ir. Djuanda beralih untuk memprioritaskan pembangunan dalam sektor transportasi darat. Terjadi perbaikan dan pembangunan fasilitas seperti pengadaan dan perbaikan gerbong kereta api, pembuatan dan perbaikan jalur rel baru, serta rekonstruksi stasiun kereta api dan jalan raya.
Pembangunan fasilitas pendukung transportasi darat mengalami hambatan akibat pemberontakan menentang penandatanganan perjanjian Linggarjati oleh PM Sjahrir.
Pemberontakan ini tidak hanya terjadi selama masa Kabinet Sjahrir III, tetapi juga menyebabkan perpecahan di antara anggota kabinet. PM Sjahrir mengundurkan diri, dan pada 27 Juni 1947, pemerintahan kembali diambil alih oleh Presiden.
Ir. Djuanda kembali dipercayakan sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Amir Syarifuddin I dan II. Kepercayaan ini mencerminkan kualitas tanggung jawab dan kapabilitas kerja yang baik. Meskipun tidak berafiliasi dengan partai tertentu, Ir. Djuanda terus menunjukkan kinerja yang berkualitas.
Kabinet Amir Sjarifuddin II mengalami kesulitan dalam perundingan Renville, menyebabkan pembubaran kabinet tersebut dan digantikan oleh Kabinet Hatta I. Wakil Presiden Moh Hatta membentuk kabinet baru pada 24 Januari 1948, dan Ir. Djuanda diangkat kembali sebagai Menteri Perhubungan.
Ir. Djuanda menjadi delegasi Indonesia dalam perjanjian dengan Belanda, termasuk perjanjian Renville dan Kaliurang. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan dari Belanda. Di dalam negeri, terjadi pemberontakan PKI Madiun 1948 yang dipimpin oleh Musso dan Amir Sjarifuddin, menjadi salah satu masalah internal pada masa Kabinet Hatta I.
Menteri di RIS
Kabinet Hatta I mengalami perombakan, dan sejak 4 Agustus 1949, Ir. Djuanda ditunjuk sebagai Menteri Negara. Dalam Kabinet Hatta II, terjadi perjanjian krusial antara Indonesia dan Belanda, yang dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar (KMB). Ir. Djuanda, mewakili delegasi komisi ekonomi dan keuangan, turut serta dalam KMB.
Hasil dari konferensi ini termasuk pembentukan Uni Indonesia-Belanda yang dipimpin oleh ratu Belanda. Keputusan lainnya adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS), yang menyebabkan perombakan di Kabinet Hatta II.
Dalam Kabinet Hatta III, Ir. Djuanda diangkat sebagai Menteri Kemakmuran untuk ekonomi rakyat, mengakibatkan perubahan tugasnya berdasarkan prestasinya di KMB.
RIS muncul sebagai hasil kesepakatan dalam KMB, dan Ir. Djuanda mendapatkan tanggung jawab berat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Meskipun beliau tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, Ir. Djuanda, dengan gigihnya, berhasil menjalankan tugas sebagai Menteri Kemakmuran di bidang ekonomi.
Ir. Djuanda segera merespons dampak agresi militer Belanda I dan II, yang merusak infrastruktur dan menyebabkan inflasi serta defisit anggaran negara. Untuk mengatasi masalah ini, Ir. Djuanda membentuk organisasi dengan anggota para ahli ekonomi dan terlibat dalam politik ekonomi berdasarkan keputusan KMB.
Pergantian pemerintahan dari RIS ke NKRI pada 17 Agustus 1950 menyebabkan pemogokan massal oleh buruh di perusahaan asing di Indonesia. Kejadian ini menggoyahkan stabilitas ekonomi yang baru dibangun, karena kebijakan ekonomi Indonesia bergantung pada kehadiran pabrik dan perusahaan asing.
Untuk mengatasi hal ini, Ir. Djuanda meminta bantuan Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono untuk menjamin ekspor hasil perkebunan demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Selain itu, perusahaan asing yang masih beroperasi dikenakan pajak sebesar 40% dari keuntungan yang diperoleh.
Menteri Perhubungan Lagi
Ir. Djuanda, setelah berhasil mengstabilkan ekonomi Indonesia, kembali diangkat sebagai Menteri Perhubungan dan Pengakutan dalam Kabinet Natsir dan Kabinet Wilopo pada tahun 1950 dan 1953. Sebagai Menteri Perhubungan, Ir. Djuanda berupaya untuk mengembangkan transportasi udara, menghadapi kendala seperti kurangnya SDM dan fasilitas dalam sektor ini.
Untuk mengatasi hal ini, Ir. Djuanda melakukan diplomasi dengan perusahaan Belanda KLMInterinsular, berharap untuk membentuk kerja sama dan merger dalam bidang transportasi udara. Hasilnya, pada tanggal 27 Desember 1949, NV. Garuda Indonesia Airways (GIA) didirikan dengan saham 50% Pemerintah Indonesia dan 50% KLM-Interinsular, yang resmi diresmikan pada 31 Maret 1950.
Ir. Djuanda berhasil mendirikan perusahaan transportasi udara Garuda Indonesia Airways dan memusatkan perhatian pada pembenahan fasilitas pelayaran, mengingat pentingnya pelayaran sebagai moda transportasi di negara kepulauan Indonesia.
Pada masa pemerintahan RIS, perusahaan pelayaran yang dominan berasal dari Belanda, yaitu Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM). Ir. Djuanda berusaha menasionalisasikan KPM, namun usahanya terkendala oleh kurangnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan di bidang pelayaran di Indonesia.
Transportasi laut memiliki peran sentral dalam menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Mencermati hal ini, Ir. Djuanda berupaya merealisasikan pembentukan badan transportasi laut Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Badan Pengausaan Pusat Kapal-Kapal atau PAPUSKA didirikan dengan modal awal dari pemerintah yang dikelola oleh Menteri Perhubungan Ir. Djuanda.
Meskipun diberikan 8 unit kapal untuk bersaing dengan KPM, PAPUSKA tidak mampu bersaing karena keterbatasan SDM dan fasilitas, sehingga pemerintah membubarkannya dan mendirikan PT PELNI (Pelayaran Nasional Indonesia) pada tanggal 20 Juni 1952.
Dalam mewujudkan revolusi di bidang transportasi, Menteri Perhubungan Ir. Djuanda menggunakan modal hasil perdagangan karet dan peminjaman dari Eximbank, sebuah bank Amerika. Keberhasilan Ir. Djuanda dalam diplomasi perdagangan dengan negara-negara Asia dan Eropa juga membantu dalam pembiayaan dan modal awal pembangunan sektor transportasi di Indonesia.
Dewan Perancangan Negara
Kabinet Wilopo diakhiri oleh Presiden Ir. Soekarno, menandakan akhir masa jabatan Ir. Djuanda sebagai Menteri Perhubungan pada tanggal 30 Juli 1953. Walaupun tidak lagi memegang jabatan di kementerian, Ir. Djuanda tetap aktif dalam revolusi Indonesia sebagai negara merdeka, melanjutkan karirnya sebagai Direktur Dewan Perancangan Negara.
Sebagai Direktur Biro Perancangan Negara, Ir. Djuanda bertugas melaksanakan pembangunan dan pembenahan bangsa melalui proyek-proyek fasilitas untuk masyarakat, pembangunan pertanian irigasi, jalan, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya.
Ir. Djuanda memulai tugasnya dengan melakukan kunjungan ke daerah-daerah, terutama di luar pulau Jawa, untuk melakukan sosialisasi mengenai proyek pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah.
Ir. Djuanda memfokuskan program perencanaan negara pada pembenahan dan pembangunan desa. Menurutnya, pembangunan di Indonesia harus dimulai dari masyarakat desa. Dalam melaksanakan program tersebut, Ir. Djuanda mengundang ahli bidang Community Development PBB, D.K. Dey.
Prinsip Community Development yang diterapkan adalah pembangunan dari bawah untuk memberikan kemakmuran kepada masyarakat desa dengan memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh mereka.
Ir. Djuanda meyakini bahwa kekuatan pembangunan Indonesia dimulai dari pembangunan masyarakat desa, yang merupakan penopang ekonomi Indonesia dengan komoditi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat desa, seperti padi yang melimpah di daerah-daerah desa di Indonesia dan pernah menjadi komoditi ekspor, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara agraris.
Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, Ir. Djuanda dan para stafnya berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (1956-1960).
Meskipun rencana pembangunan ini masih dalam tahap kajian pemerintah dan diwarnai oleh gejolak politik di kubu pemerintahan setelah pemilu 1955, pembangunan masyarakat desa baru terealisasi dalam Undang-Undang tanggal 11 November 1958. Sasaran dan prioritas rencana tersebut kemudian diubah menjadi tahun 1957 dari yang sebelumnya direncanakan pada tahun 1956.
Kabinet Djuanda / Kabinet Karya
Kabinet Djuanda, yang menjabat selama era demokrasi liberal Indonesia, dipimpin oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja dari September 1957 hingga Juli 1959.
Sejarah mencatat bahwa kepemimpinan Djuanda adalah yang terpanjang dalam era tersebut, mencapai sekitar 14 bulan, lebih lama dibandingkan dengan masa jabatan kabinet-kabinet lainnya. Pergantian kabinet sering terjadi selama periode demokrasi liberal karena adanya persaingan antar golongan dan sistem multi partai yang menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan.
Era demokrasi liberal sendiri berlangsung singkat, mulai tahun 1950 hingga 1959, sebelum beralih ke sistem pemerintahan demokrasi terpimpin pada Juli 1959. Kabinet Djuanda dikenal sebagai kabinet zaken, diisi oleh para ahli atau kalangan non-partai.
Daniel S. Lev, dalam The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959 (2009), menyebutkan Djuanda sebagai administrator yang ideal, tidak terikat pada kepentingan partai politik mana pun. Meskipun sangat menghormati Soekarno dan kelompok militer, Djuanda tidak tunduk kepada keduanya. Keahlian diplomatiknya membantu mempertahankan dukungan parlemen selama pemerintahannya.
Program kerja Kabinet Djuanda dimulai setelah Kabinet Sastroamijoyo II. Pada masa pemerintahan ini, Djuanda dan kabinetnya menghadapi berbagai tantangan, termasuk situasi separatisme di Irian Barat dan masalah ekonomi yang parah.
Menurut Dias Anjar Malintan dalam Perkembangan Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal (2019), berikut adalah beberapa program kerja Kabinet Djuanda: membentuk dewan nasional, menormalisasi keadaan Republik Indonesia, melancarkan pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB), memperjuangkan pengembalian Irian Jaya, dan mempercepat proses pembangunan.
Salah satu prestasi terkenal Kabinet Djuanda adalah Deklarasi Djuanda, yang menegaskan kembali batas wilayah perairan Indonesia. Batas ini diubah dari peraturan kolonial Belanda yang membatasi laut teritorial Indonesia hanya 3 mil dari pulau-pulau yang menjadi bagian wilayah daratan.
Deklarasi Djuanda, yang diumumkan pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia saat itu, Djuanda Kartawidjaja, menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia, yang melibatkan laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia, merupakan satu kesatuan wilayah NKRI.
Dalam konvensi hukum laut United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS), deklarasi ini diakui sebagai negara kepulauan. Isi dari Deklarasi Juanda menyatakan:
- Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan dengan corak tersendiri.
- Sejak zaman dahulu, kepulauan nusantara ini telah menjadi satu kesatuan.
- Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi yang dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia, dari deklarasi tersebut, memiliki suatu tujuan:
- Mewujudkan wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat.
- Menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan asas negara Kepulauan.
- Mengatur lalu lintas pelayaran yang damai untuk lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.
Pernyataan yang dibacakan oleh Djuanda menjadi dasar hukum untuk penyusunan rancangan undang-undang yang digunakan untuk menggantikan Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie tahun 1939.
Kabinet Djuanda juga berhasil membentuk dewan nasional dan mengadakan musyawarah nasional untuk mengatasi pergolakan di daerah-daerah, termasuk Irian Barat. Meskipun beberapa program seperti Munas untuk mengatasi krisis dalam negeri tidak berjalan lancar.
Kejatuhan Kabinet Djuanda terjadi setelah Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, menandai awal masa demokrasi terpimpin dan akhir era demokrasi liberal.
Beberapa penyebab kejatuhan tersebut meliputi banyaknya kepentingan antar golongan dan partai politik di dalam pemerintahan, peristiwa politik yang menghambat kepentingan kelompok-kelompok, kegagalan dalam menghadapi pergolakan di daerah, dan krisis ekonomi dan keuangan yang membuat sulitnya pelaksanaan program kerja kabinet.
Wafat
Ir. H. Djuanda Kartawidjaja meninggal di Jakarta pada 7 November 1963 akibat serangan jantung dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Menurut Surat Keputusan Presiden RI No.244/1963, Ir. H. Djuanda Kartawidjaja diakui sebagai tokoh nasional dan pahlawan kemerdekaan nasional.
Djuanda diabadikan dalam nama Bandar Udara Internasional Juanda di Surabaya, Jawa Timur, sebagai penghormatan atas perannya dalam memajukan pembangunan lapangan terbang tersebut.
Selain itu, namanya juga diberikan pada Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda di Bandung, yang mencakup Museum dan Monumen Ir. H. Djuanda. Jalan di Jakarta Pusat juga dinamai Jl. Ir. Juanda, dan beberapa fasilitas seperti Stasiun Juanda dan Universitas Djuanda juga menampilkan namanya.
Pada tanggal 19 Desember 2016, sebagai bentuk penghargaan atas jasanya, Pemerintah Republik Indonesia memasukkan wajah Djuanda dalam desain pecahan uang kertas rupiah baru NKRI senilai Rp50.000.
Bio Data Djuanda Kartawidjaja
| Nama Lengkap | Ir. H. Raden Djoeanda Kartawidjaja |
| Nama Kecil | R. Djoeanda Kartawidjaja |
| Nama Lain | – |
| Tempat, Lahir | Tasikmalaya, Keresidenan Priangan, Hindia Belanda, 14 Januari 1911 |
| Tempat, Wafat | Jakarta, Indonesia, 7 November 1963 (umur 52) |
| Makam | Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta |
| Agama | Islam |
| Suku | Sunda |
| Bangsa | Indonesia |
| Pekerjaan | Politisi Teknokrat |
| Keluarga | |
| Ayah | Raden Kartawidjaja |
| Ibu | Nyi Momot |
| Isteri (Pernikahan) | Julia Virzsia |
| Anak | Poppy Djuanda Astri Djuanda Ingearti Djuanda Nurwati Djuanda Kemal budiman |
Riwayat Pendidikan Djuanda Kartawidjaja
| Pendidikan | Tempat |
|---|---|
| Hollandsch Inlansdsch School (HIS) | Hollandsch Inlansdsch School (HIS) |
| Europesche Lagere School (ELS) (1924) | Europesche Lagere School (ELS) |
| Hoogere Burgerschool (HBS) (1924-1929) | Hoogere Burgerschool (HBS) Bandung |
| Civil Ingineur (1929-1933) | Technische Hoogeschool (THS) Bandung |
Karir Djuanda Kartawidjaja
| Organisasi/Lembaga | Jabatan (Tahun) |
|---|---|
| Paguyuban Pasundan | Anggota (1934) |
| Indonesische Studenten Vereniging | Anggota |
| Muhammadiyah | Anggota |
| AMS Muhammadiyah, Jakarta | Guru (1933-1939) |
| AMS Muhammadiyah, Jakarta | Direktur (1934-1939) |
| Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat, Hindia Belanda | Pegawai ( 1939) |
| Dewan Daerah Jakarta | Anggota (28 September 1945) |
| Djawatan Kereta Api Republik Indonesia | Kepala (23 Januari 1946 – 2 Oktober 1946) |
| Menteri Perhubungan Indonesia | Menteri Muda Perhubungan Indonesia (12 Maret 1946 -2 Oktober 1946) |
| Menteri Perhubungan Indonesia | Menteri Perhubungan Indonesia (2 Oktober 1946 – 4 Agustus 1949) |
| Menteri Pekerjaan Umum Indonesia | Menteri Pekerjaan Umum Indonesia (29 Januari 1948 – 4 Agustus 1949) |
| Menteri Negara | Menteri Negara (4 Agustus 1949 – 14 Desember 1949) |
| Menteri Kemakmuran | Menteri Kemakmuran (20 Desember 1949 – 15 Agustus 1950) |
| Menteri Perhubungan Indonesia | Menteri Perhubungan Indonesia (6 September 1950 – 30 Juli 1953) |
| Dewan Perancangan Agung | Direktur (7 Januari 1952 – 6 Juni 1956) |
| Perdana Menteri Indonesia | Perdana Menteri Indonesia (9 April 1957 – 6 Juli 1959) |
| Menteri Pertahanan Indonesia | Menteri Pertahanan Indonesia (9 April 1957 – 9 Juli 1959) |
| Menteri Pertama Indonesia | Menteri Pertama Indonesia (9 Juli 1959 – 7 November 1963) |
| Menteri Keuangan Indonesia | Menteri Keuangan Indonesia (10 Juli 1959 – 6 Maret 1962) |
Penghargaan Djuanda Kartawidjaja
| Tahun | Penghargaan |
|---|---|
| 1963 | Pahlawan Kemerdekaan Nasional. |
| Bandar Udara Internasional Juanda | |
| 23 Agustus 1965 | Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda |
| Universitas Djuanda. | |
| 19 Desember 2016 | Djoeanda di pecahan uang kertas Rp50.000 |
| Stasiun Juanda | |
| Museum dan Monumen Ir. H. Djuanda |
Penghargaan Bintang Djuanda Kartawidjaja
| Penghargaan (tahun) | Gambar |
|---|---|
| Bintang Bhayangkara Utama | |
| Yugoslav Star with Sash (Order of the Yugoslav Star, I Class) | |
| Seri Maharaja Mangku Negara (S.M.N.) – Malaysia |