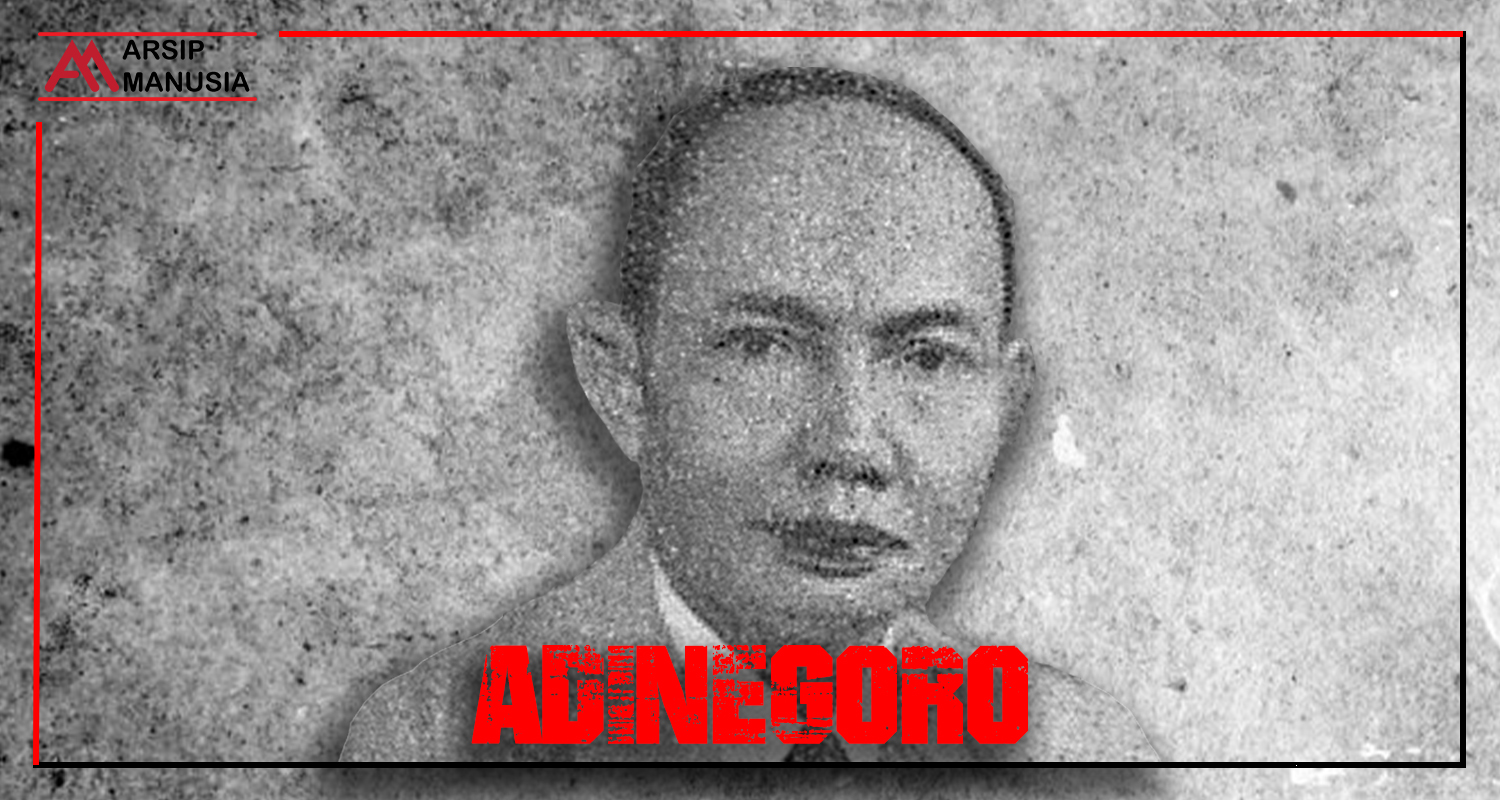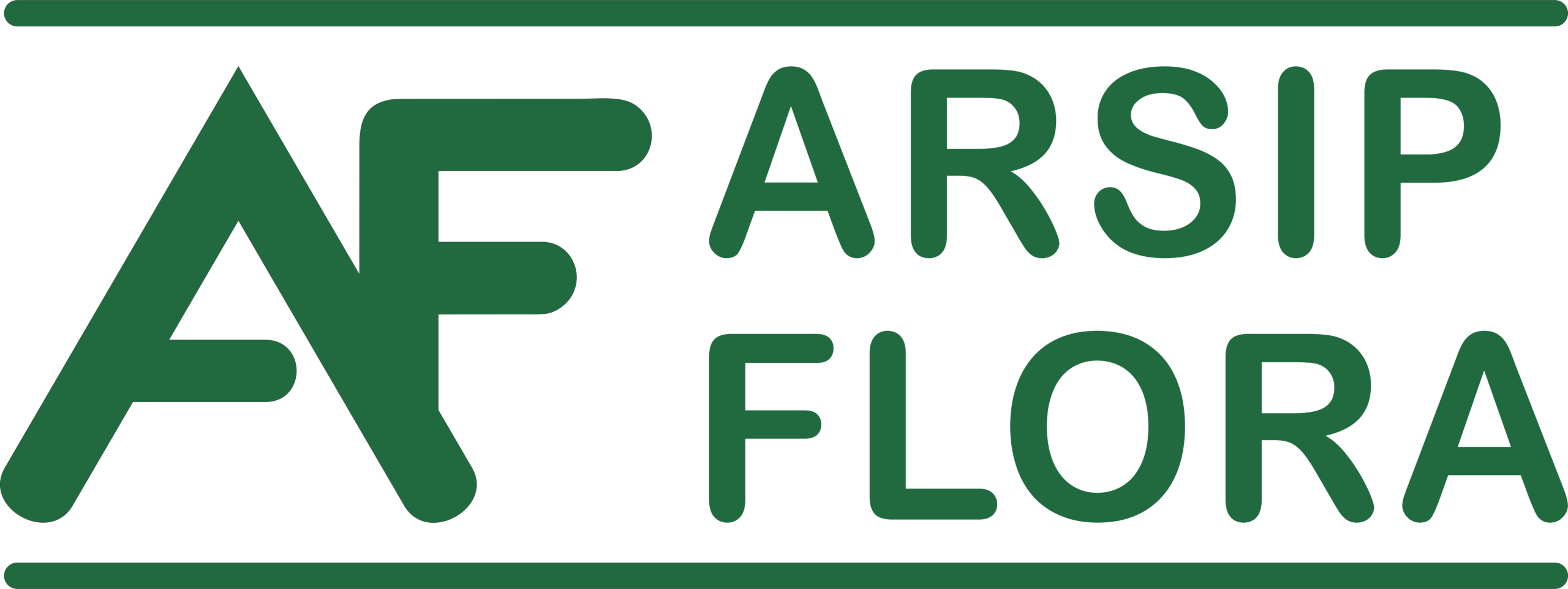Buya Hamka, seorang tokoh ulama dan sastrawan Indonesia, lahir pada 17 Februari 1908 di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat. Nama aslinya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, tetapi ia lebih dikenal dengan nama pena Buya Hamka.
“Buya” adalah panggilan hormat dalam bahasa Minangkabau yang berarti “ayah” atau “guru,” sementara “Hamka” merupakan akronim dari namanya sendiri. Buya Hamka dikenal luas sebagai seorang intelektual yang memiliki pengaruh besar dalam bidang agama, sastra, dan sosial politik di Indonesia.
Buya Hamka adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Indonesia, terutama dalam konteks perkembangan Islam dan sastra Indonesia. karya-karyanya dalam bidang sastra, seperti novel “Di Bawah Lindungan Ka’bah” dan “Tenggelamnya Kapal Van der Wijck,” masih menjadi bacaan klasik hingga saat ini.
Dalam bidang politik, Buya Hamka juga aktif sebagai anggota Konstituante dan pernah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karya-karyanya mencerminkan pemikiran progresif dan kritis terhadap berbagai masalah sosial, politik, serta keagamaan.
Buya Hamka adalah teladan nyata bagaimana seseorang dapat menggabungkan ilmu pengetahuan dengan iman, dan bagaimana komitmen terhadap pendidikan serta pengabdian kepada masyarakat dapat membawa perubahan besar.
Table of Contents
ToggleKehidupan Awal dan Pendidikan
Buya Hamka lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat. Ia lahir di keluarga yang memiliki latar keagamaan yang kuat. Ayahnya, Haji Abdul Karim Amrullah, adalah seorang ulama terkenal yang memiliki pengaruh besar di Sumatera Barat dan merupakan salah satu pendiri organisasi Muhammadiyah di Sumatera Barat.
Ibunya, Sitti Shafiyah, adalah seorang wanita yang taat beragama dan sangat mendukung pendidikan anak-anaknya. Buya Hamka adalah keturunan Minangkabau yang dikenal dengan tradisi keislamannya yang kental dan semangatnya dalam menuntut ilmu.
Sejak kecil, Buya Hamka sudah mendapatkan pendidikan agama yang ketat dari ayahnya. Haji Abdul Karim Amrullah sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya, terutama dalam hal agama. Buya Hamka belajar membaca Al-Quran dan memahami dasar-dasar agama Islam langsung dari ayahnya. Pendidikan agama ini menjadi fondasi yang kuat bagi Buya Hamka dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang ulama.
Pendidikan formal Buya Hamka tidak berjalan mulus. Ia sempat bersekolah di sekolah desa, tetapi kemudian keluar karena merasa tidak cocok dengan metode pengajaran di sekolah tersebut. Buya Hamka merasa bahwa pendidikan formal di sekolah itu tidak memberikan kebebasan berpikir yang ia butuhkan.
Keputusan ini menunjukkan awal dari sifat mandirinya yang kuat dan keinginan untuk mencari pengetahuan dengan cara yang berbeda. Ia kemudian memilih untuk belajar secara otodidak, memanfaatkan perpustakaan ayahnya dan membaca berbagai buku yang tersedia.
Meskipun tidak menempuh jalur pendidikan formal yang konvensional, Buya Hamka berhasil mengembangkan pengetahuannya dan menjadi seorang intelektual yang dihormati. Pendidikan agama dari ayahnya dan semangat belajar mandirinya menjadi kombinasi yang membentuk karakter dan pemikirannya yang kritis dan progresif.
Pendidikan dan Karir Akademik
Buya Hamka memulai pendidikan formalnya di Sumatera Thawalib, sebuah sekolah Islam terkemuka di Padang Panjang. Sumatera Thawalib dikenal dengan kurikulum yang menggabungkan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan umum.
Di sini, Buya Hamka belajar di bawah bimbingan ulama-ulama terkemuka seperti Syeikh Ibrahim Musa dan Syeikh Muhammad Jamil Jambek. Pendidikan di Sumatera Thawalib memberikan dasar yang kuat dalam ilmu agama serta memperkenalkan Buya Hamka pada pemikiran-pemikiran modern dan metodologi kritis.
Selain pendidikan formal, Buya Hamka juga belajar secara otodidak dalam berbagai bidang. Ia adalah seorang pembaca yang rakus, yang sering menghabiskan waktu berjam-jam membaca buku-buku yang tersedia di perpustakaan ayahnya. Bidang-bidang yang dipelajarinya meliputi sastra, filsafat, sejarah, dan ilmu sosial. Kebiasaannya belajar secara otodidak membantunya mengembangkan pengetahuan nya.
Di Padang Panjang, Buya Hamka terpapar pada pendidikan tradisional Islam melalui Sumatera Thawalib, tetapi ia juga terbuka terhadap pemikiran modern yang berkembang saat itu. Pengaruh pendidikan tradisional dan modern ini membentuk pandangannya yang inklusif dan progresif terhadap berbagai masalah sosial dan keagamaan.
Pada usia 16 tahun, Buya Hamka memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Di sana, ia bertemu dengan tokoh-tokoh intelektual dan nasionalis yang berpengaruh, seperti Haji Agus Salim dan HOS Tjokroaminoto. Pertemuan dengan para intelektual ini memperkaya wawasan dan pemikirannya, serta memperluas jaringan sosialnya.
Buya Hamka sering terlibat dalam diskusi dan debat yang membahas berbagai isu sosial, politik, dan agama. Pengalaman ini semakin mematangkan pemikirannya dan memperkuat komitmennya terhadap perjuangan kemerdekaan dan kemajuan bangsa.
Muhammadiyah
Dalam Muhammadiyah, Buya Hamka berperan sebagai pendidik dan pemimpin yang visioner. Ia aktif dalam berbagai program dakwah dan pendidikan, serta berkontribusi dalam penyusunan kurikulum pendidikan Muhammadiyah yang progresif. Selain itu, Buya Hamka terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan politik, memperjuangkan hak-hak umat Islam dan berpartisipasi dalam proses kemerdekaan Indonesia.
Kegiatan di Masa Jepang dan Pasca Kemerdekaan
Selama pendudukan Jepang, Buya Hamka terlibat dalam Syu Sangi Kai, sebuah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk menggalang dukungan dari tokoh-tokoh lokal. Meskipun terlibat dalam organisasi ini, Buya Hamka tetap memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia.
Setelah kemerdekaan, Buya Hamka terus aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Ia terlibat dalam Konstituante dan menjadi salah satu tokoh yang memperjuangkan penerapan nilai-nilai Islam dalam konstitusi Indonesia. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Buya Hamka tetap vokal dalam menyuarakan keadilan dan kebenaran, meskipun harus menghadapi berbagai tekanan politik.
Kontribusi Buya Hamka setelah kemerdekaan mencakup berbagai bidang, dari pendidikan, dakwah, hingga politik. Ia mendirikan dan memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI), berperan dalam pembentukan kebijakan-kebijakan keagamaan, serta terus menulis dan menyebarkan pemikiran-pemikirannya melalui berbagai media. Dedikasi dan komitmen Buya Hamka dalam memperjuangkan kemajuan bangsa dan agama menjadikannya salah satu tokoh yang paling dihormati dan dikenang dalam sejarah Indonesia.
Karya-Karya Buya Hamka
Buya Hamka adalah seorang penulis produktif yang menghasilkan banyak karya tulis berpengaruh dalam berbagai bidang, termasuk agama, sastra, dan filsafat. Beberapa karya utamanya yang terkenal antara lain “Tasawuf Modern,” “Tenggelamnya Kapal Van der Wijck,” dan “Tafsir Al-Azhar.”
- Tasawuf Modern: Buku ini adalah salah satu karya Buya Hamka yang paling terkenal dan banyak dibaca. “Tasawuf Modern” menguraikan konsep-konsep tasawuf atau sufisme dengan cara yang relevan untuk masyarakat modern, menjembatani antara nilai-nilai spiritual tradisional dan tantangan kehidupan kontemporer. Buku ini menekankan pentingnya kebersihan hati, introspeksi, dan hubungan pribadi dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.
- Tenggelamnya Kapal Van der Wijck: Novel ini adalah salah satu karya sastra Buya Hamka yang paling populer. Novel ini menceritakan kisah cinta tragis antara Zainuddin dan Hayati, dengan latar belakang budaya Minangkabau dan pengaruh kolonialisme Belanda. Melalui cerita ini, Buya Hamka mengeksplorasi tema-tema seperti perbedaan kelas, adat, dan modernisasi.
- Tafsir Al-Azhar: Ini adalah salah satu karya monumental Buya Hamka dalam bidang tafsir Al-Quran. “Tafsir Al-Azhar” adalah interpretasi Al-Quran yang ditulis dalam bahasa Indonesia, memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Karya ini menjadi referensi penting bagi umat Islam di Indonesia dalam memahami ajaran-ajaran Al-Quran secara kontekstual dan aplikatif.
- Artikel dan Ceramah: Selain menulis buku, Buya Hamka juga aktif menulis artikel dan memberikan ceramah di berbagai majalah dan forum. Artikel-artikelnya sering kali membahas isu-isu sosial, politik, dan agama, serta menawarkan perspektif Islam yang moderat dan inklusif. Ceramah-ceramahnya, yang sering disiarkan melalui radio dan televisi, menjangkau audiens yang luas dan berperan penting dalam menyebarkan pemikiran-pemikirannya.
Penghargaan dari Dalam dan Luar Negeri
Buya Hamka menerima berbagai penghargaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas kontribusinya yang luar biasa dalam bidang agama, sastra, dan sosial. Beberapa penghargaan tersebut termasuk gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar, Kairo, yang diberikan atas kontribusinya dalam menyebarkan ilmu pengetahuan Islam. Di dalam negeri, ia menerima penghargaan dari pemerintah Indonesia dan berbagai lembaga pendidikan serta sosial atas dedikasinya dalam memajukan pendidikan dan dakwah Islam.
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Buya Hamka juga diakui sebagai salah satu pendiri dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai Ketua MUI, ia memainkan peran penting dalam mengembangkan panduan dan kebijakan keagamaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam serta kebutuhan masyarakat Indonesia.
Kepemimpinannya di MUI ditandai dengan upaya untuk menjaga keutuhan umat Islam di Indonesia dan memperkuat posisi Islam dalam kehidupan sosial dan politik. Namun, pada tahun 1981, Buya Hamka memutuskan untuk mengundurkan diri dari MUI sebagai bentuk protes terhadap campur tangan pemerintah dalam urusan internal MUI.
Akhir Hayat
Buya Hamka meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta, Indonesia. Kabar wafatnya menyebar cepat dan menimbulkan duka yang mendalam di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan umat Islam dan komunitas intelektual.
Pemakaman Buya Hamka dihadiri oleh ribuan pelayat dari berbagai latar belakang, yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada seorang tokoh besar yang telah memberikan banyak kontribusi bagi bangsa dan agama. Buya Hamka dimakamkan dengan penuh kehormatan, dan suasana haru serta penghormatan mendalam mengiringi prosesi pemakamannya.
Bio Data Buya Hamka
| Nama Lengkap | Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah Datuk Indomo |
| Nama Kecil | Abdul Malik |
| Nama Lain | Buya Hamka |
| Lahir | Sungai Batang, 17 Februari 1908 |
| Wafat | Jakarta, 24 Juli 1981 |
| Makam | TPU Tanah Kusir, Jakarta |
| Agama | Islam |
| Suku | Minang |
| Bangsa | Indonesia |
| Pekerjaan | Ulama Filsuf Sastrawan Wartawan Penulis Pengajar |
| Keluarga | |
| Ayah | Abdul Karim Amrullah |
| Ibu | Sitti Shafiah |
| Istri (Awal nika – akhir) | Sitti Raham (1929 – 1972) Sitti Khadijah (1973 – 1981) |
| Anak dari Sitti Raham | Rusydi Hamka Irfan Hamka Aliyah Hamka Fathiyah Hamka Amir Syakib Hisyam Hamka Afif Hamka Zaky Hamka Hilmi Hamka Fachri Hamka Husna Hamka Sitti Khadijah |
| Cucu dari Azizah Hamka | Siti Mursidah |
| Saudara (Kandung) | Abdul Kuddus Asma Abdul Mu’thi |
| Saudara (Tiri) | Fatimah |
Riwayat Pendidikan Buya Hamka
| Tahun | Pendidikan |
|---|---|
| 1915 – 1918 | Sekolah Desa |
| 1916 – 1922 | Diniyyah School |
| 1918 – 1922 | Thawalib |
Karir Buya Hamka
| Organisasi/Lembaga | Jabatan |
|---|---|
| Muhammadiyah Padang Panjang | Ketua Cabang (1928) |
| Kulyatul Muballighin Muhammadiyah | Pendiri (1933) |
| Pedoman Masjarakat | Ketua (1935 – 1946) |
| Muhammadiyah Sumatera Timur | Konsul (1939) |
| Tyuo Sangi-in | Anggota (1944) |
| Muhammadiyah Sumatera Barat | Ketua Majelis Pimpinan (1946 – 1949) |
| Badan pengawal Nagari dan Kota | Ketua (1947) |
| Front Pertahanan Nasional | Ketua (1947) |
| Muhammadiyah | Pimpinan Pusat (1953 – 1971) |
| Majelis Ulama Indonesia | Ketua (1975 – 1981) |
Karya Buya Hamka
| Tahun | Judul |
|---|---|
| – | Khatibul Ummah, Jilid 1-3 |
| 1928 | Si Sabariah |
| 1929 | Pembela Islam (Tarikh Saidina Abu Bakar Ash Shiddiq) |
| 1929 | Adat Minang Kabau dan Agama Islam |
| 1929 | Ringkasan Tarikh Ummat Islam |
| 1929 | Kepentingan Melakukan Tabligh |
| – | Hikmat Isra’ dan Mikraj |
| 1932 | Arkanul Islam |
| 1932 | Laila Majnun |
| 1934 | Mati Mengandung Malu (Salinan Al-Manfaluthi) |
| 1936 | Di Bawah Lindungan Ka’bah |
| 1937 | Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck |
| 1939 | Di Dalam Lembah Kehidupan |
| 1940 | Merantau Ke Deli |
| 1940 | Margaretta Gauthier (terjemahan) |
| 1939 | Tuan Direktur |
| 1939 | Dijemput Mamaknya |
| 1939 | Keadilan Illahy |
| 1939 | Tasawuf Modern |
| 1939 | Falsafah Hidup |
| 1940 | Lembaga Hidup |
| 1940 | Lembaga Budi |
| 1946 | Negara islam |
| 1946 | Islam dan Demokrasi |
| 1946 | Revolusi Fikiran |
| 1946 | Islam Agama |
| 1946 | Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi |
| 1946 | Dibantingkan Ombak Masyarakat |
| 1946 | Didalam Lembah Cita-Cita |
| 1947 | Sesudah Naskah Renville |
| 1950 | Ayahku |
| 1950 | Mandi Cahaya di Tanah Suci |
| 1950 | Mengembara di Lembah Nyl |
| 1950 | Ditepi Sungan Dajlah |
| – | Kenang Kenangan Hidup, jilid 1-4 |
| 1938 – 1950 | Sejarah Ummat Islam, Jilid 1-4 |
| 1937 | Pedoman Mubaligh Islam |
| 1950 | Pribadi |
| 1939 | Agama dan Perempuan |
| 1946 | Muhammadiyah Melalui 3 Zaman |
| 1950 | 1001 Soal Hidup |
| 1956 | Pelajaran Agama Islam |
| 1952 | Perkembangan Tasawuf Dari Abad ke Abad |
| 1953 | Empat Bulan di Amerika, Jilid 1-2 |
| 1960 | Soal Jawab 1960 |
| 1963 | Dari Pembendaharaan Lama |
| 1953 | Lembaga Hikmat |
| 1972 | Islam dan Kebatinan |
| 1970 | Fakta dan Khayal Tuanku Rao |
| 1965 | Sayyid Jamaluddin Al-Afhany |
| 1963 | Ekspansi Ideologi |
| 1968 | Hak Asasi Manusia Dipandang dari Segi Islam |
| 1950 | Falsafah Ideologi Islam |
| 1950 | keadilan Sosial Dalam Islam |
| 1973 | Studi Islam |
| – | Himpunan Khutbah-Khutbah |
| – | Urat Tanggang Pancasila |
| 1974 | Doa-Doa Rasulullah S.A.W. |
| – | Sejarah Islam Di Sumatera |
| – | Bohong Di Dunia |
| 1975 | Muhammadiyah Di Minangkabau |
| – | Pandangan Hidup Muslim |
| 1973 | Kedudukan Perempuan dalam Islam |
| 1971 | Tafsir Al-Azhar |
Penghargaan Bintang Buya Hamka
| Penghargaan | Gambar |
|---|---|
| Bintang Mahapuera Utama (1993) |