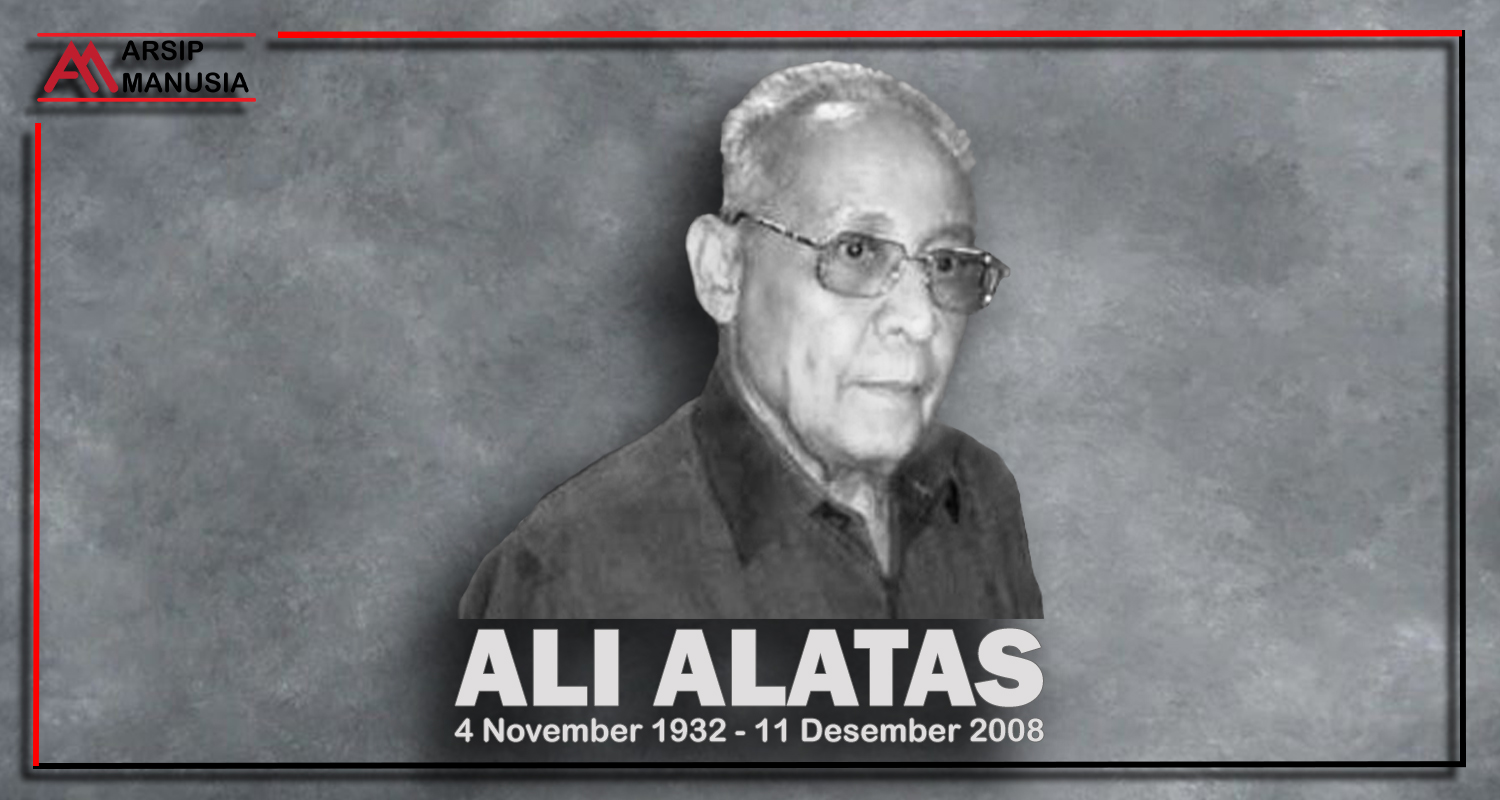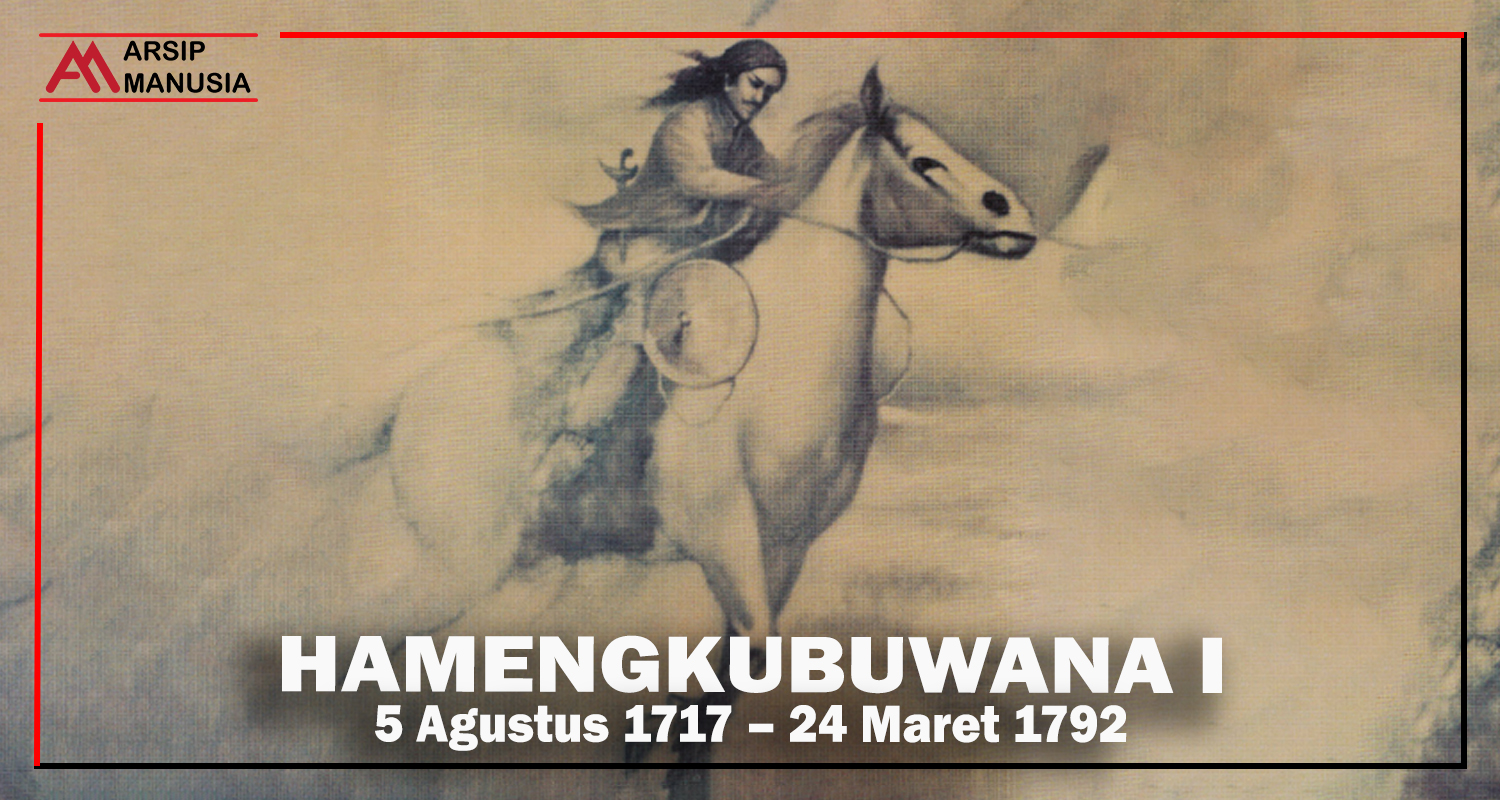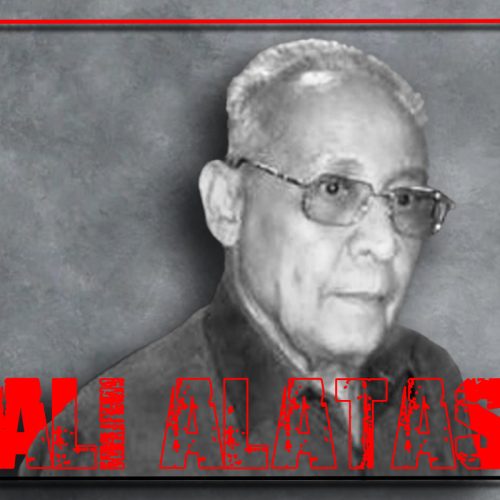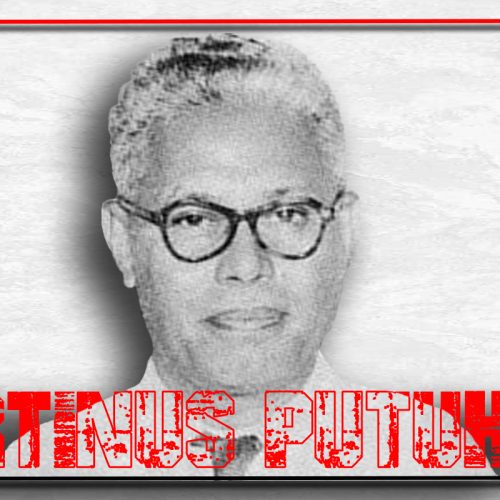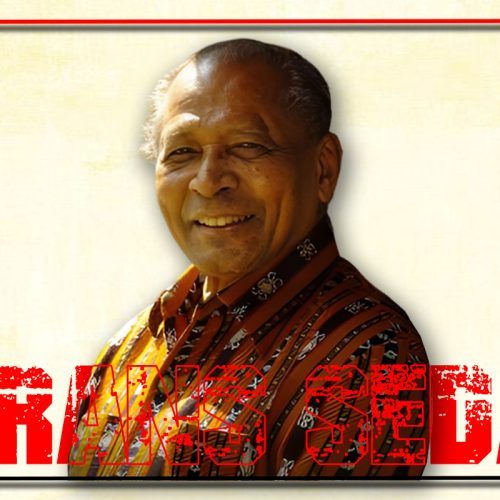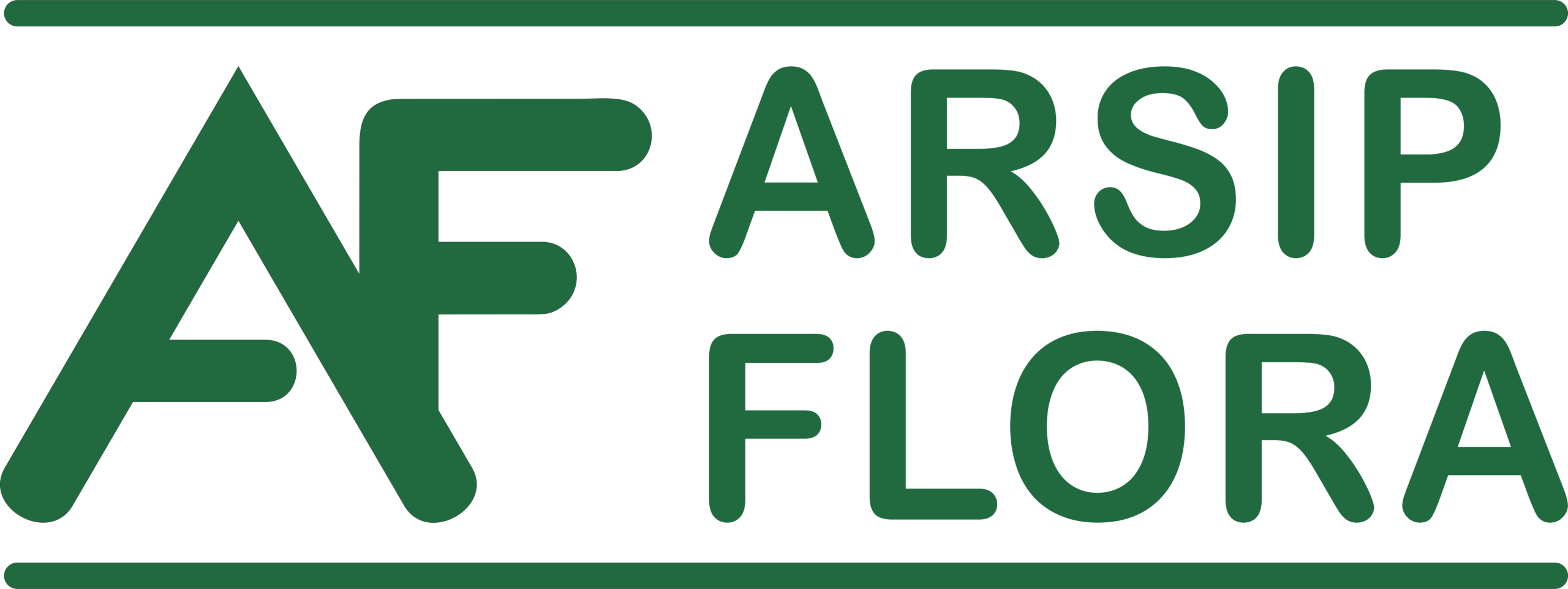Hamengkubuwana I, lahir dengan nama Raden Mas Sujana, adalah tokoh penting dalam sejarah Jawa pada abad ke-18 yang dikenal sebagai pendiri Kesultanan Yogyakarta. Ia berperan besar dalam Perang Takhta Jawa III, perundingan Perjanjian Giyanti, serta penataan politik dan budaya Jawa pasca-keruntuhan Mataram Islam.
Sebagai putra dari Amangkurat IV, ia tidak hanya tampil sebagai pemimpin militer, tetapi juga diplomat tangguh yang mampu melawan dominasi VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) di tanah Jawa. Artikel ini membahas perjalanan hidup, perjuangan Hamengkubuwana I bagi bangsa Indonesia.
Table of Contents
ToggleAwal Kehidupan
Raden Mas Sujana lahir pada tanggal 5 Agustus 1717 sebagai putra dari Amangkurat IV, Susuhunan Mataram yang kedelapan, dan selirnya bernama Mas Ayu Tejawati. Setelah dewasa, ia memperoleh gelar Pangeran Mangkubumi, gelar bangsawan yang kelak akan menjadi identitas penting dalam sejarah perpecahan Mataram.
Pada masa mudanya, Pangeran Mangkubumi tumbuh di tengah lingkungan keraton yang dipenuhi dinamika politik internal dan tekanan eksternal dari pihak asing, khususnya Belanda. Sejak dini, ia menyaksikan bagaimana konflik perebutan kekuasaan di lingkungan istana Mataram dan meningkatnya intervensi VOC dalam urusan pemerintahan kerajaan Jawa. Lingkungan ini secara perlahan membentuk karakter politik Mangkubumi yang tegas, penuh perhitungan, serta berpandangan jauh ke depan.
Situasi Politik Jawa dan Awal Perpecahan Mataram
Awal gejolak besar terjadi pada tahun 1740, saat terjadi pemberontakan besar orang-orang Tionghoa di Batavia yang menyebar ke berbagai daerah di Jawa. Pakubuwana II, kakak kandung Pangeran Mangkubumi yang saat itu menjabat sebagai Susuhunan Mataram, sempat menunjukkan simpati terhadap pemberontakan tersebut. Namun, ketika melihat VOC berhasil memukul balik pemberontak, ia segera mengubah sikap dan berbalik mendukung Belanda.
Dampak dari pergolakan ini sangat besar. Pada 1742, pasukan pemberontak berhasil menyerbu Keraton Kartasura, memaksa Pakubuwana II mengungsi dan membangun istana baru di Surakarta. Pemberontakan akhirnya bisa diredam berkat bantuan VOC dan Cakraningrat IV dari Madura, tetapi luka politik dan kepercayaan di lingkungan kerajaan semakin dalam.
Sementara itu, sisa-sisa pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Pangeran Sambernyawa (nama lain dari Raden Mas Said, keponakan Mangkubumi) berhasil menguasai wilayah Sukawati. Pakubuwana II mengumumkan sayembara bagi siapa saja yang mampu merebut kembali wilayah tersebut, dengan imbalan tanah seluas 3.000 cacah.
Mangkubumi menerima tantangan tersebut dan berhasil merebut kembali Sukawati pada tahun 1746. Namun, alih-alih mendapatkan penghargaan, ia justru dihalang-halangi oleh Patih Pringgalaya, yang diduga kuat menghasut Pakubuwana II untuk membatalkan janji sayembara. Situasi ini memperuncing ketegangan antara Mangkubumi dan elit istana yang pro-VOC.
Konflik dengan VOC dan Mangkubumi Memilih Memberontak
Ketegangan semakin memburuk saat Baron van Imhoff, Gubernur Jenderal VOC, datang ke Surakarta dan mendesak Pakubuwana II untuk menyewakan wilayah pesisir kepada Belanda guna melunasi utang keraton sebesar 20.000 real. Mangkubumi menentang keras keputusan tersebut karena menganggapnya sebagai bentuk penjualan tanah air kepada asing. Pertengkaran pun pecah, dan Van Imhoff secara terbuka menghina Mangkubumi di depan umum—sebuah tindakan yang sangat mencoreng harga diri seorang bangsawan Jawa.
Merasa dikhianati dan terhina, Mangkubumi akhirnya meninggalkan Surakarta pada Mei 1746, dan bergabung dengan Mas Said untuk mengangkat senjata melawan VOC dan Pakubuwana II. Demi memperkuat aliansi mereka, Mangkubumi menikahkan putrinya, Rara Inten (Gusti Ratu Bendoro), dengan Mas Said. Dari sinilah dimulai rangkaian panjang peperangan yang dikenal sebagai Perang Takhta Jawa III, sebuah konflik besar yang mempertemukan berbagai kekuatan di tanah Jawa.
Perang Takhta Jawa III dan Perebutan Legitimasi Mataram
Bersatunya Mangkubumi dan Mas Said menandai awal konflik bersenjata yang serius melawan pemerintahan Surakarta dan kekuasaan VOC. Sejarawan kemudian menyebut konflik ini sebagai Perang Takhta Jawa III, salah satu perang paling berdarah dan rumit dalam sejarah kerajaan Jawa. Pada tahun 1747, kekuatan pasukan Mangkubumi diperkirakan mencapai 13.000 prajurit, angka yang cukup besar untuk menandingi pengaruh VOC di wilayah pedalaman Jawa.
Mangkubumi membuktikan dirinya sebagai pemimpin militer ulung. Beberapa pertempuran penting berhasil ia menangkan, seperti di Demak dan Grobogan. Sementara itu, posisi Pakubuwana II mulai melemah, baik secara politik maupun fisik. Pada 11 Desember 1749, menjelang akhir hayatnya, ia secara mengejutkan menyerahkan kedaulatan Mataram kepada VOC untuk melindungi keluarganya. Tindakan ini memicu krisis legitimasi kekuasaan.
Merespons situasi tersebut, pada 12 Desember 1749, Mangkubumi mengangkat dirinya sebagai Susuhunan dan mengambil gelar Pakubuwana III, meskipun dirinya bukan pewaris langsung dari Pakubuwana II. Sementara itu, VOC menetapkan Raden Mas Suryadi, putra kandung Pakubuwana II, sebagai Pakubuwana III versi Surakarta pada 15 Desember 1749.
Akibatnya, dalam waktu bersamaan terdapat dua raja bergelar Pakubuwana III: satu di Surakarta yang didukung VOC, dan satu lagi di basis pertahanan Mangkubumi yang dikenal sebagai Susuhunan Kabanaran, karena bermarkas di desa Banaran (daerah Sragen saat ini).
Pertempuran dan Perundingan: Jalan Menuju Giyanti
Konflik bersenjata terus berlanjut. Pada tahun 1751, terjadi pertempuran besar di tepi Sungai Bogowonto, di mana pasukan Mangkubumi berhasil menghancurkan tentara VOC yang dipimpin oleh Kapten de Clerck (yang dikenal orang Jawa sebagai Kapten Klerek).
Namun, seiring waktu, perbedaan pandangan mulai muncul antara Mangkubumi dan Mas Said. Ketegangan memuncak pada tahun 1752, disebabkan oleh ketidaksepakatan tentang siapa yang berhak memegang kekuasaan tunggal atas Mataram. Masing-masing merasa paling berhak atas warisan kerajaan yang terpecah.
VOC, yang sudah lelah menghadapi konflik berkepanjangan dan pengeluaran militer yang membengkak, akhirnya membuka pintu diplomasi dengan Mangkubumi. Pada tahun 1754, perwakilan VOC, Nicolaas Hartingh—gubernur pantai utara Jawa—mengajukan tawaran damai. Syaikh Ibrahim sebagai seorang perantara berkebangsaan Turki yang menjembatani kedua pihak.
Setelah serangkaian perundingan intensif, Mangkubumi dan VOC mencapai kesepakatan politik dan wilayah. Mangkubumi bersedia mengakui keberadaan VOC dan Surakarta, asalkan ia mendapatkan setengah wilayah Mataram. Sebagai bagian dari kompromi, Mangkubumi juga merelakan wilayah pesisir disewakan kepada VOC dengan pembagian hasil 20.000 real: separuh untuk dirinya dan separuh untuk Surakarta.
Perjanjian Giyanti dan Lahirnya Kesultanan Yogyakarta
Akhir dari konflik panjang ini ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Perjanjian ini menjadi tonggak sejarah penting karena secara resmi mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwana I, dan membagi Kerajaan Mataram menjadi dua kekuasaan:
- Surakarta di bawah pemerintahan Pakubuwana III
- Yogyakarta sebagai kerajaan baru di bawah Hamengkubuwana I
Dengan demikian, Perjanjian Giyanti tidak hanya mengakhiri perang saudara, tetapi juga menjadi awal berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Selain itu, perjanjian ini juga menciptakan aliansi baru antara Mangkubumi, Pakubuwana III, dan VOC untuk menghadapi sisa-sisa kekuatan Pangeran Sambernyawa yang masih menolak tunduk.
Pendirian Yogyakarta dan Kota Baru di Tengah Hutan
Setelah dinobatkan sebagai sultan, Hamengkubuwana I masih menghadapi tantangan lain: ia belum memiliki keraton dan ibu kota pemerintahan. Untuk itu, ia mengajukan uang persekot dari hasil sewa wilayah pantai kepada VOC guna membangun keraton. Namun, permintaannya tidak langsung dipenuhi.
Tak mau menunggu, pada April 1755, Hamengkubuwana I memutuskan membuka Hutan Pabringan sebagai lokasi ibu kota baru. Kawasan tersebut sebelumnya pernah menjadi pesanggrahan bernama Ayogya, dan di sinilah kemudian dibangun Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
Pada 7 Oktober 1756, Hamengkubuwana I resmi pindah dari desa Banaran ke Yogyakarta, dan sejak saat itu, kota ini berkembang menjadi pusat budaya, kekuasaan, dan identitas baru di Jawa. Dalam waktu singkat, Yogyakarta berhasil menunjukkan keunggulan—baik secara militer, politik, maupun kebudayaan—bahkan mengungguli Surakarta.
Ketegangan Politik Pasca-Giyanti dan Ancaman Perang Baru
Meskipun Perjanjian Giyanti berhasil menghentikan konflik terbuka, situasi politik di Jawa tetap labil. Ambisi untuk menyatukan kembali Mataram masih menjadi impian tersembunyi para penguasa, termasuk Hamengkubuwana I dan para penerusnya.
Pada tahun 1788, Pakubuwana IV naik takhta di Surakarta. Ia dikenal sebagai raja yang lebih cakap dan ambisius dibandingkan ayahnya. Seperti halnya Hamengkubuwana I, Pakubuwana IV juga ingin mengembalikan keutuhan Mataram. Dalam langkah politiknya, ia mengangkat saudaranya sendiri dengan gelar Pangeran Mangkubumi—gelar yang sebelumnya melekat kuat pada tokoh pendiri Yogyakarta.
Langkah itu tidak hanya dianggap sebagai bentuk provokasi, tetapi juga menciptakan ketegangan baru dengan pihak Yogyakarta. Pakubuwana IV juga menolak mengakui hak waris putra mahkota Yogyakarta, yang menurut tradisi seharusnya otomatis menjadi pengganti Sultan.
VOC pun mulai merasa khawatir. Mereka menyadari bahwa jika konflik terbuka kembali pecah, keuangan dan stabilitas wilayah jajahan akan terguncang. Terlebih lagi, di lingkungan Pakubuwana IV mulai muncul penasihat-penasihat spiritual beraliran keagamaan kuat, yang dianggap potensial memicu pemberontakan berbasis agama dan moral.
Aliansi Sementara: Mencegah Perang Besar
Kekhawatiran akan terjadinya konflik skala besar mendorong terbentuknya aliansi yang tak terduga. Pada tahun 1790, Hamengkubuwana I dan Mangkunegara I—dua tokoh yang pernah berada di medan perang melawan VOC—kembali bersatu, kali ini bersekutu dengan Belanda untuk menghadapi ancaman dari Surakarta.
Pasukan gabungan ini mengepung Surakarta dan mendesak Pakubuwana IV agar membubarkan penasihat spiritualnya yang dianggap radikal. Tekanan dari tiga pihak membuat Pakubuwana IV akhirnya menyerah. Ia menyetujui pembubaran golongan spiritual tersebut sebagai kompromi politik, demi menghindari konflik besar yang dapat mengguncang tatanan politik Jawa.
Meskipun aliansi ini bersifat pragmatis dan sementara, ia menunjukkan bahwa Hamengkubuwana I mampu beradaptasi secara politik. Ia menempatkan stabilitas dan kelangsungan Kesultanan Yogyakarta di atas segala bentuk konfrontasi langsung.
Akhir Hayat Sang Sultan
Selama masa pemerintahannya, Hamengkubuwana I tetap menyimpan harapan untuk menyatukan kembali Mataram. Salah satu upaya diplomatik yang ia tempuh adalah dengan mengusulkan pernikahan antara putranya dan putri Pakubuwana III. Tujuannya jelas: membangun kembali ikatan darah dan simbol politik antara dua kerajaan. Sayangnya, gagasan ini ditolak dan tidak pernah terlaksana.
Sementara itu, generasi penerus mulai mengambil peran. Pakubuwana IV, sebagai pewaris tahta Surakarta, tampil sebagai tokoh yang akan melanjutkan ketegangan politik antara dua kerajaan. Harapan untuk menyatukan Mataram pun semakin meredup.
Pada 24 Maret 1792, Hamengkubuwana I wafat. Ia meninggalkan warisan politik dan budaya yang sangat besar bagi Yogyakarta. Takhta Kesultanan kemudian dilanjutkan oleh putranya, yang bergelar Hamengkubuwana II.
Warisan Sejarah Hamengkubuwana I
Hamengkubuwana I tidak hanya dikenal sebagai pemimpin tangguh yang membentuk Kesultanan Yogyakarta, tetapi juga sebagai figur visioner dan pemikir strategis. Ia mampu mengubah konflik menjadi kesempatan, dan membangun kekuatan politik baru dari reruntuhan Mataram.
Salah satu peninggalan paling monumental dari pemerintahannya adalah Taman Sari Yogyakarta, kompleks istana air yang dirancang oleh seorang arsitek Portugis yang dikenal dengan nama Demang Tegis. Karya ini bukan hanya simbol keindahan arsitektur, tetapi juga representasi dari cita rasa seni dan budaya yang berkembang pesat di Yogyakarta.
Meskipun akhir hidupnya ditandai dengan perdamaian formal bersama VOC, rasa benci terhadap dominasi asing tidak pernah benar-benar padam dalam dirinya. Ia bahkan pernah mencoba menghalangi Belanda membangun benteng di wilayah Yogyakarta dan terus berusaha membatasi campur tangan VOC dalam urusan internal kerajaannya.
Tak mengherankan jika pihak Belanda sendiri mengakui bahwa perlawanan Pangeran Mangkubumi adalah salah satu perang tersulit yang pernah mereka hadapi di tanah Jawa, bahkan dalam periode panjang kekuasaan mereka sejak 1619 hingga 1799.
Semangat perlawanan terhadap kolonialisme ini kemudian diwariskan kepada putranya, Hamengkubuwana II, dan menjadi bagian dari identitas ideologis Kesultanan Yogyakarta hingga masa kemerdekaan.
Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Hamengkubuwana I pada tanggal 10 November 2006, hanya beberapa bulan setelah gempa bumi melanda wilayah Yogyakarta.
Sumber:
- “Sri Sultan Hamengku Buwono I” kratonjogja.id (diakses pada 1 Agustus 2025)
- “Sri Sultan Hamengku Buwono I” pangerandiponegoro.com (diakses pada 1 Agustus 2025)