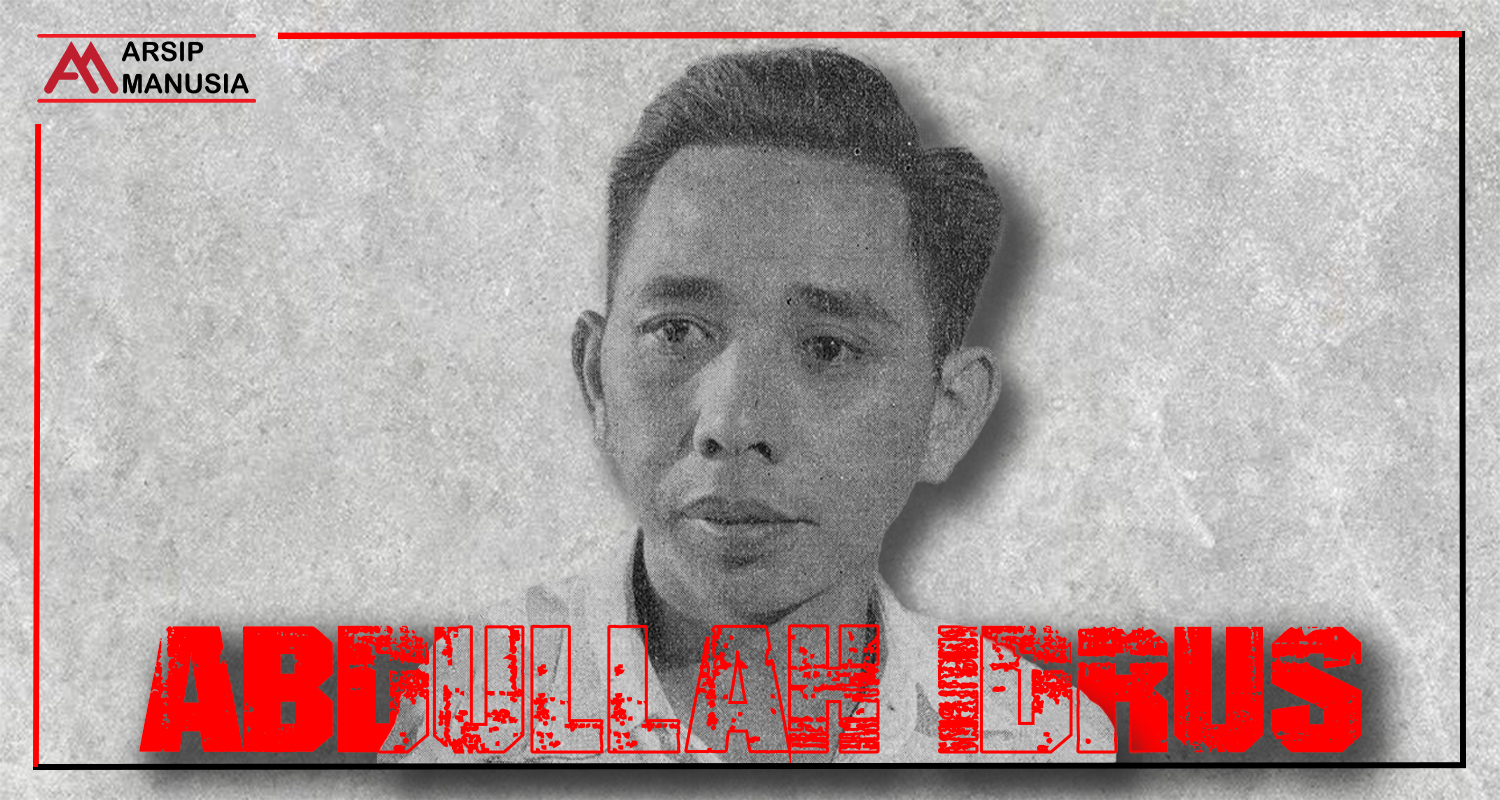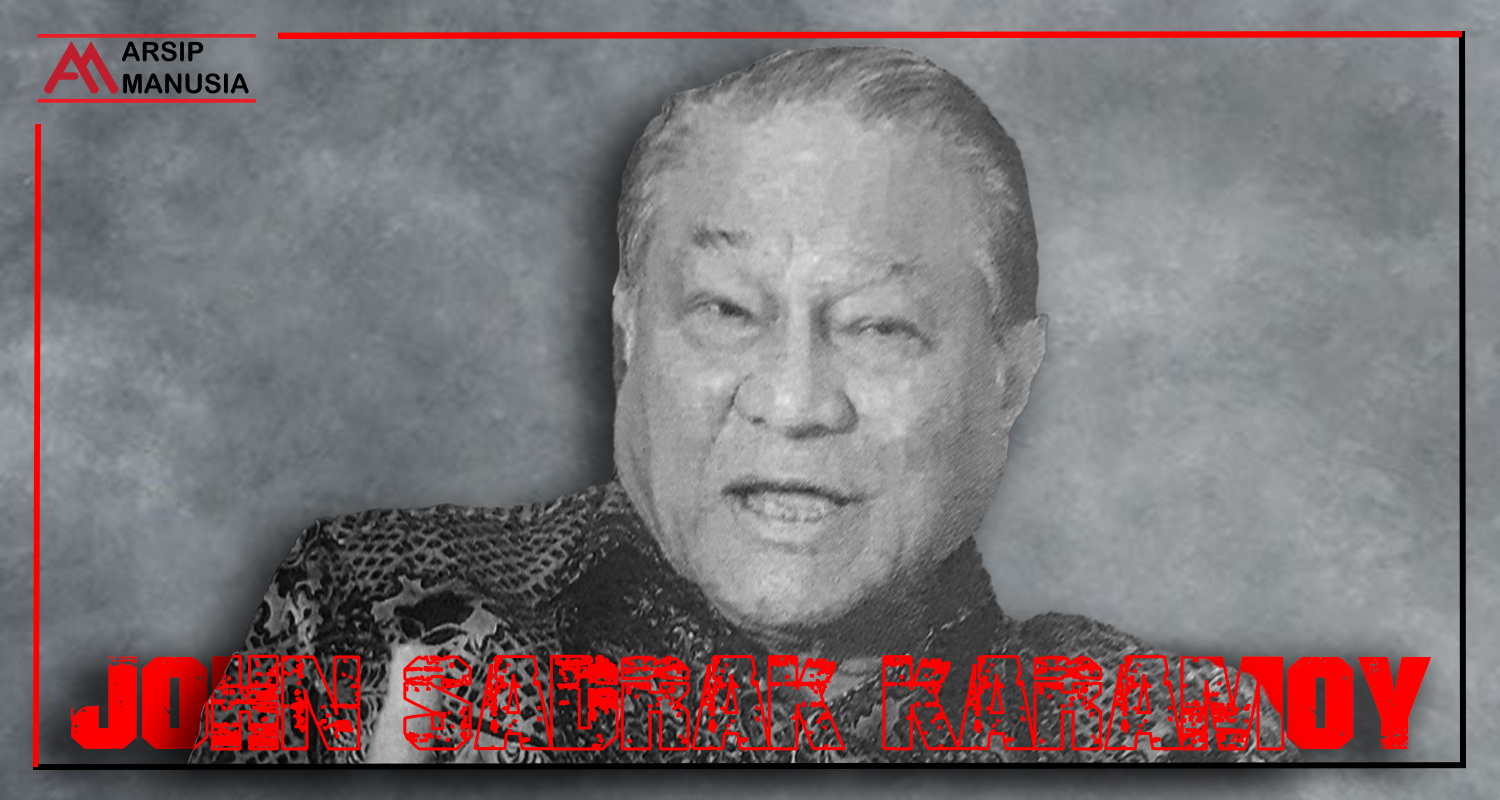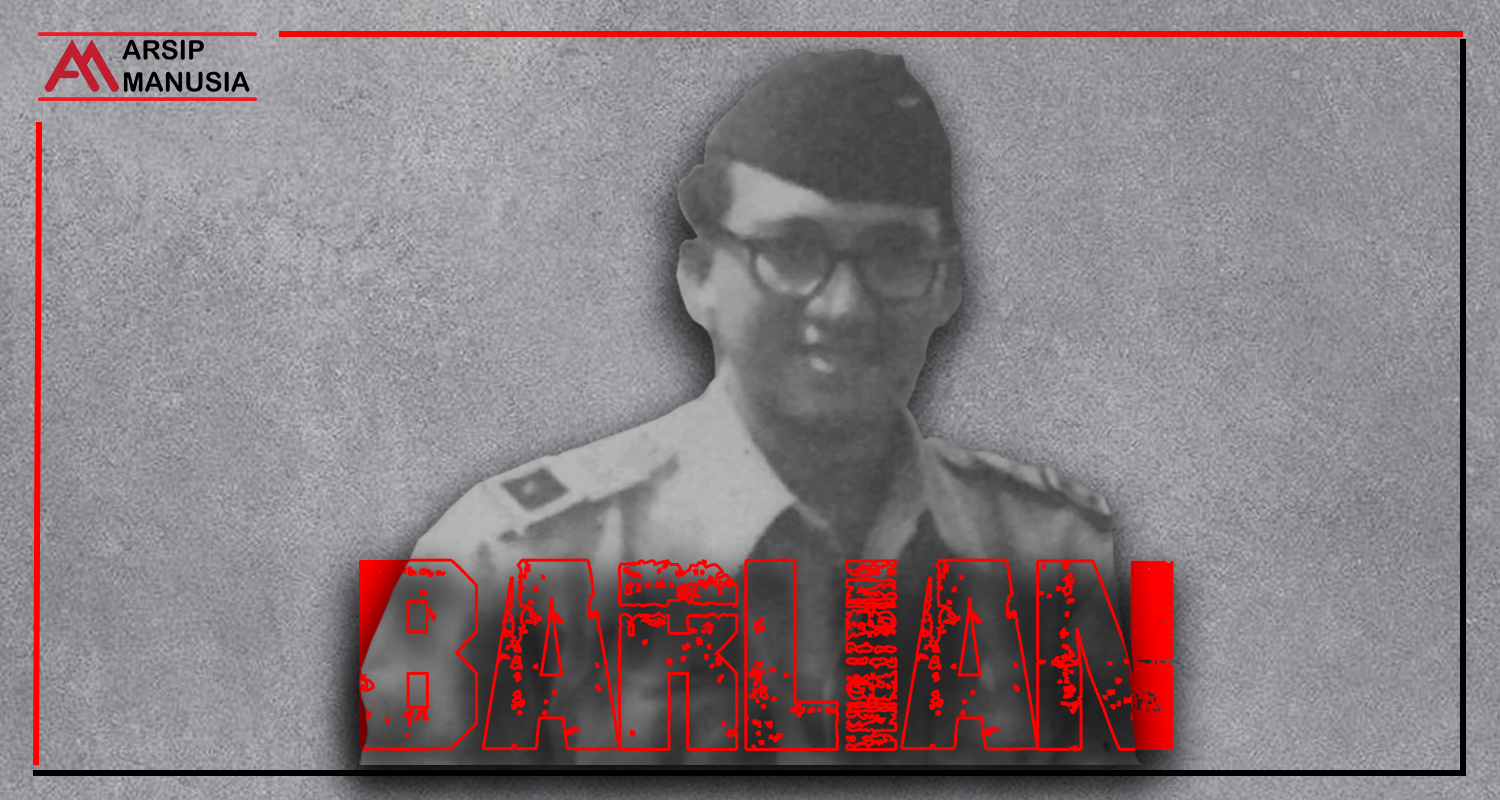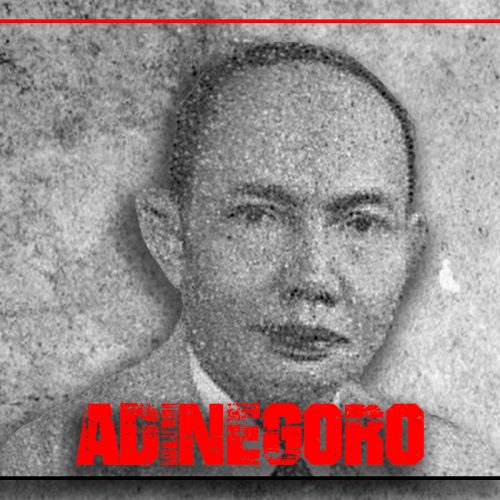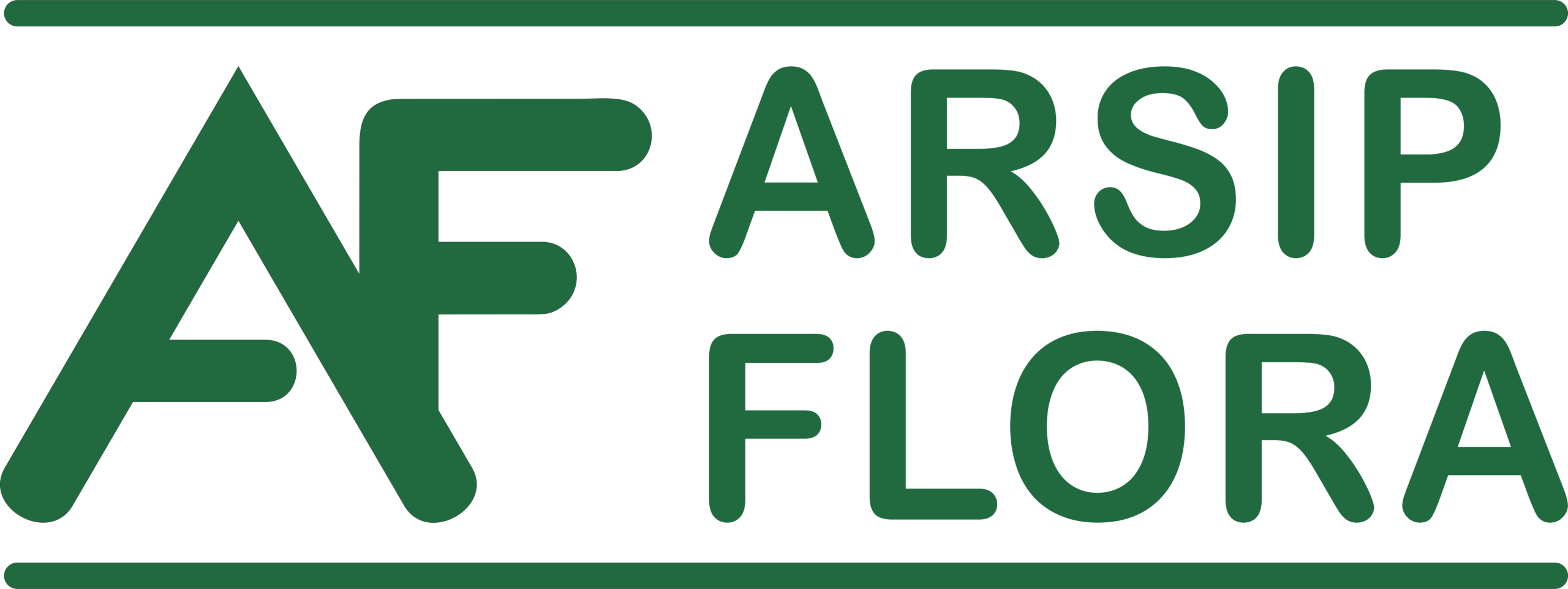Di awal abad ke-20, Indonesia belum bernama Indonesia. Nusantara masih berada di bawah bayang-bayang kekuasaan kolonial Belanda. Namun, di tengah suasana penuh keterbatasan itu, lahirlah tokoh-tokoh pergerakan yang kelak menjadi fondasi perjuangan kemerdekaan. Salah satunya adalah Haji Oemar Said Tjokroaminoto sosok yang dijuluki Guru Bangsa karena perannya mendidik dan menginspirasi generasi pejuang, termasuk Sukarno, Semaoen, hingga Kartosuwiryo.
Tjokroaminoto bukan sekadar pemimpin organisasi. Ia adalah orator ulung, penulis tajam, dan pemikir yang visioner. Perjuangannya di Sarekat Islam (SI) menandai salah satu bab terpenting dalam sejarah politik modern Indonesia.
Table of Contents
ToggleLatar Belakang Keluarga
H.O.S. Tjokroaminoto lahir pada 16 Agustus 1882 di Desa Bakur, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga priyayi, yaitu golongan bangsawan Jawa yang dekat dengan pemerintahan kolonial. Ayahnya, Raden Mas Tjokroamiseno, bekerja sebagai wedana (setingkat camat) di pemerintahan Hindia Belanda. Sementara ibunya, Raden Ayu Siti Aminah, berasal dari keluarga terpandang di Ponorogo.
Sebagai anak kedua dari dua belas bersaudara, Tjokroaminoto tumbuh dalam lingkungan yang disiplin, religius, namun tetap memberi ruang untuk pendidikan modern. Garis keturunan keluarganya memiliki hubungan dengan bangsawan Kesultanan Yogyakarta, yang membuatnya terbiasa berinteraksi dengan kalangan elit sekaligus memahami tata krama Jawa.
Lingkungan keluarga yang terhormat ini kelak membentuk kepribadiannya: berwibawa dalam berbicara, tegas dalam bersikap, dan pandai memadukan nilai tradisi dengan pemikiran pembaruan.
Pendidikan dan Awal Karier
Sejak kecil, Tjokroaminoto sudah menunjukkan kecerdasan di atas rata-rata. Orang tuanya menyadari potensi ini dan memberinya kesempatan menempuh pendidikan formal sebuah kemewahan pada masa itu, terutama bagi pribumi.
Ia mengawali pendidikannya di Sekolah Ongko Loro (Tweede Klasse School) di Madiun. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak pribumi yang berstatus sosial menengah ke atas. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Tjokroaminoto melanjutkan ke OSVIA (Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren) di Magelang, sekolah calon pegawai negeri pribumi yang bergengsi pada zamannya.
Namun, jalannya di OSVIA tidak mulus. Sifatnya yang tegas, berpikiran kritis, dan enggan tunduk pada perlakuan diskriminatif membuatnya kerap bersitegang dengan pihak sekolah. Akhirnya, ia memilih keluar sebelum lulus. Keputusan ini mencerminkan karakternya yang lebih mengutamakan prinsip daripada sekadar mengejar jabatan.
Meski tidak menamatkan OSVIA, Tjokroaminoto tidak berhenti belajar. Ia merantau ke Surabaya dan bekerja sebagai pegawai di pabrik gula, kemudian sebagai juru tulis di kantor pemerintah. Pengalaman bekerja di berbagai bidang ini membuatnya memahami realitas keras kehidupan kaum pekerja, sekaligus memperluas pandangannya tentang ketidakadilan sosial di bawah kolonialisme.
Kesadarannya semakin tumbuh bahwa perubahan besar tidak akan datang hanya dari dalam birokrasi. Ia mulai mendekat pada dunia pergerakan rakyat jalan yang kelak mengantarkannya menjadi salah satu pemimpin organisasi terbesar pada masanya.
Sarekat Islam
Tahun 1912 menjadi titik balik besar dalam hidup H.O.S. Tjokroaminoto. Pada masa itu, Sarekat Dagang Islam — organisasi yang awalnya berfokus pada kepentingan pedagang pribumi — berkembang pesat di bawah kepemimpinan Haji Samanhudi di Solo. Perubahan arah organisasi mulai terlihat ketika Sarekat Dagang Islam meluaskan tujuan, tak hanya mengurus perdagangan, tetapi juga mengangkat martabat umat Islam dan melawan diskriminasi kolonial.
Tjokroaminoto bergabung tak lama setelah organisasi ini bermetamorfosis menjadi Sarekat Islam (SI). Berkat kecakapannya dalam berbicara dan kemampuannya memimpin, ia dengan cepat dipercaya memegang jabatan penting. Tak butuh waktu lama, Tjokroaminoto terpilih sebagai ketua dan memindahkan pusat kegiatan SI ke Surabaya.
Di bawah kepemimpinannya, SI menjelma menjadi organisasi massa terbesar di Hindia Belanda. Anggotanya membengkak hingga ratusan ribu orang, terdiri dari pedagang, buruh, petani, hingga kalangan terpelajar. Tjokroaminoto menggunakan media massa sebagai alat perjuangan, antara lain dengan mendirikan surat kabar Oetoesan Hindia, yang menjadi corong aspirasi rakyat.
Sebagai orator, ia mampu membakar semangat rakyat dengan pidato-pidato yang menggabungkan nilai keislaman, rasa kebangsaan, dan seruan untuk menuntut keadilan. Panggung-panggung rapat umum SI selalu dipenuhi ribuan pendengar yang terpesona oleh gaya bicaranya yang tegas, tenang, dan penuh wibawa.
Namun, besarnya pengaruh SI juga menarik perhatian dan kecurigaan pemerintah kolonial. Gerak-gerik Tjokroaminoto diawasi ketat. Meskipun begitu, ia tetap konsisten mengarahkan perjuangan SI pada jalur politik yang damai, legal, dan beradab — meski kelak arah ini akan diuji oleh perpecahan di tubuh organisasi.
Perpecahan Sarekat Islam
Kebesaran Sarekat Islam di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto tak lepas dari tantangan internal. Memasuki dekade 1920-an, SI menjadi rumah bagi beragam aliran pemikiran. Di satu sisi, ada kelompok nasionalis dan Islamis yang ingin menjaga perjuangan sesuai garis agama dan politik kebangsaan. Di sisi lain, muncul pengaruh sosialisme dan komunisme yang mulai menyusup melalui tokoh-tokoh muda seperti Semaun dan Darsono.
Awalnya, Tjokroaminoto mencoba merangkul semua pihak. Baginya, persatuan umat dan rakyat adalah kunci kekuatan SI. Namun, perbedaan ideologi semakin tajam. Kelompok kiri yang condong ke komunisme menginginkan SI bergerak radikal melawan kolonialisme secara konfrontatif, sementara Tjokroaminoto tetap memilih jalur parlementer dan perlawanan damai.
Puncaknya terjadi pada Kongres SI di Madiun tahun 1923, ketika ketegangan memuncak. Kelompok kiri akhirnya memisahkan diri dan membentuk organisasi sendiri yang kelak menjadi bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Peristiwa ini menandai babak baru bagi SI, yang kemudian mengubah namanya menjadi Partai Sarekat Islam (PSI), lalu Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), untuk menegaskan identitas keislamannya.
Bagi Tjokroaminoto, perpecahan ini adalah pukulan berat. Namun, ia tetap melanjutkan perjuangan dengan menata kembali organisasi dan fokus pada pembinaan kader. Meskipun kekuatan massa SI menyusut, Tjokroaminoto tidak kehilangan kharisma dan pengaruhnya sebagai tokoh politik.
Guru Bangsa
Selain dikenal sebagai pemimpin politik, H.O.S. Tjokroaminoto memiliki peran yang jauh melampaui dunia organisasi — ia adalah pendidik bagi generasi pejuang kemerdekaan. Rumahnya di Gang Peneleh, Surabaya, menjadi tempat kos yang istimewa. Bukan sekadar tempat tinggal, melainkan pusat diskusi, pertukaran gagasan, dan pembentukan karakter para pemuda yang kelak menjadi tokoh besar Indonesia.
Di antara para penghuni rumah itu ada nama-nama yang kini tercatat dalam sejarah: Soekarno, yang kelak menjadi Presiden pertama RI; Semaoen, pemimpin buruh dan tokoh komunis awal; serta Kartosuwiryo, yang kemudian memimpin gerakan Darul Islam. Meskipun para muridnya kelak menempuh jalan perjuangan yang berbeda-beda, semuanya mengakui pengaruh besar Tjokroaminoto dalam membentuk wawasan dan kepemimpinan mereka.
Tjokroaminoto sering menasihati murid-muridnya dengan kalimat yang legendaris:
“Jika ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan berbicaralah seperti orator.”
Ia mengajarkan pentingnya penguasaan bahasa, pengetahuan luas, dan kemampuan berkomunikasi yang memukau. Metodenya sederhana namun efektif — membiasakan para pemuda membaca, berdiskusi, dan berani menyampaikan pendapat di depan umum.
Peran sebagai Guru Bangsa inilah yang membuat namanya tak pernah lekang, karena warisannya bukan hanya pada gagasan dan organisasi, tetapi juga pada manusia-manusia yang ia bentuk untuk melanjutkan perjuangan.
Akhir Hayat
Memasuki awal dekade 1930-an, kesehatan H.O.S. Tjokroaminoto mulai menurun. Meski tubuhnya melemah, semangatnya untuk membela rakyat tidak pernah padam. Ia masih aktif memimpin Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), menghadiri rapat-rapat, dan menyampaikan pidato yang selalu mengobarkan semangat persatuan.
Pada 17 Desember 1934, Tjokroaminoto wafat di Yogyakarta pada usia 52 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi para pengikutnya, baik dari kalangan SI maupun masyarakat luas. Jenazahnya dimakamkan di tanah kelahirannya, Ponorogo, disambut ribuan pelayat yang datang dari berbagai daerah.
Warisan Tjokroaminoto tidak hanya tercermin dalam jejak organisasi yang ia pimpin, tetapi juga dalam nilai-nilai perjuangan yang ia tanamkan: keberanian menentang ketidakadilan, komitmen pada persatuan, dan keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci kemerdekaan. Melalui murid-muridnya, gagasan dan semangatnya terus hidup hingga masa proklamasi dan seterusnya.
Kini, ia dikenang sebagai “Guru para Pendiri Bangsa”, seorang tokoh yang memadukan kepemimpinan visioner, integritas, dan kepiawaian membentuk kader. Namanya diabadikan dalam berbagai jalan, sekolah, dan monumen — menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari pengorbanan dan kerja keras tokoh-tokoh seperti dirinya.
Sumber:
- Kusuma, Hendra. H.O.S. Tjokroaminoto. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1985.
- Khikam, Fatikhul. Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto Mengenai Sosialisme Islam Tahun 1911–1934. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Metro, 2022.
- “Hadji Oemar Said Tjokroaminoto” tirto.id (Diakses pada 5 Agustus 2025)